Oleh: Soetrisno Bachir
Saudara-saudaraku sebangsa dan se-Tanah Air
Hari-hari ini hingga beberapa waktu mendatang sungguh merupakan saat-saat penting bagi Indonesia. Bukan saja karena pada tahun ini Indonesia memperingati Seabad Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, serta 10 tahun Reformasi. Lebih dari itu, saat-saat sekarang juga merupakan saat Indonesia menjelang menghadapi peristiwa dan keadaan besar yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan.
Pesta demokrasi 2009 akan segera dilangsungkan buat memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif, serta memilih presiden dan wakil presiden untuk masa`jabatan lima tahun ke depan. Hal tersebut akan benar-benar menentukan bagaimana wajah Indonesia mendatang. Tapi tidak berarti bahwa persoalan paling penting bagi Indonesia adalah siapa yang akan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden mendatang. Lebih dari itu adalah ke mana kepala negara terpilih bersama seluruh bangsa ini akan membawa Indonesia ke depan, menghadapi persoalan dunia yang akan semakin menantang. Pertanyaan itulah yang sekarang harus dijawab seluruh bangsa ini, dan tentu juga oleh pemimpinnya.
Masalah politik, ekonomi, sosial, dan bahkan lingkungan yang dihadapi dunia telah sedemikian kait mengait tanpa terpisahkan. Sekat-sekat antarbangsa telah semakin menipis sebagaimana sekat antarbudaya, bahkan antardisiplin ilmu pengetahuan. Hubungan politik antarnegara secara umum memang telah semakin mencair. Tetapi pertikaian negara model lama masih terjadi seperti pada krisis Rusia-Georgia sekarang ini. Masalah Palestina yang menjadi persoalan paling rawan bagi upaya mewujudkan perdamaian dunia, belum pula terselesaikan. Konflik politik internal suatu negara seperti di Myanmar serta Zimbabwe sedikit banyak juga berpengaruh pada stabilitas dunia.
Di bidang ekonomi, ancaman kelesuan yang menbayangi perekonomian Amerika terus dicermati para ekonom, mengingat pengaruhnya yang besar bagi ekonomi dunia. Memang ada optimisme bahwa perekonomian Amerika akan segera membaik setelah Tahun 2009 yang juga berarti membaiknya perekonomian dunia. Tetapi saat ini, puncak kelesuan ekonomi tersebut belum terlewati. Kemajuan ekonomi Asia yang dimotori oleh pertumbuhan ekonomi China dan India diperkirakan akan segera mengubah peta perekonomian global. Namun laju pertambahan penduduk dunia, menipisnya cadangan minyak bumi, serta bayang-bayang keterbatasan kemampuan dunia dalam penyediaan pangan perlu diantisipasi.
Masalah sosial yang terkait dengan perekonomian yang masih membayangi dunia adalah kemiskinan. Masalah ini juga masih merupakan persoalan mendasar Indonesia sehingga badan-badan dunia menekankan agar pengentasannya diprioritaskan. Sebanyak 34,96 juta warga miskin menurut ukuran pemerintah, atau lebih dari dua kali lipat jumlah itu menurut ukuran Bank Dunia, bukan angka yang sedikit untuk diabaikan. Tingkat partisipasi pendidikan yang rendah pada sebagian masyarakat dunia juga merupakan persoalan bagi Indonesia.
Tingkat kematian ibu dan balita, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan bahkan ancaman Tuberculosis, yang cenderung luput dari perhatian publik, tetap merupakan masalah serius bagi dunia. Human traficking atau perdagangan manusia, yang sepatutnya tidak terjadi lagi di tingkat keberadaban dunia saat ini, telah berkembang ke tingkat yang memprihatinkan. Sementara penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang dalam genggaman jaringan sindikasi global semakin sulit teratasi.
Pemanasan global, sebagaimana terungkap dengan jelas dalam pertemuan dunia di Bali akhir 2007 lalu, merupakan persoalan yang akan semakin mengemuka di tahun-tahun mendatang. Mencairnya Kutub akibat pemanasan global tersebut akan dapat langsung berpengaruh pada kawasan-kawasan kepulauan seperti Indonesia. Tenggelamnya pulau akan mengurangi luas Indonesia, karena wilayah kedaulatan negara didasarkan pada titik pulau terluarnya. Perusakan hutan yang berlangsung sangat pesat, terutama hutan-hutan hujan tropis, telah menghancurkan paru-paru dunia. Kelangkaan air bersih juga telah menjadi masalah baru yang belum pernah dihadapi dunia di masa-masa yang lampau.
Benturan antarbangsa juga masih akan terjadi. Benturan itu tak selalu berupa benturan besar seperti ‘Benturan Peradaban’ yang diramalkan Samuel Huntington. Perbedaan sudut pandang antara paham kebebasan bereskspresi dengan penghormatan terhadap keyakinan beragama dapat menajam, dan bahkan menyakitkan. Itu yang terjadi pada kasus Kartun Nabi Muhanmad di koran Denmark. Persoalan tersebut telah memunculkan pertanyaan: Di mana batas kebebasan dengan penghargaan pada keyakinan yang berbeda? Dalam ekonomi, benturan antara dominasi perusahaan-perusahaan multi nasional dengan kepentingan lokal khususnya dalam pengelolaan sum berdaya alam, juga tak terhindarkan.
Persoalan yang semakin kompleks itulah yang dihadapi dunia hingga beberapa tahun ke depan. Persoalan dunia itu pula yang harus dihadapi Indonesia mendatang, di samping di dalam negeri yang tidak kalah rumitnya. Tantangan besar tersebut tak cukup dijawab dengan sekadar memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan Tahun 2009 nanti.
Saudaraku!
Bangsa-bangsa lain telah bersiaga menghadapi dunia baru yang penuh tantangan tersebut. Filipina telah menyebarkan para pekerja menengahnya untuk mengisi pasar kerja di seluruh dunia. Thailand tengah membangun restoran-restoran masakan Thai pada hampir semua kota penting di berbagai negara untuk menjadi ujung tombak pemasaran pariwisatanya. India semakin mengukuhkan diri sebagai pusat pengembangan dan layanan Teknologi Informasi global. Singapura terus memperkuat posisi sebagai sentra jasa, keuangan, serta budaya terpenting di kawasan barat Asia Pasifik. Jepang dan bahkan Korea Selatan telah mengokohkan kedudukannya sebagai kekuatan utama dunia dalam industri mobil dan elektronika.
Di hadapan upaya besar bangsa-bangsa tetangga itu, apa yang akan diperbuat Indonesia? Apakah Indonesia cukup puas dengan menjual murah enerjinya seperti batubara dan gas, sementara negara lain seperti China mendapat berkah nilai tambah enerji itu pada perekonomiannya? Peradaban baru seperti apa yang harus dibangun bangsa ini agar dapat menghadapi masa depan dengan tegak? Budaya macam apa yang perlu dikembangkan yang sesuai untuk menopang peradaban baru tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawaban dari seluruh anak bangsa.
Dalam perekonomian, bangsa ini jelas bukan apa-apa dibanding dengan raksasa Amerika Serikat, Jepang, serta China. Indonesia bahkan masih kalah dibanding saudara serumpun Malaysia. Perbandingan komposisi perekonomian antar negara menunjukkan dengan jelas ketertinggalan kita. Kontribusi pertanian pada perekonomian secara keseluruhan masih sebesar 43,3 persen, sementara di China tinggal 11,3 persen. Sebaliknya, kontribusi industri dalam perekomian Indonesia baru 18 persen, sedang di China telah mencapai 48,6 persen. Di negara-negara maju, kontribusi terbesar pada ekonomi adalah dari sektor jasa seperti di Amerika (78 persen) serta Jepang (72 persen). Sebagai negara berkembang, India bahkan telah mampu mengandalkan jasa sebagai motor penggerak ekonominya. Jasa menyumbang 52 persen dari nilai perekonomian India yang berarti negara tersebut telah mampu mengandalkan kekuatan sumberdaya manusianya untuk meraih kemajuan.
Angka-angka tersebut bukan sekadar mencerminkan posisi ekonomi Indonesia dibanding dengan negara-negara besar dunia lainnya. Lebih dari itu, angka-angka itu juga menggambarkan wajah peradaban bangsa ini sekarang. Kontribusi pertanian yang tinggi serta peran jasa yang rendah menunjukkan bahwa Indonesia masih mengandalkan sumberdaya alam dan belum pada sumberdaya manusia dalam perekonomian. Kenyataan itu juga mencerminkan bahwa peradaban Indonesia sekarang masih tergantung pada budaya tradisional. Padahal budaya tradisional tak selalu siap memenuhi tuntutan peradaban masa depan.
Ketidaksiapan budaya bangsa untuk menyambut tantangan masa depan telah muncul dalam Polemik Kebudayaan di tahun 1930-an. Achdiat Karta Mihardja dalam pengantar kumpulan polemik itu menyebut bahwa sisa budaya feodal berpengaruh besar pada jiwa dan budaya bangsa. Pada masyarakat feodal, kehidupan ekonomi, sosial, dan politik dikendalikan sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekuasaan sangat besar. Masyarakat kebanyakan harus menerima keadaan yang apa adanya, termasuk menanggung kemiskinan. Itulah yang membuat jiwa mati dan bangsa ini menjadi bangsa yang statis. Kalah dalam kehidupan, masyarakat lalu menghibur diri dengan hal-hal yang bersifat takhayul dan mistis.
Untuk membongkar sifat statis tersebut, Sutan Takdir Alisjahbana mengajak bangsa untuk mengadopsi nilai-nilai Barat. Baginya, bangsa ini harus menjadi bangsa yang dinamis, maju, serta berani memperjuangkan kepentingan sendiri. Karakter itu disebutnya ada pada bangsa-bangsa Barat sehingga Barat menguasai peradaban dunia beberapa abad terakhir. Gagasan mengadopsi budaya Barat itu mengundang reaksi para budayawan yang yakin pada kekuatan budaya lokal, sehingga memunculkan polemik serupa yang pernah terjadi di Jepang. Di Jepang, setelah Restorasi Meiji 1868 polemik demikian melahirkan sintesa budaya yang menjadi dasar peradaban baru Jepang. Yakni peradaban moderen yang membawa kemajuan namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai budaya asli Jepang, Masakan ‘teriyaki’ dan ‘yakiniku’, serta prinsip manajemen Kaizen merupakan hasil sintesa budaya tersebut.
Di Indomesia, Polemik Kebudayaan dahulu itu belum menghasilkan sintesa budaya yang dapat membawa pada peradaban baru. Prioritas perjuangan saat itu untuk menyiapkan kemerdekaan, serta hiruk pikuk Perang Dunia II, membuat polemik penting tersebut tak berlanjut. Maka karakter bangsa yang dirisaukan para pemimpin tiga perempat abad silam, sampai sekarang belum hilang. Sisa warisan budaya feodal serta karakter statis terasa masih ada pada bangsa ini. Itu yang membuat Indonesia sulit mewujudkan cita-cita kemerdekaan seperti memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menciptakan perdamaian dunia. Karakter itu pula yang membuat Indonesia tidak siap bersaing di tingkat global dalam menghadapi masa depan yang menantang.
Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air!
Ketidaksiapan budaya bangsa dalam menghadapi tantangan global harus ditebus dengan harga yang mahal. Banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan atas`ketidaksiapan itu seperti hilangnya semangat kebangsaan, tidak tegaknya hukum, moralitas yang rusak, hingga lemahnya daya saing bangsa. Pengorbanan tersebut sebenarnya tidak perlu karena bangsa ini telah mempunyai pondasi berupa nilai-nilai spiritualitas yang mengajarkan agar manusia bergantung dan berserah diri hanya pada Tuhan Yang Maha Esa, dan bukan pada lainnya. Itulah kunci sukses manusia, dan pada akhirnya juga kunci sukses masyarakat serta bangsa.
Tetapi pondasi itu rusak oleh budaya feodal yang menekankan anggapan bahwa pemimpin adalah Wakil Tuhan di bumi ini, sehingga jika patuh pada Tuhan maka harus patuh pada pemimpin. Tanpa pemahaman kokoh pada nilai-nilai kebenaran, masyarakat lalu memasrahkan hidup pada pemimpin. Ungkapan ‘pejah gesang nderek panjenengan’ yang berarti ‘hidup mati ikut Anda (pemimpin)” menjadi ungkapan yang berakar kuat di masyarakat Jawa sebagai suku bangsa terbesar di Indonesia. Namun pandangan seperti itu bukan hanya menyebar di Jawa, melainkan hampir di seluruh wilayah Nusantara.
Masyarakat menjadi terbiasa merendahkan dirinya sendiri sebagai ‘kawulo’ atau ‘hamba’ menurut istilah Melayu. Dalam kultur feodal Melayu, masyarakat tak cukup dengan hanya bersimpuh dan menyembah pemimpin. Masyarakat juga terbiasa mengucapkan istilah ‘Daulat Tuanku’ sebagai ungkapan siap menerima perintah. Seolah-olah hanya Sang Tuan yang berdaulat, sedangkan dirinya sendiri tidak. Masyarakat menjadi sangat bergantung pada pemimpin, termasuk pemimpin adat dan keagamaan, walaupun tak jarang pemimpin yang memanfaatkan kepatuhan pengikutnya untuk kepentingannya sendiri.
Sikap ‘pasrah’ dan ‘nrimo’ pada keadaan merupakan sikap umum masyarakat luas. Kebanyakan orang memilih menerima keadaan apa adanya dibanding berusaha keras meraih kehidupan yang lebih baik. Padahal Nabi mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jika hari ini sama dengan kemarin berarti merugi, sedangkan bila hari ini lebih buruk dari kemarin berarti celaka. Namun ajaran Nabi itu tidak dituruti. Banyak orang tak mau berusaha mengatasi kemiskinannya sendiri karena menganggap kemiskinan itu merupakan takdir.
Dalam kultur demikian, masyarakat mengutamakan keselarasan dan harmoni dibanding kepentingan menyangkut materi. Kepentingan materi seolah-olah hanya akan mengganggu harmoni karena itu harus dihindari. Priyayi lebih dihargai dibanding saudagar yang memakmurkan negeri. Di lingkungan masyarakat tradisional, cara pandang dan sikap hidup begitu dapat dipahami. Adanya kebersamaan yang hangat, budaya tolong-menolong yang kuat, serta alam yang murah hati memang dapat membantu masyarakat mengatasi kesulitan, termasuk mengurangi beban kemiskinan. Tampaknya tidak ada persoalan bagi bangsa dengan memiliki budaya seperti itu. Namun setelah keadaan bangsa dan dunia berubah baru terbukti bahwa budaya yang ada tidak mampu menghadapi tantangan baru.
Alam tidak lagi dapat bermurah hati akibat ledakan penduduk, keserakahan, serta ketidakpedulian manusia dalam mengelola. Sementara itu, budaya-budaya lokal harus berbenturan dengan budaya global yang masuk ke seluruh pelosok negeri ini akibat revolusi teknologi komunikasi dan transportasi. Budaya global yang menawarkan kemajuan, kemudahan, kenyamanan, serta gengsi yang dianggap lebih, dengan cepat diadopsi menjadi dambaan baru masyarakat. Terjadi lompatan orientasi masyarakat dari orientasi harmoni ke orientasi materi. Lompatan yang tidak dipersiapkan serta dalam waktu yang relatif singkat tersebut menimbulkan akibat yang tidak sedikit.
Terjadinya guncangan budaya (cultural shock) menjadi tak terhindarkan. Dengan budaya nrimo dan memasrahkan jiwa raga pada pemimpin, masyarakat tak terlatih memperjuangkan kepentingan sendiri yang bersifat materi. Mempercakapkan urusan materi bahkan cenderung dipandang sebagai hal rendah. Sekarang tiba-tiba materi menjadi dambaan baru, seolah-olah merupakan hal terpenting dalam kehidupan. Sebagaimana biasanya kecintaan pada hal-hal baru yang sering berlebihan, orientasi baru terhadap materi saat ini juga cenderung lebih dari wajar. Tanpa tersadari bangsa ini bergeser dari bangsa idealistis menjadi bangsa materialistis. Di antara para pemerhati bahkan ada yang menyebut Indonesia saat ini merupakan salah satu bangsa paling materialistis di dunia.
Penilaian itu belum tentu benar. Tetapi simbol-simbol materi memang menjadi dambaan baru masyarakat yang selama ini cenderung pasrah dan tidak siap bekerja keras untuk mendapatkan materi dengan cara semestinya. Berbagai kalangan masyarakat mulai berlomba mengakumulasi simbol-simbol keberhasilan materi dengan berbagai macam cara. Jalan pintas`menjadi pilihan yang biasa. Lembaga-lembaga publik yang semestinya didedikasikan buat melayani masyarakat bahkan banyak dibelokkan buat memenuhi kepentingan pribadi. Itu yang menjelaskan mengapa korupsi terus meningkat tak teratasi meskipun upaya untuk mencegahnya juga dilakukan.
Bias kepentingan pribadi membuat birokrasi, politik, hukum, dan kelembagaan lain yang dibangun untuk kepentingan publik tak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Birokrasi belum efektif membantu masyarakat untuk menjadi masyarakat maju, tapi lebih tersibukkan dengan formalitas menangani program-program yang normatif. Politik belum sepenuhnya didedikasikan untuk memperjuangkan kepentingan umum, dan masih cenderung menjadi alat berebut kekuasaan seperti yang sering ditudingkan. Hukum terasa lebih berpihak pada yang kuat dibanding pada kebenaran. Dunia akademis dan media yang diharapkan dapat lebih berperan dalam menjaga nilai-nilai bangsa, tak jarang terseret pula oleh kepentingan praktis perorangan di belakangnya.
Mengagungkan simbol-simbol materi telah membawa masyarakat pada perilaku konsumtif dan bukan produktif, juga pada sikap yang ingin serba gampang dibanding kemauan berusaha. Maraknya remaja yang terjun menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) beberapa waktu terakhir ini bukan saja didorong oleh faktor kemiskinan, melainkan juga oleh keinginan perilaku konsumtif dan hidup enak secara gampang. Tidak sedikit dari mereka yang bukan berasal dari kalangan yang benar-benar miskin. Banyak lagi masalah sosial lain yang juga disebabkan dorongan yang melebihi kewajaran dalam urusan materi tersebut. Rapuhnya nilai-nilai keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya kriminalitas, hilangnya kejujuran, serta melunturnya kepercayaan pada sesama merupakan akibat dari orientasi materi secara berlebihan tersebut. Padahal, seperti dikemukakan Francis Fukuyama, rasa percaya (trust) merupakan modal sosial paling berharga bagi kemajuan suatu bangsa.
Dengan latar keadaan seperti itu, dapat dipahami bila Indonesia menjadi konsumen peradaban dunia. Peradaban Indonesia saat ini menjadi peradaban yang terwarnai dan bukan mewarnai peradaban dunia. Budaya yang mendominasi peradaban dunia dengan cepat diadopsi oleh bangsa ini. Namun sesuai dengan kecenderungan masyarakat baru yang ingin serba gampang, budaya yang teradopsi tersebut lebih merupakan budaya yang bersifat materialistis, konsumtif, serta hedonistis. Maraknya pornografi dan pornoaksi, serta berkembangnya sikap dan perilaku liberal yang permisif menggambarkan derasnya pengaruh budaya global. Sedangkan nilai-nilai yang membuat Barat menguasai peradaban global seperti sikap mandiri, kepatuhan pada aturan dan hukum, serta keberanian dan konsistensi untuk mengeksplorasi hal-hal baru bagi kepentingan bersama, justru tidak diadopsi bangsa ini.
Memang tidak sedikit anak-anak bangsa yang tetap mampu menjaga kejernihan kesadaran sehingga tidak larut dalam keadaan yang ada. Di setiap tempat masih dapat ditemui pribadi-pribadi seperti suster apung Rabiah yang terus berbuat mengabdi untuk sesama; pemuda seperti Firman yang tak mengeluh dan memilih gigih berwiraswasta; atau pelajar yang bertekun dengan ilmu untuk mengangkat nama Indonesia di mata dunia seperti Stefano.
Namun di antara sosok-sosok berkesadaran itu, lebih banyak lagi yang tenggelam dalam sikap pragmatis materialistis yang menghalalkan cara. Tidak sedikit tokoh masyarakat yang tidak malu berebut kekuasaan demi uang, pejabat yang tidak malu mencari komisi atau malah korupsi, hingga penjaga keadilan yang tidak malu menerima imbalan dari perkara yang tengah diadilinya. Pada merekakah bangsa ini akan mempercayakan kepentngan untuk mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata dunia? Pada generasi baru yang hanya mau hidup enak tanpa harus berusaha keraskah bangsa ini mempercayakan masa depannya? Peradaban yang ada di Indonesia saat ini sungguh tidak lagi memadai untuk membangun bangsa yang bermartabat dan sejahtera sesuai dengan perkembangan dunia.
Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air!
Dunia semakin konvergen. Budaya antar bangsa telah semakin menyatu satu sama lain. Dalam penyatuan tersebut, budaya yang kuat akan mewarnai peradaban baru dunia, sedangkan budaya yang lemah akan lenyap dari khazanah peradaban. Bangsa-bangsa berjaya, yang mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya adalah bangsa-bangsa yang budayanya menguasai dan bukan dikuasai peradaban dunia. Peradaban Indonesia masih jauh dari posisi untuk tidak larut, apalagi untuk dapat mewarnai peradaban dunia. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun peradaban baru.
Semangat kebangsaan merupakan kunci untuk membangun peradaban baru bangsa. Semangat itulah yang melahirkan sikap dan perilaku serempak bangsa dalam berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Jepang punya semangat Bushido yang terjaga oleh kekaisaran. Ketika Kaisar menyatakan ‘beras Jepang yang terenak dan terbaik’, seluruh bangsa Jepang serempak menjadikan beras Jepang memang beras terenak dan terbaik, serta tak akan menyentuh beras asing sekalipun harganya jauh lebih murah. Amerika Serikat juga punya American Dream yang menempatkan bangsa dan negaranya sendiri sebagai pemimpin dunia. Sebuah ‘mimpi’ yang terbukti mampu membuat seluruh bangsa Amerika bergerak serempak untuk memimpin dunia. China menempuh jalan yang berbeda. Mao Zedong menggunakan komunisme untuk membongkar sistem feodal masyarakatnya untuk dapat membangun China baru.
Indonesia harus menemukan jalannya sendiri untuk bangkit dan menjadi bangsa maju. Untuk itu, bangsa ini perlu segera membangun peradaban baru yang sesuai dengan kebutuhan masa depan, yang membuat masyarakatnya aktif, dinamis, serta berdaya saing tinggi dalam berhadapan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Budaya lama warisan budaya feodal yang membuat masyarakat pasrah, memandang rendah urusan materi, serta puas mengekor para pemimpinnya, tidak lagi dapat diandalkan. Sebaliknya, budaya sekarang sebagai budaya pancaroba yang materialistis, konsumtif, dan mementingkan atribut dibanding substansi, juga bukan pilihan budaya yang tepat. Indonesia memerlukan budaya baru yang didasarkan pada nilai-nilai idealistik, yang dapat menghubungkan kepentingan mewujudkan harmoni serta kepentingan materi sekaligus.
Untuk dapat melangkah maju tersebut, jalan Jepang bukan pilihan tepat bangsa ini karena Indonesia bukan bangsa homogen dan tidak dipersatukan oleh nilai-nilai budaya tunggal yang berakar panjang dalam sejarahnya. Meskipun sama-sama terbangun oleh masyarakat yang beragam, Indonesia bukan pula Amerika yang dibangun oleh kesamaan nilai para imigran yang mematikan nilai-nilai budaya asli. Keragaman Indonesia terbangun oleh budaya yang mayoritas memang berakar di bumi pertiwi ini, dan bukan oleh pendatang. Bukan pula jalan China yang dapat ditempuh Indonesia karena gerak bangsa ini tak akan pernah diserempakkan berdasar penyeragaman yang mengorbankan kalangan minoritas. Peradaban baru Indonesia justru harus dibangun atas kesadaran kebhinekaan Indonesia seperti yang telah ditunjukkan para pendiri bangsa.
Kesadaran kebhinekaan Indonesia selalu ada dalam setiap kelompok masyarakat. Semua yang berkesadaran kebhinekaan itulah yang dapat membangun Indonesia menuju hari depan lebih baik. Mereka adalah sosok-sosok jernih yang kritis terhadap realitas yang berkembang sekaligus bersikap positif untuk terus mencari jalan keluar persoalan bangsa. Mereka tidak mengorbankan nilai-nilai ideal yang diyakininya demi kepentingan pribadi. Namun mereka akan selalu berbuat untuk kebaikan bersama. Mereka ada di mana saja, bisa di kalangan birokrasi, militer, politisi, pengusaha, pedagang kaki lima, petani, nelayan, buruh, pekerja angkutan, artis, guru, tokoh agama atau siapapun. Mereka bisa berasal dari suku apa saja, agama apapun, juga dari kelompok kepentingan apapun. Mereka itulah para ‘Simpul Kesadaran’ bangsa, yang perlu dipertautkan dalam jejaring untuk dapat membangun peradaban baru Indonesia.
Untuk membangun peradaban baru Indonesia, para ‘Simpul Kesadaran’ perlu menggali nilai-nilai budaya lokal di lingkungan masing-masing. Nilai-nilai budaya yang relevan dengan tuntutan peradaban masa depan harus dibangkitkan dan diperkuat. Sebaliknya nilai budaya yang sudah tidak relevan seperti budaya feodal, takhayul, serta mistis perlu segera ditempatkan sebagai bagian dari sejarah. Nilai-nilai budaya lokal yang relevan dengan kebutuhan masa depan itulah yang harus dipertemukan, dan bila perlu dibenturkan satu sama lain, bahkan juga dengan sisi positif budaya global yang mengalir deras ke seluruh pelosok negeri ini. Pertautan antar nilai budaya, baik lokal maupun global tersebut akan melahirkan sintesa budaya yang dapat menjadi pijakan kokoh bagi peradaban baru Indonesia.
Memang bukan pekerjaan mudah bagi jejaring ‘Simpul Kesadaran’ untuk membangun sintesa budaya dan terus mengawalnya agar terbentuk peradaban baru. Bukan hal mudah bagi para ‘Simpul Kesadaran’ untuk mengajak orang-orang sekitarnya, yang masih larut dalam kepentingannya sendiri, untuk bersama-sama membangun keberadaban baru di lingkungan masing-masing. Baik keberadaban baru dalam politik, bitrokrasi, dan hukum; keberadaban baru masyarakat Jawa, Papua, hingga keturunan Tionghoa; juga keberadaban baru komunitas agama serta adat. Tetapi dengan segala tantangannya hal tersebut harus dilakukan, dan memang mungkin dilakukan.
Keterpaduan aspek jiwa serta profesionalitas diperlukan sebagai pilar utuhnya bangunan peradaban baru Indonesia, sebagaimana utuhnya keterpaduan “Otak Kanan” dan “Otak Kiri” dalam kehidupan. Jiwa menjadi seperti api yang akan terus mengobarkan semangat kebaikan dalam berbangsa dan bernegara apapun kesulitan yang menghadang. Adapun profesionalitas yang mengandung nilai-nilai kompetensi, integritas, serta kapasitas manajemen akan memastikan bahwa setiap langkah bangsa di masa depan akan selalu dapat dipertanggungjawabkan menurut ukuran apapun, termasuk ukuran-ukuran universal. Kesatuan jiwa dan profesionalitas itu perlu mewarnai seluruh proses berbangsa dan bernegara, baik dalam pengelolaan negara maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Selain kuat dalam jiwa dan profesionalitas, peradaban baru Indonesia tentu harus pula memiliki orientasi global, teknologi, dan keriwausahaan yang kuat. Pembekalan orientasi global akan membantu para Tenaga Kerja Indonesia sebagai ‘pahlawan devisa bangsa’ untuk lebih mampu bersaing dengan para pekerja bangsa lain dalam pasar tenaga kerja menengah bahkan atas. Orientasi global akan menjadikan putra-putra bangsa bukan cuma ‘jago kandang’ melainkan juga akan siap menjelajah luasnya dunia. Teknologi menjadi keharusan untuk dikuasai agar dapat tegak di antara bangsa-bangsa besar dunia. Sedangkan kewirausahaan bukan saja mendinamiskan, melainkan juga akan mengantarkan bangsa pada kemakmuran.
Untuk membangun peradaban baru tersebut, pendidikan merupakan jalan utama untuk menyebarkan nilai-nilai penopang peradaban baru Indonesia. Keteladanan para ‘Simpul Kesadaran’ untuk membebaskan lingkungan kepemimpinan masing-masing dari pengaruh budaya lama yang feodal maupun dari budaya pancaroba sekarang yang materialistis merupakan proses pendidikan terbaik bagi publik. Apalagi bila ditopang dengan pengembangan sistem yang memperkuat profesionalitas masyarakat. Pengembangan wilayah dan penataan kota sehingga teratur, bersih, serta manusiawi juga merupakan sarana pendidikan publik yang efektif untuk membangun peradaban baru. Lee Kuan Yew mengawali pembangunan Singapura dengan mengembangkan komplek perumahan moderen pada tahun 1964, Langkahnya tersebut bukan hanya membuat Singapura maju secara fisik, namun juga berpengaruh pada sikap dan perilaku masyarakatnya sekarang.
Sebagai bagian pembelajaran untuk mengadopsi nilai-nilai peradaban baru, seremoni dan acara publik penting untuk direvitalisasi. Upacara dan acara pemerintah yang kaku dan mekanisitis yang terwarisi dari budaya birokrasi feodal sudah saatnya lebih dicairkan agar efektif buat menyampaikan pesan yang diharapkan. Tak sedikit acara adat yang perlu disegarkan agar menjadi keriaan yang dapat membangkitkan semangat masyarakat serta terbebas dari simbol-simbol mistis yang mengada-ada dan membodohkan masyarakat Spiritualitas yang kuat yang dapat menjadi pijakan bangsa selalu spiritualitas`yang didasarkan atas kesadaran rasional, seperti Bushido di Jepang. Bukan spiritualitas yang berlandaskaan pada mistis. Maka bela diri bangsa-bangsa seperti Jepang dan Korea juga lebih bertumpu pada kekuatan jiwa, dan tak dihubung-hubungkan dengan mistis seperti umumnya bela diri bangsa ini.
Pengajaran agama juga memiliki arti penting untuk membangun peradaban baru Indonesia. Seperti seruan Bung Karno agar umat mengambil ‘api’ dan bukan ‘abu’ agama, pengajaran agama harus mampu memerdekakan jiwa dan membangkitkan etos bangsa. Adapun pembangunan peradaban baru yang perlu ditempuh melalui pendidikan formal adalah pengembangan keteladanan guru, pembiasaan perilaku baik oleh lingkungan sekolah, serta pengajaran yang bermuatan keterampilan hidup (life skills). Pengajaran tentang keterampilan hidup di sekolah terbukti membuat masyarakat lebih mampu mengelola kesehatan diri, pandai mengelola ekonomi keluarga, serta efektif dalam berkomunikasi dan negosiasi.
Pembangunan peradaban baru yang diperlukan Indonesia untuk maju juga tak boleh terlepas dari pondasi yang telah dibangun para pendiri bangsa serta pemimpin terdahulu. Presiden Soekarno telah berjasa membangun rumah peradaban baru tersebut dalam bentuk Pancasila yang mempersatukan kebhinekaan bangsa. Presiden Soeharto berjasa mengamankan rumah Pancasila itu dari kehancuran agar Indonesia dapat membangun. Hanya karena kesalahan politiknya, jasa itu menjadi terabaikan dan Pancasila tidak lagi dihargai secara semestinya oleh bangsa. Indonesia era baru harus mampu membangkitkan kembali Pancasila dan mendinamiskannya agar bangsa dapat mewujudkan kemakmuran yang didambakan masyarakat.
Akhirnya, upaya besar membantu Indonesia keluar dari jebakan keadaan sekarang dan menjadikannya berjaya akan sulit diwujudkan tanpa ketulusan serta tekad semua. Terutama ketulusan dan tekad para ‘Simpul Kesadaran’ yang mensintesakan budaya penopang peradaban baru Indonesia. Sebuah peradaban yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang berjaya, bermartabat, serta memakmurkan seluruh masyarakat.
Jakarta, 26 Agustus 2008
(eh)
Sumber: Soetrisno Bachir.com
•••

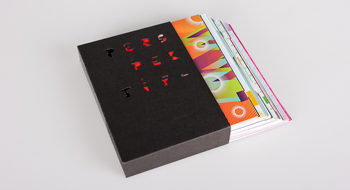



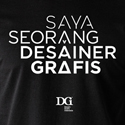



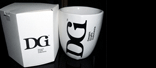

 1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto
1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto 2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong
2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong 3. Hurufontipografi | Surianto Rustan
3. Hurufontipografi | Surianto Rustan www.underconsideration.com
www.underconsideration.com

Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia kepada pergaulan dan percaturan politik antarbangsa. Namun, dalam percaturan politik antarbangsa belakangan ini, Indonesia tidak banyak tampil berkesan. Hal ini, disebabkan berbagai krisis yang melanda di dalam negeri, baik ekonomi, keamanan, dan lain-lain (multidimensi). Daya saing sumber daya manusianya pun belum dapat diandalkan, memandangkan kualitas pendidikan yang dimiliki masih terus menjadi bahan diskusi.