2. Analisis Semiotika ILM Membaca versi Seekor Unta
(Kompas, 31 Desember 1996)
Tanda Verbal:
Headline:
Mau pintar tanpa perlu membaca? Jadilah seekor unta.
Teks:
Sebuah perumpamaan klasik mengatakan: ’’Membaca adalah sumber pengetahuan. Nilainya ibarat seteguk air bagi tubuh kita’’.
Memang benar. Dan tak ada satu manusia pun di dunia ini bisa jadi pintar tanpa membaca. Termasuk mereka yang tergolong jenius sekali pun.
Hanya dengan memiliki kebiasaan membaca seperti kebiasaan minum air setiap hari, kita bisa membuat pikiran kita terus ’’hidup’’ dengan pengetahuan. Kecuali, bila kita adalah seekor unta yang sanggup bertahan hidup berhari-hari tanpa minum.
Closing Word:
Membaca setiap hari, seteguk pengetahuan bagi kehidupan kita.
Tanda Visual:
Ikon seekor unta yang memakai kacamata dan berdasi. Idiom estetik yang digunakan adalah idiom estetik parodi dan personifikasi.
Analisis Semiotika:
ILM berukuran 9 kolom kali 27 cm ini dirancang oleh Cipta Citra Advertising dan dimuat di harian Kompas tanggal 31 Desember 1996. Penempatan bidang ILM ditata secara horizontal. Komposisi yang digunakan komposisi dinamis, hal itu ditunjang dengan penempatan ilustrasi yang sedikit digeser ke kanan. Di samping itu, nuansa dinamis dan ekspresif juga terlihat dari ilustrasi yang dikerjakan dengan teknik hand drawing yang digoreskan secara spontan, ekspresif, dan lugas.
Dampak dari digesernya ilustrasi ke arah kanan memberikan kesan keluasan atau bidang kosong dari desain ILM tersebut. Hal itu ditopang dengan penempatan desain ILM secara horizontal. Bidang kosong pada ILM ini mempunyai makna konotasi tentang luasnya belantara ilmu pengetahuan yang harus kita ketahui. Masa depan manusia masih panjang, untuk itu dengan memiliki kebiasaan membaca seperti kebiasaan minum setiap hari, bisa membuat pikiran kita terus hidup dengan pengetahuan. Atau bisa juga mempunyai makna sebaliknya, masa depan kita semakin gelap karena kita tidak memiliki wawasan dan pengetahuan, akibatnya kita hanya akan menjadi manusia terjajah yang tidak berkembang akal dan pikiran kita. Center of interest tampak kepala unta berada pada titik tengah bidang iklan yang didominasi warna hitam pekat. Sedangkan gambar dasi yang berkibar di leher unta berfungsi sebagai penunjuk dan menekankan kalimat ’’Jadilah seekor unta’’.
Headline, teks, dan closing word menggunakan jenis huruf Sans Serif, garis huruf sama tebal dan tidak mempunyai kaki. Jenis huruf ini bersifat netral dan mudah dibaca.
Penempatan headline yang dipecah menjadi dua, di atas dan di bawah ilustrasi memberikan makna konotasi tentang sempitnya wawasan dan pengetahuan seseorang karena ia tidak mau menambah dan mengembangkan wawasan tersebut dengan membiasakan diri membaca. Makna konotasi tersebut terlihat pada posisi kalimat ’’Mau pintar tanpa perlu membaca?’’ menekan ilustrasi. Sehingga keberadaan ilustrasi menjadi dikerdilkan.
ILM yang dicetak dengan warna hitam putih dengan teknik positif negatif ini mampu bersaing di antara deretan kolom surat kabar harian Kompas yang berisi susunan huruf. Dengan dominasi blok hitam sebagai latar ILM dan headline berwarna putih mampu menarik perhatian pembaca untuk mencermati ILM yang dikemas dengan idiom estetik parodi.
Berdasarkan tanda verbal dan tanda visual maka bisa dicermati pesan ILM tersebut dengan bantuan kode hermeneutik, kode simbolik, kode narasi, dan kode kebudayaan.
Kode hermeneutik terlihatpada aspek pertanyaan, teka-teki, dan enigma. Ketiga aspek kode hermeneutik itu tampak pada headline yang berbunyi: ‘’Mau pintar tanpa perlu membaca?’’. Kalimat tersebut bernada pertanyaan, sekaligus teka-teki, dan enigma. Sebab jika headline itu dikupas lebih jauh, akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa pintar tanpa membaca. Kemudian kalimat di bawahnya seolah-olah berbentuk jawaban tetapi masih merupakan teka-teki: ‘’Jadilah seekor unta’’. Kalimat tanya yang dimunculkan oleh headline dan jawaban dari kalimat tanya itu masih merupakan enigma dan tidak ada korelasi antara yang satu dengan lainnya.
Kegamangan dari enigma headline tersebut baru terjawab ketika menyimak teks berbunyi: ‘’… Hanya dengan memiliki kebiasaan membaca seperti kebiasaan minum air setiap hari, kita bisa membuat pikiran kita terus ’’hidup’’ dengan pengetahuan. Kecuali, bila kita adalah seekor unta yang sanggup bertahan hidup berhari-hari tanpa minum’’. Makna konotasi dari tanda verbal tersebut, wawasan dan tingkat intelektualitas kita rendah ketika tidak mempunyai kebiasaan membaca.
Kode visual hermeneutik terlihat pada tanda visual berupa ikon seekor unta yang didandani sedemikian rupa menggunakan kacamata dan dasi. Visualisasi ikon seekor unta merupakan enigma dan parodi dari sifat manusia instan yang maunya serba enak, tidak mau menerapkan peribahasa: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Visualisasi ikon seekor unta tersebut merupakan personifikasi dari seorang intelektual, kaum profesional yang mempunyai wawasan dan kepandaian yang mumpuni. Kacamata dan dasi yang dijadikan atribut unta merupakan parodi dari mitos kepandaian, intelektualitas, modern, dan profesionalisme.
Kode simbolik terlihat pada aspek kemenduaan, pertentangan dua unsur dan kontradiksi. Ketiga aspek kode simbolik itu bisa diterapkan pada sifat kontradiksi dari headline berbunyi: ’’Mau pintar tanpa perlu membaca?’’. Pertentangan dua unsur atau kontradiksi ini terlihat pada kata ’’mau pintar’’, dengan kata ’’tanpa perlu membaca’’.
Kode narasi yaitu kode yang mengandung cerita, terlihat dari keseluruhan tanda verbal ILM tersebut, terutama pada teks.
Kode visual narasi terkandung pada tanda visual berupa ikon seekor unta. Keberadaannya menceritakan tentang mitos unta yang diyakini sebagai binatang yang bodoh, tetapi ia mau belajar dari pengalaman. Ketika ia berjalan di belantara padang pasir, ia tidak akan terperosok pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Makna konotatifnya, ia mau belajar dengan mata batinnya. Ketika mitos unta itu diparalelkan dengan manusia yang mempunyai akal dan budi, akankah hal itu terjadi?
Kode kebudayaan nampak pada aspek mitos dan pengetahuan. Mitos unta diyakini oleh masyarakat Timur Tengah sebagai binatang padang pasir yang selalu belajar dari pengalaman. Sebab sebodoh-bodohnya unta, ia tidak akan pernah terperosok dalam lubang yang sama. Makna konotasinya, jika manusia dalam kehidupan kesehariannya selalu mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan, berarti ia lebih tolol dari seekor unta. Makna konotasi dari mitos unta tersebut sebenarnya sudah tersirat dalam headline yang berbunyi: ‘’Mau pintar tanpa perlu membaca? Jadilah seekor unta’’.
Aspek pengetahuan tersirat pada closing word: ‘’Membaca setiap hari, seteguk pengetahuan bagi kehidupan kita’’ yang diperjelas dengan teks yang terdapat pada ILM tersebut.
Tanda visual yang ditampilkan dalam ILM ini adalah ikon seekor unta. Visualisasi tanda visual tersebut menggunakan idiom estetik parodi dan personifikasi. Ikon seekor unta itu memparodi manusia yang terjebak budaya jalan pintas, dan budaya yang menisbikan proses, termasuk di antaranya budaya membaca. Meski pun si unta itu didandani dengan kacamata dan berdasi yang merupakan personifikasi dari mitos kepandaian, modern, profesionalisme, dan wawasan yang jembar, tetapi ia tetap kelihatan bodoh dari ekspresi wajahnya yang nyengir dan melongo. Tanda visual tersebut mempertegas teks yang berkonotasi pembenaran bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini bisa pintar tanpa membaca.
Dari analisis berdasarkan tanda verbal dan tanda visual yang terkandung dalam ILM ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tanda verbal dan tanda visual. Keduanya saling melengkapi. Parodi dan personifikasi yang merupakan idiom estetik tanda visual menjadi kuat keberadaannya sebagai visualisasi dari tanda verbal. Maka kesimpulannya, tanda bermakna sebagai pengetahuan budaya baca.
PENUTUP
Pesan yang terdapat pada berbagai karya iklan layanan masyarakat adalah pesan yang disampaikan kepada khalayak sasaran dalam bentuk tanda. Secara garis besar, tanda dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tanda verbal dan tanda visual. Tanda verbal didekati dari ragam bahasa, gaya penulisan, tema dan pengertian yang didapatkan. Tanda visual dilihat dari cara menggambarkannya, apakah secara ikonis, indeksikal, atau simbolis.
Penjelajahan semiotika sebagai metode kajian ke dalam berbagai cabang keilmuan – dalam hal ini karya ILM yang merupakan bagian dari ranah kreatif desain komunikasi visual – dimungkinkan, karena ada kecenderungan untuk memandang berbagai wacana sosial sebagai fenomena bahasa. Artinya, bahasa dijadikan model dalam berbagai wacana sosial. Bertolak dari pandangan semiotika tersebut, jika sebuah praktik sosial dapat dianggap sebagai fenomena bahasa, maka semuanya – termasuk karya desain komunikasi visual – dapat juga dilihat sebagai tanda-tanda. Hal itu menurut Yasraf A Piliang dimungkinkan karena luasnya pengertian tanda itu sendiri.
Mengingat karya iklan layanan masyarakat mempunyai tanda berbentuk verbal (bahasa) dan visual, serta merujuk bahwa teks karya iklan layanan masyarakat penyajian visualnya mengandung ikon terutama berfungsi dalam sistem-sistem nonkebahasaan untuk mendukung pesan kebahasaan, maka pendekatan semiotika sebagai sebuah metode analisis tanda guna mengupas makna karya iklan layanan masyarakat layak diterapkan dan disikapi secara proaktif sesuai dengan konteksnya.
DAFTAR PUSTAKA
Barthes, Roland. 1974. S/Z. Penerjemah Richard Miller. New York: Hill and Wang, Buku asli diterbitkan tahun 1970.
Barthes, Roland. 1998. The Semiotics Challenge. New York: Hill and Wang.
Bakhtin, Mikhail. l981. The Dialogic Imagination. Massachussets: Harvard University Press.
Berger, Arthur Asa. 2000. Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer. Penerjemah M. Dwi Marianto dan Sunarto. Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana, buku asli diterbitkan tahun 1984.
———- ‘’Dagadu Djokdja: Perjalanan Empat Tahun Pertama’’. l997. Yogyakarta: PT Aseli Dagadu Djokdja.
Eco, Umberto. l979. A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press.
Fiske, John. 2005. Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif. PenerjemahYosal Iriantara dan Idi Subandy Ibrahim. Yogyakarta: Penerbit Jalasutra, buku asli diterbitkan tahun 1990.
Hoedoro Hoed, Benny. 1994. ‘’Dampak Komunikasi Periklanan, Sebuah Ancangan dari Segi Semiotik’’. Jurnal Seni BP ISI Yogyakarta IV/2. 111-133.
Hornby, A.E. (ed). l974. Oxford Advanced Learner Dictionary. London: Oxford University Press.
Hutcheon, Linda. l985. A Theory of Parody, The Teaching of Twentieth Century Art Form. Methuen.
Jefkins, Frank. 1996. Periklanan. Penerjemah Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga, buku asli diterbitkan tahun 1985.
Jewler, A. Jerome., dan Drewniany Bonnie, L. 2001. Creative Strategy in Advertising. USA: Wadsworth Thomson Learning, 10 Davis Drive Belmont.
Kasali, Rhenald. 1992. Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Kotler, Philip. 1991. Marketing. Penerjemah Herujati Purwoko. Jakarta: Penerbit Erlangga, buku asli diterbitkan tahun 1984.
Liliweri, Alo. 1991. Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
Luxemburg, Jan van., Bal, Mieke., dan Weststeijn, Willem, G. l992. Pengantar Ilmu Sastra. Penerjemah : Dick Hartoko. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, buku asli diterbitkan tahun 1982.
Miryam, Bebe Indah. 1984. ‘’Iklan Layanan Masyarakat’’, Skripsi, Bandung: Institut Teknologi Bandung.
Nizar, M dan Mawardi. l972. Saduran Basic Design. Yogyakarta: STSRI ‘’ASRI’’.
Noth, Winfriend. 1995. Handbook of Semiotics. Blommington and Indianapolis: Indiana University Press.
Nuradi. 1996. Kamus Istilah Periklanan Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Piliang, Yasraf Amir. 1998. Sebuah Dunia yang Dilipat, Realitas Kebudayaan menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme. Bandung: Penerbit Mizan.
Piliang, Yasraf Amir. l999. Hiper-Realitas Kebudayaan. Yogyakarta: LKiS.
Piliang, Yasraf Amir. 2004. ‘’Metode Penelitian Desain : Berbagai Kecenderungan Masa Kini’’. Jurnal Seni Rupa dan Desain Visual, FSRD Untar Jakarta VI/2. 78-94.
Pirous, AD. 1989. ‘’Desain Grafis pada Kemasan’’. Makalah Simposium Desain Grafis, FSRD ISI Yogyakarta.
Sanyoto, Sadjiman Ebdi. 2006. Metode Perancangan Komunikasi Visual Periklanan. Yogyakarta: Dimensi Press.
Saussure, Ferdinand de. 1998. Pengantar Linguistik Umum. Penerjemah Rahayu S. Hidayat. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, buku asli diterbitkan tahun 1973.
Selden, Raman. l99l. Panduan Pembaca Teori Sastra Masa Kini. Penerjemah Rachmat Djoko Pradopo. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, buku asli diterbitkan tahun 1985.
Subakti, Baty. 1993. Sejarah Periklanan Indonesia. Jakarta: Penerbit Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia.
Sutanto, T. 2005. ‘’Sekitar Dunia Desain Grafis/Komunikasi Visual’’. Pura-pura Jurnal DKV ITB Bandung. 2/Juli. 15-16.
Spradly, James, P. 1997. Metode Etnografi.Penerjemah Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana.
Tinarbuko, Sumbo. 2001. ‘’Semiotika Desain Dagadu Djokdja’’. Yogyakarta: Dagadu For Beginners Pakuningratan.
Tinarbuko, Sumbo. 1998. ‘’Memahami Tanda, Kode, dan Makna Iklan Layanan Masyarakat’’. Tesis. Bandung: ITB Bandung
Williamson, Judith. 1984. Decoding Advertisements, Ideology and Meaning in Advertising. London: Marion Boyars Publishers Ltd, 24 Lacy Road.
Widagdo. 1993. ‘’Desain, Teori, dan Praktek’’. Seni Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Seni. BP ISI Yogyakarta III/03.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumbo Tinarbuko
Kandidat Doktor FIB UGM ini adalah alumnus Magister Seni Rupa dan Desain Program Pascasarjana ITB. Sehari-hari menjadi Konsultan Desain dan Dosen Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Program Pascasarjana ISI Yogyakarta. Di almamaternya mengajar mata kuliah: Huruf dan Tipografi, Tinjauan Desain I & II, Desain Komunikasi Visual I & IV, Skripsi, Tugas Akhir Karya.
Sejak September 2003 sampai sekarang mengajar mata kuliah Semiotika dan Penciptaan Seni (Desain Komunikasi Visual) Program Pascasarjana ISI Yogyakarta.
Mulai September 2005 sampai sekarang mengajar mata kuliah Semiotika Iklan dan Penulisan Naskah Iklan di Jurusan Komunikasi FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Sekarang bermukim di Jl. Sonopakis Lor 15 Yogyakarta 55182.
Telpon 0274-378276, 08886896089, 08122703228.
email: [email protected]
•••


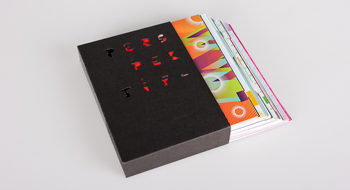


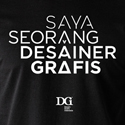




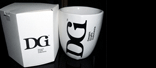

 1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto
1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto 2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong
2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong 3. Hurufontipografi | Surianto Rustan
3. Hurufontipografi | Surianto Rustan www.underconsideration.com
www.underconsideration.com

mas, saya taufiq mahasiswa sastra indonesia unesa. bisa minta tolong jelaskan tentang konsep lima kode barthes itu mas? please mas, saya minta tolong banget karena ujian proposal tinggal menunggu hari. sekalian saya minta tolong diberitahu dimana mas dapatkan buku sumber karangan roland barthes itu karena di surabaya saya kesulitan menemukan buku tersebut. mohon dijawab, please tolong saya mas. terima kasih…
ini jawaban dari mas sumbo:
Rekan Taufiq, Selamat Jumat ….
Selamat datang di belantara tanda dan selamat berjumpa di rerimbunan makna.
Penjelasannya seperti ini:
KODE
Kode, merujuk terminologi sosiolinguistik ialah variasi tutur yang memiliki bentuk yang khas, serta makna yang khas pula (Poedjosoedarmo, 1986:27). Sementara itu, kode menurut Piliang (1998:17), adalah cara pengkombinasian tanda yang disepakati secara sosial, untuk memungkinkan satu pesan disampaikan dari seseorang ke orang lainnya. Di dalam praktik bahasa, sebuah pesan yang dikirim kepada penerima pesan diatur melalui seperangkat konvensi atau kode. Umberto Eco menyebut kode sebagai aturan yang menjadikan tanda sebagai tampilan yang konkret dalam sistem komunikasi. (Eco, 1979:9).
Fungsi teks-teks yang menunjukkan pada sesuatu (mengacu pada sesuatu) dilaksanakan berkat sejumlah kaidah, janji, dan kaidah-kaidah alami yang merupakan dasar dan alasan mengapa tanda-tanda itu menunjukkan pada isinya. Tanda-tanda ini menurut Jakobson merupakan sebuah sistem yang dinamakan kode (Hartoko, l992:92).
Kode pertama yang berlaku pada teks-teks ialah kode bahasa yang digunakan untuk mengutarakan teks yang bersangkutan. Kode bahasa itu dicantumkan dalam kamus dan tata bahasa. Selain itu, teks-teks tersusun menurut kode-kode lain yang disebut kode sekunder, karena bahannya ialah sebuah sistem lambang primer, yaitu bahasa. Sedangkan struktur cerita, prinsip-prinsip drama, bentuk-bentuk argumentasi, sistem metrik, itu semua merupakan kode-kode sekunder yang digunakan dalam teks-teks untuk mengalihkan arti.
Roland Barthes dalam bukunya S/Z mengelompokkan kode-kode tersebut menjadi lima kisi-kisi kode, yakni kode hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, kode narasi, dan kode kultural atau kode kebudayaan (Barthes, 1974:106). Uraian kode-kode tersebut dijelaskan Pradopo (1991:80-81) sebagai berikut:
Kode Hermeneutik, yaitu artikulasi berbagai cara pertanyaan, teka-teki, respons, enigma, penangguhan jawaban, akhirnya menuju pada jawaban. Atau dengan kata lain, Kode Hermeneutik berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam sebuah wacana. Siapakah mereka? Apa yang terjadi? Halangan apakah yang muncul? Bagaimanakah tujuannya? Jawaban yang satu menunda jawaban lain.
Kode Semantik, yaitu kode yang mengandung konotasi pada level penanda. Misalnya konotasi feminitas, maskulinitas. Atau dengan kata lain Kode Semantik adalah tanda-tanda yang ditata sehingga memberikan suatu konotasi maskulin, feminin, kebangsaan, kesukuan, loyalitas.
Kode Simbolik, yaitu kode yang berkaitan dengan psikoanalisis, antitesis, kemenduaan, pertentangan dua unsur, skizofrenia.
Kode Narasi atau Proairetik yaitu kode yang mengandung cerita, urutan, narasi atau antinarasi.
Kode Kebudayaan atau Kultural, yaitu suara-suara yang bersifat kolektif, anomin, bawah sadar, mitos, kebijaksanaan, pengetahuan, sejarah, moral, psikologi, sastra, seni, legenda.
Terkait dengan 5 kode sosial Roland Barthes, anda harus pandai-pandai menghubungkan dan menyambungkan objek kajian dengan kelima kode tersebut. Dengan mengkaitkan 5 kode tersebut maka Anda akan lebih mudah melihat makna konotasi dari objek penelitian/kajian Anda.
Semoga membantu.
Salam,
Sumbo
http://sumbo.wordpress.com
ya ampunn.. bagus banget tulisannya. saya lasty mas, mahasiswi dkv binus, udah semester 8 sedang ta. knp ya 4 thn kuliah di dkv baru nemu web ini skrg.. hehe..
pak ismiaji juga dosen di binus, tapi saya belum sempet ngerasain diajarin dia.
saya ansy mas, mahasiswi fikom unitomo, bisa minta tolong dijelaskan tentang teori piktorial semiotik versi erwin panofsky, atau teori semiotika mana yang sesuai dengan judul penelitian skripsi saya. saya sekarang sedang meneliti tentang makna simbolik relief ramayana candi prambanan. makasih mas, atas masukannya.
slmt siang pak sumbo, perkenalkan saya pras, saya skrg sdg meneliti tentang semiotika desain grafis t-shirt local clothing yang didistribusikan di distro. adapun korpus saya adalah tipografi dan gambar yang ada pada t-shirt tersebut. namun, saya masih kesulitan menganalisa tipografi tersebut dengan semiotika. saya menggunakan icon, indeks, simbol apakah bisa?
mohon saya dibantu bgmn cara menganalisa tipografi, apakah ada teori semiotika yang cocok untuk menganalisanya.
terima kasih pak sumbo.
mas, saya lagi mau bikin tesis. judulnya kajian visual hermeneutika film ayat-ayat cinta.
1. buku acuannya apa yah?
2. kalau estetika islam apa bisa sebagai pisau penelitian film yang bernuansa islam?
3.apakah herneutika bagian dari estetika, atau estetika bagian dari hermeneutika?
makasih mas atas waktu dan jawaban yang diberikan.
saya dalam dilema mempertanyakan keabsahan dan kesesuaian penggunaan teori2 semiotika yg berasal dari linguistik (sausure) dan filsafat sosiologis (pierce) utk secara langsung digunakan pada bentuk2 visual, tepatnya piktorial. Goran Sonesson melakukan proyek2 utk mengkaji semiotika visual dan piktorial yg disesuaikan di olah kembali dari semiotika yg sebelumnya. Apakah tidak ada pengkritisian terhadap metode2 dan prosedur2 analisa semiotik itu sendiri, apakah sesuai atau tidak, baik secara epistemologis maupun ontologisnya bagi kajian visual dan piktorial dalam iklan atau desain grafis?
untuk semiotika film buku basicnya mungkin karangan christian metz
Anda sepertinya terjebak dalam logika pemaknaan tanda anda sendiri. Barthes sendiri menganalisa logika tanda sebelum membaginya dalam kode2 tanda, silahkan baca bukunya lagi. In my perspective, iklan tersebut mempunyai logika “pintar-baca” (S1) dan anti “pintar-baca” (~S1) selanjutnya anda (seharusnya) bisa menggunakan Lacan Matrics untuk menilai komposisi logika sehingga pemaknaan di level pembaca bisa diketahui. Yang saya tangkap dari analisa anda, masih terlihat context anda sendiri dalam artian, anda lalai untuk merasakan aura pembaca tanda dari iklan tersebut secara keseluruhan. Seperti pada kalimat “Atau bisa juga mempunyai makna sebaliknya, masa depan kita semakin gelap karena kita tidak memiliki wawasan dan pengetahuan, akibatnya kita hanya akan menjadi manusia terjajah yang tidak berkembang akal dan pikiran kita”. Ini adalah analisa pribadi anda sebagai pembaca tanpa melihat dulu komposisi logika yang mungkin dirasakan pembaca lain selain anda. Buktikan dulu ada hubungannya antara bidang kosong dengan masa depan suram para pembaca iklan tersebut. Bidang kosong bisa di paradigmatic kan dengan “tanpa tulisan/makna/isi” dan seterusnya (kalau saya yang analisa keenakan anda nantinya)…
Anda juga seharusnya mulai dari konsep yang sederhana dulu, apakah sebaran tanda dalam iklan bisa dinilai dalam binary oppositionnya. Jangan langsung tergesa2 memburu ketenaran dengan menggunakan Barthes, kadang2 kita tidak perlu sejauh itu, tidak ada guna nya membahas sesuatu yang semua orang sudah tahu artinya, itu namanya rahasia umum, bukan analisa seorang akademisi.
Satu lagi, menurut saya yang ada iklan itu bukan ikon unta, tapi symbol unta. Donald Duck bukan ikon bebek walaupun semua orang tahu grafis tubuh donald ‘mirip’ bebek, tapi donald bisa jadi symbol dari bebek, orang yang kelakuannya mirip bebek, atau masyarakat ‘bebek’. yang ada di iklan itu kan cuma garis-garis yang dihubungkan. Kalau Sandra Dewi? nah, itu bisa jadi ikon aktris muda indonesia tuh…
mendengar, eh, membaca kata2 karma, jadi inget Margitte…. this is not an ‘unta’.
atau this is not ‘semiotika’, just a self-reflection on unta.
saya mahasiswa Politeknik Global Indonesia di Jakarta, jurusan Advertising, sdng buat iklan layanan masyarakat mengenai korupsi.
saya menggunakan bahasa “korupsi anda mengGANTUNGkan nasib hidup jutaan rakyat Indonesia”.
kiranya pas / tidak dari segi semiotika.
dateline 3 hari lg.
mohon sarannya dan saya ucapkan terima kasih.
mas, saya lg bingung dgn skripsi sy
sy ambil semiotik iklan yg b.inggris krn jur sy sastra ing
tp susah bgt nyari iklan2 b.ing dgn jenis yg sama tp macamnya byk. mhn saran dn bantuannya mas
thanx
mas, minta tolong juga dong, hahahaha…
gapapa ya?
saya mahasiswa ISI jogja jurusan televisi
hendak Tugas Akhir dan rencananya bikin ILM,
tapi buku2 referensi ttg ILm di Indonesia kayaknya kok gak banyak ya….
ada referensi buat saya ga mas?
apa aja yang berhubungan dg ILm lah,buku, blog, atau apa aja..
terimakasih banyak sebelumnya..
thanks banget mas, sangat membantu dalam tugas saya ^^
keep hardwork ^^
mas saya mahasiswa periklanan moestopo
mohon saya dibantu bgmn cara menganalisa tipografi, apakah ada teori semiotika yang cocok untuk menganalisanya.
terima kasih pak sumbo.
.mas, saya gi ngerjain skripsi tentang semiotika iklan politik di tv . .
.bisa bantu kasi referensi sistematika penulisan nya ga . ?
.saya kesulitan menjabarkan iklan secara detail, sebab di kampus saya masih belum banyak penelitian semiotika ini .
.saya menggunakan teori konsep Barthes . .
.oia saya mhs komunikasi fisip Universitas Riau . .
mas, atau pak ? salam kenal.
Minta tolong banget……., saya mhs pascasarjana fikom. Sy tertarik dengan iklan teh sariwangi di televisi yang versi mari nge-teh mari bicara. Saya ingin menganalisnya melalui pendekatan semiotika pada keharmonisan suami isteri dalam iklan tersebut. Referensinya apa saja?.
pak sumbo…tolong diberi contoh realitas tentang teori pierce, saussure, barthes….karena kebanyakan rujukan buku hanya membahas teori dan hanya sedikit contoh…..dari contoh di kehidupan nyata akan mudah dimengerti daripada bersifat teori…(itu menurut saya) untuk KRITIK SOSIAL IKLAN LAYANAN MASYARAKAT yang paling cocok pakai modelnya siapa????? terima kasih pak sumbo