Oleh Iwan Gunawan
Ringkasan Disertasi
Penggambaran sosok manusia pada iklan majalah De Zweep/D’Orient dan Pandji Poestaka tahun 1922 - 1942. Analisis ideologis pada media massa kolonial.
1. Latar belakang
Pemerintah Belanda sebagai fihak yang memegang tampuk pemerintahan banyak menanamkan sistem dan struktur sosial yang mengatasi struktur sosial yang sudah ada seperti misalnya pada sistem dan tingkat kepegawaian (negeri) yang akhirnya berujung pada pergeseran nilai dan tingkatan dari kedudukan seseorang. Sistem nilai Belanda yang dianut juga mengubah orientasi dari keraton dan kerajaan lokal di nusantara ke kerajaan Belanda. Hal ini berakibat pada berubahnya penampilan dari masyarakat lokal yang mulai mengadopsi nilai-nilai Barat ke dalam kehidupannya sehari-hari. Tolok ukur dan perilaku masyarakat diukur berdasarkan nilai-nilai Barat atau Belanda. Pakaian mereka mulai tertutup, atau dikombinasi dengan pakaian gaya Barat. Tidak hanya pakaian, gaya hidup juga berubah sesuai nilai-nilai Barat terutama masyarakat kota.
Dengan masuknya produk-produk Barat melalui kolonisasi, maka masyarakat lokal yang menggunakan produk-produk Barat akan berubah juga gaya hidup dan perilakunya. Secara tidak langsung modernisasi juga mulai memasuki kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian, ilmu pengetahuan menjadi acuan dari nilai kebenaran yang terwujud dalam sistem pendidikan, pengobatan, ilmu pengetahuan alam, juga teknologi. Dalam industri media, juga terjadi banyak perubahan akibat dari pengaruh modernisasi dan proses pembaratan tersebut. Sebelumnya, dalam masyarakat tradisional, media hanyalah menjadi milik golongan khusus seperti sastrawan dan kaum bangsawan, tetapi dengan munculnya teknologi penerbitan modern, media sudah lebih memasyarakat. Sistem perdagangan yang dianut Belanda dan negara Eropa juga membawa serta industri media di dalamnya. Surat kabar dan majalah selain bisa dilihat sebagai produk juga dapat dilihat sebagai salah satu bagian dari sistem penjualan produk karena di dalam media massa tersebut terselip iklan-iklan. Surat kabar dan majalah adalah media bagi para industrialis dan pedagang untuk menyampaikan informasi mengenai produk yang dijualnya.
Media cetak khususnya di tahun 1922-1942, merupakan media yang dapat diandalkan dalam menyampaikan informasi yang terinci tentang suatu produk. Di samping itu, iklan di media cetak seperti majalah memiliki keuntungan karena bisa menyatu dengan isi dari majalah itu sendiri. Misalnya ketika di dalam majalah tersebut ditayangkan artikel tentang suatu jamuan makan dan bila di dalam majalah tersebut juga dimuat iklan yang mempergunakan gambar adegan jamuan makan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan antara pesan artikel dan iklan. Artikel akan memperkuat pencitraan dari iklan tersebut. (Silverblatt, 1995: 181)
Dalam menggambarkan keunggulan dan kebaikan produk dilakukan upaya–upaya untuk menarik perhatian dan menanamkan pengaruh kepada konsumen seperti dramatisasi suatu adegan yang dibuat sedemikian rupa sehingga berkaitan dengan target pembeli dari produk. Sebagai pelaku dalam adegan tersebut, biasanya manusia digambarkan secara stereotype. Hal tersebut diperlukan untuk memperkuat identifikasi dari pemirsa atas tokoh yang menjadi pelaku dari adegan dalam iklan tersebut.
2. Periode sejarah: 20 tahun sebelum pendudukan Jepang
Di awal abad ke 20 sudah muncul organisasi yang berorientasi pada nasionalisme seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1912) dan Indische Partij (1912). Di samping itu, banyak peristiwa penting lain yang akan berdampak pada perkembangan nasionalisme Indonesia kemudian. Pada sekitar tahun 1920 bahasa Melayu memperoleh kekuatan sebagai bahasa politik. Pers pribumi berbahasa Melayu maju pesat. Kemajuan ini merupakan bagian dari alur sebelumnya di tahun 1910 dimana C.A. van Ophuijsen menerbitkan tata bahasa Melayu baru dan kemudian bahasa Melayu Ophuisen ini menjadi bahasa standar baru yang diajarkan di sekolah-sekolah menengah pribumi (Miert, 2003: 161-162). Pada sidang Volksraad di tahun 1921, nama “Indonesia” dikemukakan oleh Abdoel Moeis untuk menggantikan “Hindia Belanda” (Miert. 2003: 272). Kemudian, sejalan dengan semangat untuk menyatukan diri, bahasa Melayu pun mulai dipakai sebagai bahasa yang mempersatukan bangsa-bangsa di Indonesia.
Pada tahun 1930-an bangsa Jepang sudah mulai hadir di Hindia Belanda sebagai pedagang produk buatan Jepang. Armada Belanda akhirnya dikalahkan oleh Jepang pada Perang Pasifik (1942-1945). Jepang kemudian masuk dan mulai menjajah Indonesia. Ketika Jepang menduduki Indonesia situasi menjadi sangat berbeda akibat kebijakan politik Jepang yang dengan serta merta menghentikan segala produk kebudayaan yang berkaitan dengan Belanda, bahkan film dan gambar-gambar yang menggunakan bahasa Belanda dilarang beredar (Poesponegoro, 2008: 103). Surat kabar dan majalah, walaupun terbit tanpa izin istimewa namun tetap diawasi oleh badan-badan sensor. (Poesponegoro, 2008: 96). [1]
Situasi sosial juga menjadi berbeda karena bangsa Belanda tidak lagi menjadi lapisan sosial yang dominan sehingga topik tentang penampilan iklan-iklan pada periode setelah 1942 bisa menjadi suatu penelitian yang berbeda dari penelitian ini.
3.1. Perkembangan ekonomi
Perekonomian Indonesia di tahun 1920-an hingga 1940-an sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang mendahuluinya yaitu diberlakukannya Politik etis di Hindia Belanda sejak tahun 1901. Disamping itu peristiwa perekonomian dunia yang baru saja meneyelesaikan perang dunia pertama yang diikuti masa depresi di tahun 1930-an sangat mempengaruhi perekonomian Hindia Belanda saat itu.
Politik Etis merupakan hasil dari pemikiran orang-orang Belanda yang merasa berhutang budi akibat sistim tanam paksa yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia sejak tahun 1830. Politik Etis adalah suatu pemikiran yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus). Kalangan industrialis Belanda yang berfikiran liberal, menyambut baik keputusan ini karena mengharapkan ekspansi pasar mereka sebagai akibat dari meningkatnya kesejahteraan kaum sosialis dan konservatif di Belanda, yang memandang ideologi liberal dengan ketidakpercayaan secara kritis. (Wertheim, 1999: 70).
Depresi berlangsung di tahun 1933. Akibat depresi ini, banyak tenaga kerja yang terancam kehilangan pekerjaan dan pemerintah mengalami krisis pendapatan. Banyak pegawai negeri yang tidak begitu penting tugasnya diberhentikan atau dilakukan pemotongan gaji. Hal ini berdampak buruk, yaitu pengangguran pada tenaga kerja pribumi khususnya lulusan sekolah modern. Tetapi disamping itu, banyak perusahaan yang tadinya memperkerjakan tenaga kerja Barat dan Cina terpaksa menggantinya dengan tenaga kerja pribumi yang bisa dibayar lebih murah (Ricklefs 2005: 386).
Perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang telah diuraikan tadi saling berkaitan dan pada akhirnya akan membentuk strata sosial dan pemaknaan terhadap strata sosial yang terjadi di masa tahun 1920-an hingga 1940-an. Strata sosial yang diwarisi dari sistem feodal Jawa, diintervensi oleh struktur sosial Belanda / Barat baik secara ekonomi, politis maupun budaya. Masuknya Belanda jelas menghasilkan struktur lapisan masyarakat yang berbeda dari sebelumnya. Struktur lapisan masyarakat dan pemaknaannya terus bergerak seiring dengan pergolakan politik dan nasionalisme Indonesia. Masyarakat pribumi berusaha keras untuk mencapai lapisan sosial yang tertinggi lewat pendidikan, perekonomian maupun politik (kekuasaan).
3.2. Strata sosial masyarakat di Hindia Belanda
Pada abad ke 17 dan 18, Kompeni Hindia Belanda telah menumbuhkan suatu sistem status yang berkembang di Indonesia, khususnya di Jawa. Di Batavia, pegawai kompeni Belanda menempati lapisan sosial tertinggi, kemudian di bawahnya adalah mereka yang disebut sebagai warga merdeka (bebas), yaitu mereka yang terdiri dari penganut agama Kristen (Belanda, mestizo, dan budak-budak Kristen yang diberi hak suara). Setelah itu adalah lapisan yang terdiri atas orang Cina. Penduduk Indonesia, sebagian besar adalah budak, menempati urutan terbawah. Sistem status di Batavia ini membentuk titik awal bagi masyarakat kolonial di Jawa pada abad ke-19 (Wertheim, 1999: 107).
Dalam Regeringsreglement tahun 1854, masyarakat Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan penduduk berdasarkan pada ras, yaitu
a. Golongan Eropa, (yang didominasi oleh orang Belanda).
b. Golongan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) seperti Tionghoa, India, dan Arab,
c. Golongan Pribumi (Inlanders).
Pengelompokan tersebut diatur melalui peraturan Regerings Reglement (RR) jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling (Stb. 1855-270 jo. Stb. 1925-415 jo. Stb. 1925-447) maupun dalam Nederlandsche Onderdaanschap van niet Nederlanders (Stb. 1910-126).
Pada pembagian secara rasial ini, orang Tionghoa dimasukkan dalam kelompok Timur Asing bersama orang India, dan Arab. Pemisahan ini dimaksudkan untuk alasan keamanan. Mereka diharuskan mengenakan pakaian khas, ciri khas fisik kelompok masing-masing, seperti penggunaan thaucang (kuncir) bagi para pria Tionghoa. Khusus untuk istilah golongan Vreemde Oosterlingen merupakan pergeseran nama dari Vreemdelingen yang berlaku pada abad ke-17 dan ke-18. Strata sosial yang diciptakan oleh peraturan tersebut terus berlanjut hingga awal abad ke 20.
Secara sosial, bangsa pribumi (inlanders) juga tergolongkan ke dalam beberapa kelas. Pengelompokan ini terjadi akibat masuknya pribumi ke dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda atau akibat dari pencapaian mereka di bidang pendidikan dan perekonomian.
Menurut DH Burger; sejak abad XVIII sampai dengan awal abad XX di pulau Jawa terdapat lima golongan masyarakat yaitu:
a. Golongan pamongpraja bangsa Belanda
b. Golongan pegawai Indonesia baru
c. Golongan pengusaha partikelir Eropa
d. Golongan akademisi Indonesia (sarjana hukum, insinyur, dokter, guru, ahli pertanian, dan ahli-ahli lainnya).
e. Golongan menengah Indonesia, yaitu para pengusaha Indonesia yang memiliki usaha di bidang perniagaan dan kerajinan (Burger,1975, ).
Sartono Kartodirdjo membagi stratifikasi masyarakat Hindia Belanda menjadi:
a. Elit birokrasi yang tediri dari Pangreh Praja Eropa ( Europees Binnenland Bestuur) dan Pangreh Praja Pribumi.
b. Priyayi Birokrasi termasuk priyayi ningrat, priyayi profesional (priyayi gedhe dan priyayi cilik),
c. Golongan Belanda dan Indo yang secara formal masuk status Eropa,
d. Orang Kecil (Wong Cilik) yang tinggal di kampung.
Strata sosial bisa dilihat dari berbagai kategori ukuran; berdasarkan pendidikan, tingkat ekonomi, kebangsawanan, atau berdasarkan ras. Secara hukum pemerintah Belanda menegaskan perbedaan dengan pembagian lapisan sosial berdasarkan ras. Namun di masyarakat, khususnya pribumi, terjadi suatu perjuangan untuk meningkatkan diri ke lapisan sosial yang lebih tinggi melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan ekonomi, juga dengan berupaya memasuki struktur masyarakat Belanda melalui sistem pemerintahan yaitu sebagai pegawai negeri.
Pada tahun 1920-an di Yogyakarta, dimana kesultanan menjadi pusat dari sistem sosial, masyarakatnya terbagi ke dalam strata sosial sebagai berikut:
a. Bangsawan
b. Priyayi
c. Kawudalem (orang biasa) atau wong cilik (Sumardjan, 2009: 23)
Priyayi yang dimaksud ini merupakan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, terbentuk lapisan baru masyarakat yang berbeda dari struktur tersebut di atas. Belanda menjadi bagian dari struktur masyarakat dimana mereka menempatkan diri mereka pada lapisan atas setingkat kaum bangsawan. Akibat dari sistem pemerintahan Belanda pula maka dibutuhkan pegawai-pegawai untuk bekerja di kantor pemerintahan. Orang-orang pribumi yang telah mendapatkan penididikan yang cukup, seperti sekolah tingkat dasar yaitu HIS (Hollandsch-Inlandsche School hingga sekolah-sekolah lanjutan yang khusus mendidik ahli-ahli administrasi pribumi yaitu OSVIA (Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaaren), menjadi pegawai pemerintah. Dari stratanya mereka berada di lapisan menengah sejajar dengan priyayi. Selain itu ada kelompok menengah lain yang juga muncul yaitu pekerja di bidang swasta yang memiliki cukup pendidikan formal. (Sumardjan, 1962: 38). Dari segi pakaian, priyayi asli masih berorientasi pada keraton dan kebudayaan Jawa. Mereka berpakaian Jawa dengan kain dan blangkonnya. Sementara itu rekannya “priyayi” yang berasal dari kalangan pegawai pemerintah dan swasta menggunakan pakaian yang berorientasi ke Barat atau Belanda. Pola pikir mereka juga terbuka dengan pikiran-pikiran tentang demokrasi. Pakaian mereka biasanya adalah kemeja, celana panjang dan jas. (Sumardjan, 2009: 39).
Jadi, istilah priyayi menjadi memiliki pengertian yang bermacam-macam. Pertama-tama Priyayi bisa diartikan sebagai kelompok bangsawan, yaitu para pangeran dari keempat swapraja di Jawa Tengah (Surakarta dan Yogyakarta) (Miert, 2003: 6). Yang kedua, Priyayi bisa diartikan sebagai priyayi yang berada di kelas pemerintahan atau pangreh praja. Kelompok kedua ini sudah memerintah penduduk Jawa sejak dahulu. Di masa tanam paksa, para priyayi kelompok kedua ini memegang peranan sebagai perpanjangan tangan Belanda. Mereka terdiri dari bupati, patih (pembantu bupati), dan wedana (kepala distrik). Kelompok ketiga barulah muncul setelah tahun 1900 para priyayi baru yang muncul baik dari kalangan pangreh praja yang lama maupun berasal dari masyarakat wong cilik yang berhasil meningkatkan pendidikannya (Miert 2003: 3). Selo Sumardjan menambahkan satu “jenis” priyayi lagi yaitu mereka yang berasal dari kalangan swasta. Van Miert menyebut mereka sebagai kaum muda yang tidak mau mengikuti jejak orang tuanya. Mereka memilih jabatan yang merdeka sebagai dokter praktek, guru sekolah, swasta, pengacara, atau wartawan. (Miert, 2003: 3).
Dari segi gaya hidup (dan akhirnya mempengaruhi penampilan), para priyayi golongan ketiga dan keempat ini hidup di antara kerangka pikir Barat dan Jawa. Hal tersebut sangat wajar karena merupakan akibat dari pendidikan Barat yang didapatnya dan nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua mereka.
Di samping struktur yang tebentuk akibat posisi resmi dalam kepegawaian pemerintah terdapat kelompok masyarakat lain yang terbentuk karena orientasi agamanya yaitu kaum Muslim. Koentjaraningrat (1984) menyebutnya sebagai Sodagar Kauman. Istilah ini ditujukan masyarakat jawa yang biasanya berprofesi sebagai pedagang yang taat menjalankan syariat Islam. Pandangan hidup dan gaya hidup mereka berbeda dengan priyayi. Selain berdagang mereka umumnya bekerja sebagai pengurus mesjid. Koentjaraningrat tidak memberikan informasi tentang bagaimana tingkatan posisi Kauman dalam strata sosial masyarakat saat itu. Kauman bertalian erat dengan penyebaran agama Islam di suatu daerah. Di kota-kota di Jawa, terutama kota-kota pesisir. Kauman juga dikaitkan dengan tanah yang ditempatinya yaitu yang berasal dari “pemberian hak sultan”. Pengunaan tanah kerajaan disebut sebagai desa perdikan. Dalam hal ini tanah tersebut ditujukan untuk penggunaan kegiatan keagamaan. Salah satu kategori desa perdikan ini adalah juga yang disebut sebagai desa pesantren, yaitu desa yang dipakai untuk sumber pemeliharaan agama dan sifatnya turun temurun. Desa pesantren ini banyak melahirkan pertumbuhan pengrajin-pengrajin yang giat dalam usaha perdagangan seperti batik. (Surjomihardjo, 2008: 39-40)
Para Santri (dan para Kiai) yang berasal dari pesantren ini berada dalam posisi yang cukup khusus dan penting karena ia seperti tidak dipengaruhi oleh sistem dan sruktur yang dibentuk Belanda. Dari sejarahnya memang para santri ini merupakan ujung tombak agama Islam Jawa. Ciri lain dari kelompok santri ini selain ketaatannya beribadah adalah peranannya dalam dunia perdagangan (Lombard, 1990, Jaringan Asia: 86 - 87)
Dari segi pakaian, antara santri yang memiliki posisi sebagai ulama ataupun bekerja sodagar biasanya tidak banyak berbeda yaitu tarbus atau peci dengan ikat kepala, jas, dan sarung.
Yang dimaksud dengan Belanda adalah juga termasuk mereka yang berasal dari perkawinan campur antara Belanda dengan pribumi. Mereka menduduki jabatan-jabatan sebagai pegawai pemerintah dalam masyarakat kolonial Belanda. “Mereka merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja di bawah terik matahari daerah tropis dengan tujuan pokok untuk jaminan hari tua” (Surjomihardjo, 2008: 177).
4. Majalah yang diteliti
Pada periode tahun 1922 hingga tahun 1940-an sudah cukup banyak majalah yang diterbitkan di Hindia Belanda. Dari pengamatan terlihat bahwa jika dibandingkan dengan majalah lain, majalah De Zweep atau kemudian berganti nama menjadi D’Orient pada tahun 1924 adalah majalah yang banyak memuat iklan, khususnya iklan-iklan yang mempergunakan gambar atau ilustrasi. Majalah D’Orient adalah majalah mingguan yang diterbitkan tahun 1924 hingga tahun 1942 di Hindia Belanda. Majalah ini diterbitkan di Weltevreden dan didistribusikan di kota Batavia. Sebelum bernama D’Orient majalah ini menggunakan nama De Zweep (1922 - 1923). Majalah ini berisi artikel-artikel tentang gaya hidup, berita, tips, dan lain-lain. Karena majalah ini menggunakan bahasa Belanda bisa disimpulkan bahwa target pembaca utama dari D’Orient adalah para pengguna bahasa Belanda. Pada tahun tersebut pengguna bahasa Belanda terutama adalah orang Belanda, indo dan pribumi yang pernah duduk di bangku sekolah yang mengajarkan bahasa Belanda.
De Zweep dan D’Orient diterbitkan oleh penerbit yang berada dalam satu grup perusahaan dengan Aneta, suatu kantor berita yang juga memiliki usaha biro iklan dengan nama yang sama (de Zweep, April 1922). D’ Orient dipilih juga karena memiliki rentang waktu penerbitan yang cukup panjang sehingga dari perjalanan terbitnya, dapat dilihat perubahan dalam penggunaan karakter atau tokoh dalam iklan.
Selain De Zweep atau D’Orient, majalah lain yang cukup banyak memuat iklan dengan gambar adalah majalah Pandji Poestaka yang berbahasa Melayu. Majalah mingguan Pandji Poestaka baru diterbitkan tahun 1923. Majalah ini bertahan hingga tahun 1945. Dari segi isinya, majalah ini hampir sama dengan D’Orient, merupakan majalah berisi berita dan artikel populer, hanya bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Melayu. Majalah ini diterbitkan oleh Balai Poestaka (sekarang ditulis Balai Pustaka) atau Kantoor voor de Volkslectuur.
Balai Poestaka atau Kantoor voor de Volkslectuur ini didirikan dengan Keputusan no. 63 tanggal 22 September 1917 tentang pembentukan Kantoor voor de Volkslectuur yang dipimpin Hoofdambtenaar. Lembaga inilah yang kemudian diberi nama Balai Poestaka yang dipimpin oleh D.A. Rinkes. Pada tahun 1923, Pandji Poestaka mulai diterbitkan sebagai majalah mingguan dan baru pada tahun 1926 menjadi dua kali seminggu karena permintaan yang sangat banyak. Pada tahun 1941 tiras majalah ini hingga mencapai 7.000 eksemplar. Di samping memuat banyak iklan, majalah Pandji Poestaka juga memiliki rentang waktu penerbitan yang cukup panjang sehingga sebanding dengan rentang waktu penerbitan De Zweep / D’Orient.
5. Ideologi dalam iklan
Ideologi adalah suatu keyakinan yang dijalankan tanpa sikap kritis. Orang yang meyakini kepercayan tersebut mempraktekkan nilai-nilai dari ideologi secara sukarela karena si pelaku sudah merasa bahwa apa yang diyakininya tersebut memang merupakan kebenaran mutlak. Ideologi ini oleh masyarakat umum biasanya dikaitkan dengan ideologi negara, atau partai, walaupun sebenarnya ideologi bisa berupa gaya hidup yang dibawakan lewat pesan-pesan dalam iklan.
Dalam upaya mempersuasi, iklan disampaikan tidak hanya dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan produknya secara terukur tetapi juga menyampaikan pesan bahwa ada nilai dan kualitas tertentu yang ikut serta ketika konsumen mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Jadi iklan membuat suatu struktur yang mampu mengubah suatu nilai kuantitatif yang rasional menjadi nilai kualitatif yang langsung berpengaruh pada emosi pemirsa.
Iklan sebenarnya memiliki fungsi yang bermacam-macam (Silverblatt, 1995, 178) :
1. Memberikan informasi kepada publik tentang suatu produk
2. Menarik perhatian konsumen kepada produk
3. Memotivasi konsumen untuk melakukan aksi (membeli)
4. Merangsang pasar
5. Menunjang komunitas usaha
6. Melanggengkan dan memelihara hubungan yang mempertahankan hubungan antara konsumen dan suatu perusahaan (produsen)
Disamping itu iklan juga menjalankan peran lain. Iklan menjual sesuatu yang lebih dari sekedar produk. Harus diperhatikan bahwa iklan tidak hanya berupaya untuk menjual kualitas-kualitas inheren dan atribut dari produk, tetapi juga juga berusaha agar barang-barang tersebut memiliki sesuatu makna tertentu kepada si pembeli. (Wlliamson, 1978: 12).
Kenneth Boulding dalam the Image menyatakan bahwa Image atau Citra tidak hanya membentuk masyarakat, tetapi masyarakat juga secara berkesinambungan mencipta ulang citra tersebut. Lingkaran ini menjadi salah satu faktor penting dalam memahami dinamika masyarakat. (Boulding, 1956: 64)
Dalam proses penyampaian pesan dari iklan terjadi suatu konstruksi makna yang dilakukan melalui penggambaran atau visualisasi iklan. Dalam konstruksi ini kemudian terjadi usaha untuk mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan segmentasi produk. Dalam pembuatan rancangan iklan juga terjadi upaya untuk memahami identitas dari target konsumen sehingga pengelompokan masyarakat terjadi bukan karena dari apa yang mereka ciptakan tetapi dari apa yang mereka konsumsi. Hal ini terjadi akibat dari hubungan timbal balik yang terjadi. Ketika suatu produk diarahkan untuk kelas sosial tertentu maka bisa terjadi ada kelas sosial yang berada di luar yang ingin masuk menjadi kelas sosial dari target konsumen dan berupaya membeli agar diterima menjadi kelas sosial yang ditujunya. Iklan-iklan sering melakukan pendekatan dengan cara menghubungkan produk tertentu dengan satu set kualitas atau keuntungan-keuntungan dalam benak konsumen. Penghubungan ini seringkali dicapai melalui penanaman kualitas produk ke dalam benak konsumen, Kemudian, kualitas tersebut akan berpindah dari produk kepada konsumen seketika setelah produk tersebut dibeli.
Pada dasarnya, hal ini berarti bahwa kita mendefinisikan diri kita berdasarkan apa yang kita miliki – dan iklan adalah jalur dimana kita mendapatkan identitas tersebut. (Williamson, 1998: 13)
Untuk memahami pesan-pesan iklan baik yang eksplisit maupun yang implisit dibutuhkan pengetahuan tentang sejarah dari masa iklan tersebut ditayangkan. Perubahan strategi dan pendekatan dalam membuat iklan seringkali juga dipengaruhi oleh situasi sosial dimana hal ini bisa difahami dengan mengetahui perkembangan sejarah yang terjadi. Situasi sosial dan budaya pada masa iklan tersebut dibuat akan mempengaruhi tampilan dari tokoh-tokoh tersebut sesuai dengan kebutuhan strategi persuasi dari iklan tersebut. Periklanan juga sering dianggap sebagai teks yang merefleksikan sikap dan nilai-nilai budaya. Termasuk di dalam pemahaman konteks budaya ini adalah upaya melihat bagaimana Ideologi dan Stereotype yang terjadi. (Silverblatt, 1995: 187).
Stereotyping sering dilakukan dalam merancang iklan karena para pengiklan memiliki waktu dan ruang yang terbatas dalam proses penyampaian pesan-pesan dalam iklan tersebut. Stereotyping dilakukan agar pemirsa mudah memahami isi pesan.
James T. Lull dalam buku Media Komunikasi Kebudayaan (1998) memberikan pernyataan tentang ideologi yang disimpulkan sebagai berikut: dalam melihat faktor ideologi dari suatu iklan maka akan didapatkan pemahaman bagaimana iklan didominasi oleh ideologi dan budaya yang berkuasa saat iklan tersebut ditayangkan. Pemilik media (massa) bisa digolongkan sebagai salah satu penguasa ideologis. Hal ini mendorong munculnya hegemoni. [2] Para pemilik media massa bersama sistem produksinya ini berperanan dalam penentuan dan penyebaran ideologi yang tersebar dalam isi media massa yang dikelolanya. Majalah dimana di dalamnya terdapat sekumpulan artikel, karikatur termasuk iklan yang terkadang saling terkait merupakan suatu sistem pesan. Jadi ideologi adalah “peta dari hal-hal yang dapat dimengerti” yang terarah, yang sebagian dari hal-hal itu dibuat lebih dapat diperoleh ketimbang yang lain-lain, bergantung pada siapa penguasanya, sedangkan media massa adalah “perkakas bagi representasi ideologi”. Para pemilik dan pengelola industri media dapat meproduksi dan mereproduksi isi, infleksi, dan nada dari ide-ide yang menguntungkan mereka dengan jauh lebih mudah ketimbang kelompok-kelompok sosial lain, karena mereka mengelola lembaga-lembaga sosialisasi utama, dan dengan demikian mendapat jaminan bahwa sudut pandang mereka secara tetap dan secara menarik disampaikan ke publik. Ideologi yang dimedia-massakan dibenarkan dan diperkuat oleh suatu sistem keagenan yang saling terkait dan efektif dalam mendistribusikan informasi dan praktek-praktek sosial yang sudah dianggap semestinya, yang merembesi segala aspek realitas dan sosial dan budaya. Pesan-pesan yang mendukung status quo yang dipancarkan dari sekolah, bisnis, organisasi politik, serikat buruh, organisasi keagamaan, militer, dan media massa semuanya saling menyesuaikan secara ideologis. Proses pengaruh ideologis yang saling mengartikulasikan, dan saling memperkuat ini merupakan esensi hegemoni. (Lull, 1997: 35).
Iklan menjadi satuan dari sistem ideologis yang terwujud dari penyelarasan dan kesepakatan berbagai pihak. Lebih dalam lagi bisa dilihat bahwa cara penggambaran sosok-sosok manusia yang terdapat dalam iklan tersebut merupakan proses sosialisasi nilai-nilai yang berakar dari ideologi tertentu.
6. Sosok manusia dalam iklan
Dari sudut konsumennya, Ada produk yang ditujukan untuk pribumi, orang Belanda dan ada juga yang lebih bersifat umum. Untuk kepentingan tersebut, Keduanya mempergunakan persepsi tentang strata sosial dan membawa suatu sistem kebudayaan melalui produk. Bangsa pribumi sebagai fihak yang dijajah biasanya dianggap sebagai bangsa yang lebih rendah dalam hal peradaban sehingga dianggap layak apabila diberikan peningkatan peradaban dengan cara diperkenalkan kepada produk-produk budaya modern. Di sisi lain, penggambaran bangsa pribumi juga seringkali dimanfaatkan sebagai obyek yang menjadi daya tarik eksotik pariwisata atau kebudayaan. Pemaknaan atau pencitraan ini diperoleh akibat dari pertemuan antar banyak kepentingan. Kepentingan pedagang, kepentingan kolonialis dan kepentingan pembaca majalah. Pedagang berkepentingan untuk menjual produk, sementara Belanda berkepentingan melanggengkan kekuasaannya di Hindia Belanda. Di dalam format kekuasaan tersebut terdapat suatu sistem strata sosial formal yang dibentuk oleh pemerintah Belanda yang kemudian berkembang secara sosial dalam bentuk reaksi dan upaya-upaya kelompok masyarakat meningkatkan strata sosialnya. Jadi, strata sosial yang lebih dulu terbentuk dalam masayarakat lokal diintervensi oleh sistem kolonial dan kemudian muncul reaksi-reaksi dari masyarakat.
Pada sebagian iklan bisa terjadi suatu penggambaran sosok manusia atau penggambaran adegan yang bisa menunjukan tatanan hubungan antar kelas manusia yang ada di Hindia Belanda atau lebih tepat lagi suatu pemahaman atas tatanan yang menjadi persepsi dari masyarakat yang dalam hal ini diwakili si produsen atau si perancang iklan tersebut. Hubungan antar kelas manusia ini terkait dengan cara bagaimana struktur sosial ini dibentuk ketika Indonesia mengalami kolonisasi oleh Belanda.
Dalam merancang iklan, seringkali dipergunakan sosok-sosok manusia yang dimanfaatkan sebagai tokoh atau karakter yang secara emosional dapat mewakili atau menjadi penghubung antara produk dengan target pemirsanya. Penggambaran tokoh ini dalam iklan biasanya bertujuan untuk membantu mengilustrasikan pemakaian produk atau menggambarkan suasana tentang bagaimana produk tersebut berperanan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana produk ini dipakai. Namun akibat dari kemunculan tokoh-tokoh dalam iklan tersebut, muncul suatu pencitraan tertentu yang melekat kepada produk. Produsen ingin mengidentifikasikan produk dengan suatu sosok manusia yang dianggap dapat menimbulkan citra positif dan kemudian terjadi asosiasi yang berkelanjutan antara sosok tersebut dengan produk. Pencitraan tersebut diharapkan akan memberikan nilai tambah kepada produknya.
Sebuah iklan selalu berupaya untuk menanamkan makna ke dalam pikiran orang dan karena makna-makna tersebut hanya ada di dalam konteks manusia, maka masuk akallah bila mayoritas dari iklan berisi gambar (images) manusia (Fowles, 1996:149). Dengan penggambaran tersebut maka pesan yang ingin disampaikan akan lebih mudah dan lebih cepat sampai dibandingkan dengan tulisan.
Sosok manusia juga bisa dimanfaatkan sebagai pembawa citra tertentu karena manusia memiliki bebagai nuansa karakter, golongan, kelas sosial, dan hal ini akan dapat mendukung pencitraan positif bagi produk yang diwakilinya. Sosok manusia yang digambarkan dalam iklan-iklan tersebut tidak terlepas dari ideologi masyarakat pada jaman itu. Masyarakat, baik dari sisi produsen, pembuat iklan, maupun pembaca, dan konsumen telah memiliki persepsi tertentu terhadap sosok-sosok manusia yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat diasosiasikan kepada kelompok masyarakat sosial yang terbentuk di masa itu. Ciri-ciri tertentu ini selain melekat pada etnisitas dari sosok manusia tersebut, juga melekat pada pakaian dan atribut lain seperti peci, ikat kepala dan lain-lain.
Iklan biasanya mempergunakan ilustrasi sebagai unsur utama dalam menyampaikan pesan-pesannya. Ilustrasi dalam iklan adalah suatu gambar yang berfungsi mendampingi teks dari iklan sehingga pesan dari iklan itu menjadi lebih jelas. Seringkali digambarkan suatu adegan untuk membuat pemirsa yakin tentang kemanjuran obat, produk atau untuk memberikan sugesti yang memperkuat pesan dari poster atau reklame tersebut. Dalam pembuatan ilustrasi tersebut, dapat kita temui penggambaran dari sosok manusia-manusia yang hidup di Hindia Belanda yang selain bisa digolongkan ke dalam kelompok etnis atau bangsa (Belanda, pribumi dan Asia lain) juga bisa dilihat adanya perbedaan kelas masyarakat. Penggambaran tersebut menghasilkan pencitraan tertentu dari masing-masing kelompok masyarakat. Bangsa pribumi umumnya digambarkan sebagai bangsa yang terkebelakang, sementara bangsa Belanda sebagai bangsa yang membawa peradaban dan bangsa non Eropa pendatang sebagai bangsa yang menjadi mitra dagang dari bangsa Belanda.
7. Metode Penelitian
Penelitian dilakukan melalui penelitian langsung pada sumber data primer dan melalui kajian pustaka. Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu:
a. Mendeteksi majalah yang cocok untuk dijadikan lingkup penelitian yaitu majalah-majalah yang diterbitkan di Hindia Belanda di antara tahun 1922-1942. Dari koleksi perpustakaan Nasional di Jakarta, dipilih majalah yang banyak memuat iklan-iklan yang berragam dan menggunakan sosok manusia dalam penggambaran rancangannya. Telah terkumpul sejumlah 353 iklan yang menggambarkan sosok manusia.
b. Penelitian awal untuk mendapatkan gambaran umum tentang iklan pada periode yang dituju dengan mempergunakan bahan pustaka dan melihat langsung contoh-contoh iklan yang bisa didapat dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan sample dengan mempergunakan kriteria tertentu atas pilihan. Yang diutamakan dalam memilih sample adalah iklan-iklan yang dalam penggambarannya menggunakan nuansa khas Hindia Belanda pada saat itu, baik dari segi tokoh yang muncul, maupun penggambaran latar belakangnya.
7.1. Postur, sikap tubuh, pakaian dan komposisi adegan sebagai sarana komunikasi
Pengertian postur disini dibedakan dengan sikap tubuh. istilah postur dalam penelitian ini dimaksudkan untuk merujuk kepada bentuk dan ukuran tubuh, dan warna kulit, yang mencerminkan juga ras atau etnik sosok manusia yang tergambar. Sikap tubuh adalah posisi tubuh seseorang ketika ia berdiri atau duduk: tegak, bungkuk, jongkok, dan seterusnya. Postur dan sikap tubuh dari sosok ditambah dengan tanda-tanda etnisitas, pakaian yang dikenakan, dan bagaimana tokoh ini ditampilkan dalam suatu adegan, merupakan tanda-tanda visual yang bisa dimaknai. Pakaian yang dipakai oleh tokoh dalam iklan akan mencerminkan siapa dan latar belakang sosok manusia yang tergambar.
Demikian juga dengan adegan. Dalam suatu iklan, adegan yang disusun oleh ilustrator / fotografer akan memberikan pesan-pesan tertentu. Bagaimana suatu tokoh dihadapkan pada sosok yang lain dan hubungan yang terjadi akibat keberadaan tokoh-tokoh dalam satu adegan akan memunculkan pemaknaan yang berbeda-beda.
Selain dari sosoknya sendiri, pemaknaan bisa muncul dari bagaimana latar belakang dari tokoh tersebut ditampilkan dalam bentuk gambar. Sebagai perbandingan, dalam tehnik fotografi, hal tersebut menjadi unsur yang penting dalam upaya menampilkan “identitas” atau citra dari orang yang difoto. Akan lebih mudah mengidentifikasi seseorang dengan latar belakang yang membantu menjelaskan siapa orang tersebut. (Berger, 1989: 67). Sebagai media yang sama-sama menggunakan persepsi indera mata, gambarpun memiliki prinsip yang kurang lebih sama. Dalam suatu gambar tentang tokoh, bisa ditampilkan latar belakang atau penampilan dari obyek lain atau tokoh lain yang disandingkan dengan obyek utama sehingga informasi tentang siapa dan bagaimana tokoh utama tersebut akan lebih jelas.
Pakaian berfungsi mengomunikasikan keanggotaan dari satu kelompok kultural baik pada orang-orang yang menjadi anggota kelompok tersebut maupun bukan. (Barnard, 1996: 83). Berbedanya pakaian dari satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain bisa dikarenakan tradisi yang kemudian bisa terjadi percampuran antar kultur tetapi bisa juga disebabkan oleh unsur kekuasaan yang mengatur tata cara berpakaian antar kelompok sosial tertentu. Dengan kata lain, pakaian bisa berfungsi sebagai penanda akan identitas seseorang. Selain itu pakaian bisa dilihat sebagai alat untuk mengekspresikan diri atau kelompok.
Postur, pakaian dan komposisi adegan adalah merupakan sistem tanda. Karena makna yang timbul akibat dari hubungan antar tanda-tanda tersebut bersifat arbitrer, maka untuk memahami kelompok tanda-tanda tersebut, dibutuhkan pemahaman atas kode. Kode dapat dilihat sebagai cara untuk memahami tanda-tanda sebagai sistem konvensi yang diajarkan atau berdasarkan adat, kebiasaan, dan kebudayaan (Berger, 1989: 31).
Oleh karena itu latar belakang pendidikan dan budaya dari orang yang mempersepsi akan mempengaruhi pemaknaan dari tanda-tanda dan sistem kode tersebut. Selain itu, untuk memperkaya pemaknaan dari tokoh-tokoh yang muncul dalam iklan-iklan, dilakukan analisis dengan memperhatikan masalah hubungan antar tokoh secara ruang yaitu bagaimana suatu obyek dibandingkan dengan obyek lain dalam suatu bingkai gambar. Dengan disandingkannya suatu obyek dengan obyek lain maka obyek tersebut akan memiliki makna tertentu. Di samping itu skala atau perbandingan besar gambar antara obyek yang satu dengan yang lainnya juga akan membawa dampak emosional. Demikian juga dengan bagaimana suatu obyek atau tokoh yang diletakkan di ruang yang sempit akan berbeda dampak emosionalnya ketika obyek tersebut diletakkan dalam ruang yang luas. Kondisi dan ukuran ruang juga akan meyampaikan pesan yang berbeda-beda. Ruang yang relatif besar atau lega akan terasosiasi pada kelas sosial atas dan sebaliknya, ruang yang sempit dan pengap akan berasosiasi pada kelas sosial bawah. (Berger, 1989: 44)
Skala merujuk kepada ukuran relatif antar obyek-obyek. Skala adalah suatu cara yang paling mendasar dalam menyampaikan pesan: semakin besar suatu obyek tampil, maka akan semakin penting juga obyek itu akan terlihat. (Silverblatt, 1995:101).
Posisi obyek tersebut ditempatkan pada suatu ruang juga menjadi penting karena akan menyampakan makna yang berbeda. Bagaimana suatu obyek atau tokoh ditempatkan dalam suatu halaman / bidang akan menyampaikan pesan yang khusus kepada pemirsa. Obyek yang muncul mengarah ke depan (arah pembaca) maka akan segera menarik perhatian, sementara benda-benda di latar belakang secara umum dianggap sebagai sekunder. (Silverblatt, 1995:102)
7.2. Denotasi, Konotasi, Kode, dan Mitos
Denotasi dan Konotasi adalah istilah yang dipergunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara petanda dan penanda (signifier dan signified). Denotasi cenderung merupakan makna yang bersifat definisional, literal, pasti, atau akal sehat dari suatu tanda. Sementara Konotasi lebih ditujukan untuk pemaknaan asosiatif yang bersifat sosio-kultural dan ‘pribadi’ (ideologis, emosional dll.) dari suatu tanda. Konotasi lebih terkait dengan pada kelas sosial, usia, kelamin, etnisitas dan seterusnya. (Chandler, 2002: 140). Dalam penggunaannya baik tanda konotatif maupun tanda denotatif akan menggunakan Kode-kode.
Kaitan antara Konotasi dengan Mitos diterangkan Roland Barthes dengan mengetengahkan konsep konotasi yang dimulai dari pengembangan segi tiga signifié (petanda, “makna”) dari Pierce oleh pemakai bahasa. Pada saat konotasi menjadi mantap, ia menjadi mitos, dan ketika mitos menjadi mantap, ia menjadi ideologi. (Hoed, 2007: 153)
Dalam semiotik konsep Kode ini cukup mendasar. Saussure menekankan bahwa suatu tanda tidak banyak bermakna jika berdiri sendiri. Tanda akan lebih memiliki makna ketika diinterpretasikan dalam hubungannya dengan tanda-tanda yang lain. Seorang ahli linguistik struktralis yang lain, Roman Jakobson berpendapat bahwa penciptaan dan interpretasi dari suatu teks bergantung kepada eksistensi dari Kode-kode atau kesepakatan untuk komunikasinya. Karena makna dari suatu tanda bergantung kepada keberadaan Kode dimana tanda itu berada, maka Kode akan menjadi suatu kerangka kerja dimana di dalamnya tanda akan memiliki makna. Kaitannya dengan konsep tanda dan petanda adalah bahwa kode-kode akan menyusun tanda-tanda menjadi sistem yang bermakna yang menghubungkan tanda dengan petanda. (Chandler, 2002: 147)
Daniel Chandler membagi Kode-kode menjadi 3 (Chandler, 2001: 149) :
a. Kode Sosial:
- bahasa verbal (subkode phonologis, sintaksis, leksikal, prosodic, dan paralinguistik)
- bahasa tubuh (kontak tubuh, kedekatan, orientasi fisik, penampilan, ekspresi wajah, tatapan, anggukan kepala, gestur dan postur)
- komoditas (fesyen, pakaian, mobil)
- perilaku ( protokol, ritual, role-playing, games)
b. Kode Tekstual:
- Kode-kode ilmiah, termasuk matematika
- Kode-kode estetis termasuk di dalamnya berbagai macam seni (puisi, drama, seni lukis, patung, musik dan lain-lain) - termasuk klasikisme, romatisisme, realisme.
- Kode-kode genre, rethorical, stylistic; eksposisi, argumen, deskripsi dan narasi, dan seterusnya
- Kode-kode media massa termasuk fotografi, televisual, filmis, radio, surat-kabar, majalah, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat konvensional (termasuk formatnya)
c. Kode Interpretatif:
- Kode-kode perceptual (termasuk kode visual)
- Kode-kode ideologis [3]
Dengan cara yang berbeda Roland Barthes menyampaikan juga konsep Kode tersebut. Ia menyatakan suatu konsep tentang adanya rantai asosiasi yang membentuk narasi dari suatu gambar. Istilah yang sering digunakan untuk rantai asosiasi inilah yang disebutnya sebagai Kode. Masyarakat memiliki suatu sistem Kode yang kompleks yang menjadi referensi dari anggota masyarakat tersebut dalam berkomunikasi dan memahami masalah sehari-hari. Kode ini tercipta setelah melalui waktu sosialisasi yang lama (sejarah dan adat kebiasaan).
Lebih jauh lagi, John Fiske menguraikan sejumlah sifat dasar dari kode: Kode mempunyai sejumlah unit (atau kadang-kadang satu unit) sehingga seleksi bisa dilakukan. Inilah dimensi paradigmatik. Unit-unit tersebut (kecuali unit tunggal kode on-off sederhana) mungkin bisa dipadukan berdasarkan aturan atau konvensi. Inlah dimensi sintagmatik. Semua kode menyampaikan makna: unit-unit kode adalah tanda-tanda yang mengacu pada sesuatu di luar dirinya sendiri melalui berbagai sarana. Semua kode bergantung pada kesepakatan di kalangan para penggunanya dan bergantung pada latar belakang budaya yang sama. Kode dan budaya berinterelasi secara dinamis. Semua kode menunjukkan fungsi sosial atau komunikasi yang dapat diidentifikasi. Semua kode bisa ditransmisikan melalui media dan / atau saluran komunikasi yang tepat. (Fiske, 1990: 92)
Barthes juga mengungkapkan kosepsi tentang Mitos. Mitos adalah suatu sistem komunikasi, atau jelasnya ‘suatu pesan’. Mitos tidak dapat menjadi sebuah obyek, konsep atau ide, karena mitos adalah suatu ‘cara pemaknaan’, suatu bentuk. Bentuk ini harus punya batasan historis, mempunyai komunitas dan masyarakat harus menjadi bagian dari mitos. Mitos tidak ditentukan oleh obyek pesannya, namun oleh cara mitos mengutarakan pesannya sendiri. Semua di alam ini punya potensi menjadi mitos. Sejarah manusia mengubah realitas menjadi wicara, dan sejarah juga mengatur hidup matinya bahasa mitis. Sejak masa kuno sampai sekarang, mitos selalu punya landasan historis oleh karena tipe wicara (type of speech) yang terbentuk telah dipilih oleh sejarah (Barthes, 1957: 109).
Menurut Barthes, mitos tidak hanya terjadi dalam wacana tertulis, namun juga berbentuk fotografi, sinema, reportase olah raga, pertunjukan, dan semua hal yang bisa dipakai sebagai pendukung wicara mitis. Persepsi yang timbul karena tulisan, tidak berada dalam kategori yang sama dengan persepsi visual yang terjadi karena melihat gambar. Dengan gambar seseorang dapat menggunakan banyak ragam pembacaan. (Barthes 1957: 110).
Barthes juga menyatakan bahwa wicara mitis, dibangun oleh materi yang telah dibuat sedemikian rupa agar cocok untuk komunikasi. Materi mitos mensyaratkan kesadaran akan pemaknaan, meskipun dengan mengabaikan arti harafiah sebuah bentuk. Dalam mitos suatu gambar lebih bersifat imperatif daripada uraian tertulis, gambar-gambar memaksakan makna dengan seketika (Barthes 1957: 110).
Dalam menganalisa penggambaran tokoh-tokoh digunakan pendekatan konsep Konotatif karena dirasakan akan lebih memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang citra-citra yang terjadi akibat penggambaran sosok manusia menjadi tokoh-tokoh dalam iklan, terutama karena iklan-iklan ini dilihat dalam konteks dan perspektif sejarah dan budaya yang mempengaruhi kemunculan tokoh-tokoh dalam iklan tersebut. Iklan juga dilihat sebagai media komunikasi (massa) dimana dalam prosesnya terjadi proses encoding dan decoding dari pesan yang disampaikan melalui media (cetak).
8. Hasil pengumpulan dan klasifikasi iklan dari majalah De Zweep / D’Orient dan Pandji Poestaka
Dari kedua majalah - De Zweep / D’Orient dan Pandji Poestaka dikumpulkan 353 iklan, yaitu, De Zweep 65 iklan. D’Orient 169 iklan, dan Pandji Poestaka 119 iklan. Dari ketiga majalah setelah satu persatu dihitung dari masing-masing iklan, maka terlihat bahwa tokoh Laki-laki Barat sebanyak 272 sosok paling banyak digunakan dalam iklan. Di urutan kedua adalah Laki-laki Pribumi yaitu 216 sosok, kemudian Perempuan Barat 209 sosok dan perempuan pribumi sejumlah 82. Sementara Pria Afrika 15 orang, Pria Cina 8, dan Pria Arab 8.
8.1. Klasifikasi sosok manusia dalam majalah D’Orient tahun 1922 – 1942
Dari data iklan yang menggambarkan tokoh, didapatkan tokoh - tokoh yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pemilahan pertama adalah pada etnis dan jenis kelamin. Selanjutnya pengelompokan besar tadi ditinjau berdasarkan ciri-ciri fisik yang melekat pada tokoh, diuraikan lagi tokoh-tokoh tersebut ke dalam berbagai posisi sosial, profesi atau kelas pekerja yaitu:
a. Perempuan Barat: Ibu Rumah Tangga, Pekerja Profesional
b. Laki-laki Barat
c. Perempuan Pribumi : Ibu Rumah Tangga, Babu/Emban/Koki, Pekerja Profesional
d. Laki-laki Pribumi: Priyayi, Pekerja Kasar, Jongos/Pelayan, Tokoh muslim
e. Arab
f. Afrika
g. Cina
8.2. Perempuan pribumi
Perempuan Indonesia mengalami proses perkembangan yang cukup signifikan pada awal abad ke-20. Setelah Sumpah Pemuda, pada tanggal 22 Desember 1928, dilangsungkan Kongres Perempuan Indonesia nasional pertama di Yogyakarta. Kongres ini bisa dikatakan sebagai dasar bagi gerakan perempuan Indonesia selanjutnya. Kemudian, Kongres Perempuan yang kedua dilangsungkan di Jakarta pada tahun 1935 dan pada tahun 1938 dilangsungkan kongres yang ketiga.
Dari majalah-majalah yang diteliti, ditemukan penggunaan tokoh perempuan pribumi sebagai berikut:
a. Ibu rumah tangga atau isteri
b. Koki atau pembantu rumah tangga
Perempuan Indonesia saat itu sudah memiliki profesi selain dari ibu rumah tangga. Perempuan pribumi sudah menjadi guru, sarjana hukum, perawat, pegawai, pengrajin, pemilik perusahaan, pedagang dan lain-lain. Akan tetapi dalam iklan, profesi dari sosok perempuan baik pribumi maupun Barat tidak banyak ditampilkan secara jelas. Peran perempuan pada saat itu memang tidak bisa dilepaskan dari peran dalam rumah tangga. Dalam Kongres Perempuan yang pertama, secara tidak langsung, sudah nampak semangat dari para pembicara untuk mengangkat masalah pentingnya keprofesian perempuan selain dari kegiatan perempuan di rumah.
R.A. Soekonto sebagai Ketua Kongres menyampaikan suatu pernyataan tentang perlunya perempuan Indonesia melangkah maju. ” Dewasa ini telah terlihatlah kepentingannya pergerakan kaum perempuan. Zaman kaum perempuan hanya dianggap baik untuk tinggal di dapur saja itu zaman kuno. Zaman sekarang adalah zaman kemajuan. Oleh karena itu, zaman ini sudah waktunya mengangkat derajat kaum perempuan agar kita tidak terpaksa duduk di dapur saja” (Blackburn, 2007, 138). Akan tetapi dia tetap mengingatkan bahwa perempuan juga masih harus berada di dapur. Ia mengatakan lebih lanjut ” Sudah pasti perkataan saya ini tidak bermaksud melepaskan perempuan Indonesia dari dapur. Kecuali harus menjadi nomor satu di dapur, kita juga harus turut memikirkan pandangan kaum laki-laki sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwa laki-laki dan perempuan harus berjalan bersama-sama dalam kehidupan umum.” (Blackburn, 2007, 138).
Tien Sastrosuwirjo salah satu pembicara dalam Kongres perempuan membahas salah satu kewajiban perempuan Indonesia yaitu “Kewajiban perempuan adalah harus setia kepada suaminya, bangsanya, tanah tumpah darahnya, dan harus cinta kepada anak-anaknya. Inilah yang menjadi tugas perempuan karena semua pekerjaan, adat-istiadat, sopan santun itu keluar dari ingatan dan pikiran dahulu”. (Blackburn, 2007, 199).
Nilai-nilai yang dianut masyarakat saat itu, walaupun sudah mulai mendapat masukan pemikiran yang progresif tentang pekerjaan perempuan namun tetap memberi tekanan bahwa perempuan tidak dapat meninggalkan tugas di dapur dan mengurus keluarga.
Pakaian perempuan yang umum pada saat itu adalah kain dan kebaya. Memang pakaian Barat seperti gaun atau rok juga sudah mulai dipergunakan namun ketika itu, penggunaan pakaian Barat atau modifikasi dari pakain tradisionil, oleh perempuan masih mendapat pertentangan. Mengutip Nonah Srijati seorang perancang mode dari majalah Doenia Kita “Mode jang dipakai sekarang ini oleh poetri kita seringkali mengetjewakan modelnja. Asal sadja namanja model baroe, pantas tidak pantas dipakai sadja…..Menoeroet pendapat saja pakaian Solo dan Djokdja jang aseli itulah jang harmonisch dengan segala-galanja.” (Doenia Kita no. 3, Maret 1940, 12)
8.2.1. Perempuan Pribumi, Ibu Rumah Tangga
Dari segi pakaian, Ibu rumah tangga dan perempuan pekerja rumah tangga ( koki, emban, babu), digambarkan sama-sama menggunakan kain dan kebaya. Yang dapat membedakan antara keduanya adalah pada penggunaan perhiasan oleh ibu rumah tangga seperti giwang, dan gaya dari kebaya yang digunakan. Ibu rumah tangga digambarkan lebih rapi dan banyak menggunakan hiasan pada kebaya. Kemudian pada beberapa iklan, kebaya ibu rumah tangga digambarkan lebih ketat. Posisi tubuh perempuan pribumi dan perempuan Barat tidak berbeda, hanya sikap tubuh, postur dan pakaiannya saja yang berbeda. Ekspresi wajah yang tersenyum menunjukkan keceriaan dan sikap tubuhnya yang tegak menunjukkan kepercayaan diri. Pada beberapa gambar pengenalan identitas ini hanya bisa dilakukan setelah tokoh tersebut berada dalam bingkai iklan sebagai konteks.
8.2.2. Pekerja rumah tangga (Babu, emban, koki)
Pekerja rumah tangga adalah para perempuan pribumi yang bekerja di rumah tangga keluarga bangsa Belanda atau Indo. Seperti umumnya para pekerja domestik pribumi pada zaman itu, dalam iklanpun mereka digambarkan menggunakan pakaian tradisonal Jawa, baik itu berupa kebaya dan kain maupun hanya kemben (hanya kain batik yang dililit dari dada hingga ke bawah lutut).
Dapat dilihat dari penampilan dari tokoh bahwa pakaian yang dikenakan adalah pakaian tradisional daerah jawa yaitu kebaya dan kain (batik) dengan gaya penataan rambut gelung konde tradisional. Biasanya, mereka digambarkan tidak mempergunakan perhiasan. Posisi tubuhnya sering digambarkan berjongkok atau bersimpuh. Dari letaknya terhadap gambar perempuan pelayan sering digambarkan berada di posisi bawah.
Secara fungsional ada 2 hal yang membuat tokoh pelayan atau koki perempuan menjadi subyek utama dari iklan yaitu diaitan dengan fungsi produk dan untuk memposisikan produk kepada konsumen. Tokoh koki dan pelayan dipergunakan untuk menunjukkan bahwa pengguna produk ini adalah masyarakat yang memiliki koki dalam struktur rumah-tangganya. Dengan begitu, posisi produk juga menjadi terangkat ke tingkatan yang lebih tinggi. Di sisi lain bisa dilihat juga bahwa masyarakat yang membeli produk seakan-akan juga menjadi terangkat kelas sosialnya bila memakai produk tersebut walaupun tidak memiliki koki dalam rumah tangganya.
8.3. Laki-laki pribumi
Dalam iklan, tokoh laki-laki pribumi muncul dalam berbagai kelas sosial. Priyayi adalah salah satu tokoh yang muncul. Seperti telah diuraikan di bab sebelumnya, yang disebut dengan istilah priyayi selain kelompok bangsawan adalah juga mereka yang bekerja di kantor baik itu pemerintahan atau swasta. Mereka umumnya berpendidikan. Dari segi pakaian, ada yang berorientasi pada kebudayaan Jawa dan ada yang memakai pakaian gaya Barat. Dari iklan-iklan yang didapat, terlihat bahwa semakin mendekati tahun 1942, semakin sedikit penggambaran priyayi dengan baju daerah dan lebih banyak dengan mempergunakan pakaian Barat dengan peci. Dari orientasi pada kebudayaan Jawa menjadi berorientasi pada citra intelektual Barat dan lebih bersifat nasional.
Berpakaian gaya Eropa menjadi suatu indikasi bahwa seseorang mendukung perkembangan ide-ide progresif. Ini menunjukkan bahwa seseorang menjadi bagian dari suatu gerakan modern baru, bukan saja untuk menuntut kebebasan politik yang lebih besar dari Belanda, melainkan juga memprotes tata krama dan etiket kaum elit masyarakatnya sendiri. (Nordholt, 1997, 59).
Tentang cara berpakaian, Soekarno, presiden Republik Indonesia pertama, turut mempelopori gaya berpakaian Barat dengan peci ini. Di tahun 1920-an Soekarno memang sudah menolak menggunakan pakaian Bumiputera (kain atau sarung dan pakaian Jawa). Sarung (pakaian tradisonil Indonesia) menurutnya tidak sesuai dengan Indonesia Baru dari masa datang. “Kita harus melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh masa lampau yang merangkak-rangkak seperti pelayan, jongos dan orang dusun yang tidak bernama dan tidak berupa. Mari kita tunjukkan bahwa kita sama progresif dengan orang Belanda. KIta harus tegak sama tinggi dengan mereka. Kita harus memakai pakaian modern,” (Adams, 2000, 112). Penggunaan peci, sesuai pernyataan Soekarno di uraian sebelumnya, sudah cukup meluas.
Peci juga digunakan oleh “wong cilik” yaitu para pekerja kasar dan buruh selain oleh pegawai kantor. Pada sebagian iklan digambarkan laki-laki pribumi yang bekerja tidak di di belakang meja. Mereka ada yang membawa pacul, ada yang bekerja mengecat, menjadi kuli angkut dan lain-lain. Pakaian mereka bisa telanjang dada, baju tanpa kerah tanpa kancing, atau baju putih lengan pendek. Selain peci, para pekerja yang tidak bekerja di kantor ini menggunakan ikat kepala atau sebagian tidak memakai tutup kepala. Bagian bawah biasanya menggunakan celana pendek atau celana tanggung. Mereka bisa juga disebut pekerja “kasar” yang termasuk diantaranya adalah petani, kuli bangunan, kuli angkut, atau termasuk juga disini pekerja yang memiliki keterampilan seperti mengecat (tukang). Dalam iklan sering ditampilkan tokoh pekerja yang sedang melakukan pekerjaan menggunakan produk yang diiklankan.
Jongos adalah sebutan untuk laki-laki pribumi yang bekerja sebagai pelayan, membersihkan rumah atau melayani keperluan majikan khususnya di era kolonial Hindia Belanda.
Dalam suatu rumah-tangga keluarga Belanda, posisi seorang jongos (bersama babu) dalam struktur jelas berada di strata paling bawah. Dari sisi lain, kita bisa melihat bahwa dalam posisi itulah seorang pribumi bisa menjadi sangat dekat dengan keluarga Belanda di Hindia Belanda. Kedekatan jongos dengan suatu keluarga Belanda bisa dianggap sebagai “keuntungan” yang membedakannya dengan pribumi lain. Bahkan, menurut Robert van Niel dalam buku Munculnya Elite Modern Indonesia, seorang pembantu rumah tangga seorang Eropa di atau keluarga Indonesia yang terkemuka dipandang sebagai lapisan tertinggi oleh karena dianggap setidak-tidaknya turut dalam kedudukan dan sukses majikan mereka. (Niel. 2009: 41). Bisa jadi hal tersebutlah yang mengakibatkan seorang jongos menjadi sah untuk muncul dalam bingkai adegan yang sama dengan orang Belanda dalam suatu iklan karena ia merupakan bagian dari struktur rumah tangga. Jongos muncul dalam iklan dengan berbagai produk.
Sosok lainnya yang muncul dalam iklan adalah sosok Tokoh muslim. Tokoh ini adalah pribumi yang memilki ketaatan yang kuat dalam beribadah (Islam) sebagian dari mereka memang berprofesi sebagai pedagang, tetapi sebagian lagi bekerja sebagai pengurus masjid, menjadi penguhulu, ulama, atau profesi lain. Mereka umumnya berasal dari kalangan organisasi Muslim seperti misalnya Syarikat Dagang Islam. Di kota-kota Jawa mereka disebut Sodagar. Mereka mengisi sektor-sektor yang belum dijamah oleh orang Tionghoa seperti perdagangan tengkulak tembakau, tekstil, kerajinan rumah tangga dan ikan asin. Ada juga yang memiliki usaha yang lebih besar seperti batik tulis yang mempekerjakan 15 hingga 30 pengrajin atau ada juga yang berusaha di bidang rokok. Mereka sering disebut juga sebagai Kauman walaupun tidak semua orang Kauman berprofesi sebagai pedagang. (Koentjaraningrat, 1984, 232-233).
Antara Santri yang berprofesi sebagai sodagar dan yang bukan tidak dibedakan. Masyarakat cenderung menyamakan dan menyebutnya sebagai Santri. Dalam iklan, ditemukan sosok yang menggunakan atribut-atribut khas yang biasanya dipakai kaum Muslim yaitu sorban sebagai tutup kepala atau turban, sarung dengan jas. Cara berpakaian seperti ini juga tampak digunakan pemimpin politik berlatar belakang Islam seperti Haji Agoes Salim. Di harian De Locomotief (19-05-1921) dituliskan bahwa pada pembukaan sidang Volksraad tanggal 17 Mei 1921, ketika peserta yang hadir kebanyakan berpakaian lengkap dan resmi seperti jas, uniform dengan tanda-tanda penghargaan, jarik dan jas dilengkapi keris (bagi orang Jawa), Haji Agoes Salim datang dengan pakaian sederhana yaitu jubah panjang kecoklatan dengan ikat putih melilit pici hajinya. Pada saat itu cara berpakaian Haji Agoes Salim dianggap tidak layak oleh hadirin. Menurut kebiasaan, untuk acara semacam itu, hanya pakaian Barat dan pakaian pribumi yang paling mahal yang pantas dipakai.
Perbedaan antara Sukarno dan Haji Agoes Salim dalam berpakaian merupakan perlambangan dari startegi perjuangan mereka melawan ideologi kolonial. Sukarno dengan cara menggunakan simbol Barat yaitu pantalon dan jas yang dimodifikasi dengan unsur Timur yaitu peci. Haji Agoes Salim dengan bersikukuh pada pakaian yang umum digunakan oleh orang Islam sebagai simbol untuk melawan nilai-nilai Barat.
Penggambaran tokoh laki-laki pribumi dalam iklan memiliki keberagaman yang tinggi. Hal ini disebabkan karena laki-laki pribumi memiliki rentang variasi pekerjaan yang besar. Mulai dari jongos, pekerja kasar, pegawai, priyayi hingga seorang bangsawan.
8.3.1. Priyayi
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya mengenai strata sosial di Hindia Belanda, ada banyak klasifikasi priyayi. Pada klasifikasi pertama yaitu priyayi yang benar berdarah bangsawan, ditampilkan laki-laki berpakaian seperti seorang bupati atau pangeran. Pada klasifikasi kedua priyayi ditampilkan berpakaian tradisionil dengan blangkon, kain dan jarik / beskap. Klasifikasi ini berlatar belakang tradisi pangreh praja yang kemudian menjadi pegawai negeri. Klasifikasi ketiga adalah priyayi yang “modern” karena berpakaian ala Barat plus peci. Profesi priyayi ketiga ini ada yang menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, profesional, dan kalangan intelektual.
8.3.2. Laki-laki pribumi pekerja kasar
Profesi pekerja kasar juga memiliki tampilan yang beragam. Mulai dari petani yang memakai ikat kepala dan berbaju tradisionil, atau telanjang dada. Ada juga pekerja kasar yang menggunakan peci dan kemeja. Untuk pekerjaan yang lebih “halus” seperti tukang cat, bisa digambarkan seseorang yang berkemeja ala Barat dan peci dengan celana panjang atau celana pendek tanpa alas kaki.
Tanda (sign) utama dari laki pribumi pekerja kasar adalah “laki-laki pribumi”. Signifier laki-laki pribumi + signified pakaian tradisi petani / kemeja lengan pendek / telanjang dada + ikat kepala / peci + peralatan kerja sikap tubuh tegap. Ekspresi wajah ceria. memiliki makna konotatif pekerja kasar
8.3.3. Laki-laki pribumi jongos / pelayan
Posisi berikutnya adalah jongos atau pelayan laki-laki. Karena kemunculan jongos atau pelayan laki-laki ini merupakan hasil konstruksi bangsa Belanda dan menjadi bagian dari struktur sosialnya, maka penampilan jongos sudah cukup seragam. Atribut yang dipakai seorang jongos sudah jelas: ikat kepala, baju putih, sarung /kain batik dipakai setengah tinggi yang diapakai dibawah baju, dan celana panjang putih tanpa alas kaki. Atribut lain adalah serbet yang disampirkan di bahu, di lengan atau dilekatkan dengan peniti di bagian dada. Ekspresi wajah digambarkan lugu, tertawa, dan berkesan kurang cerdas. Sikap tubuhnya cenderung membungkuk.
8.3.4. Tokoh muslim
Tokoh muslim ada yang menggunakan pakaian gamis tetapi ada juga menggunakan pakaian Muslim atau Timur Tengah yang dikombinasi dengan pakaian tradisionil seperti sarung dan pakaian Barat. Tokoh Muslim yang bekerja sebagai pengusaha atau pedagang biasanya membutuhkan tas untuk menyimpan catatan pekerjaan atau usaha dagangnya. Selain berdagang sebagain dari tokoh Muslim bekerja untuk kepentingan agama, seperti menjadu Ulama, pengurus mesjid, guru madrasah, dan lain-lain.
8.4. Perempuan Barat
Perempuan Barat yang dimaksud disini umumnya adalah perempuan Belanda yang menetap di Hindia Belanda karena mengikuti suaminya bekerja atau memang sudah dilahirkan di sini. Walaupun tinggal di negara tropis, perempuan Belanda saat itu umumnya sudah tidak mau menggunakan pakaian tradisonil Jawa, berbeda dengan masa sebelumnya sekitar tahun 1900-an.
Seperti halnya para perempuan pribumi, dalam iklan, tidak banyak penggambaran tentang profesi mereka. Hampir sama dengan kenyataannya, dalam iklan, mereka hanya diberi peran sebagai ibu rumah tangga, perawat, atau seorang perempuan yang tidak memiliki ciri-ciri keprofesian tertentu. Mereka dalam berpakaian mengikuti kecenderungan tata busana yang berlaku di Barat, baik pakaian, maupun tata rambut. Dalam iklan, dari tahun ke tahun, terlihat perbedaan tata busana mereka.
Perempuan Barat menggunakan pakaian ala Barat (gaun). Penggambaran mode busana dalam iklan umumnya selalu disesuaikan dengan kecenderungan gaya zaman itu. Sosok ini bisa dikatakan sebagai seorang ibu rumah tangga setelah memiliki tanda tambahan lain seperti celemek, dan perangkat yang berkaitan dengan rumah tangga. Celemek dan perangkat dapur tersebut untuk menandakan bahwa ia sedang bertugas memasak di dapur. Dalam iklan cukup banyak digambarkan sosok perempuan Barat lain yang tidak memiliki tanda - tanda tersebut secara spesifik. Sosok perempuan tersebut beraktifitas selain kegiatan yang biasa dilakukan di rumah seperti sport, jamuan makan, dan lain-lain.
8.5. Laki-laki Barat
Laki-laki Barat yang dimaksud disini adalah laki-laki Belanda atau Indo yang tinggal dan bekerja di Hindia Belanda. Mereka umumnya bekerja sebagai karyawan atau menduduki posisi kepala perusahaan atau kepala kantor pemerintahan. Dalam gambar iklan, mereka sering digambarkan menggnakan jas tutup putih dengan pantalon. Yang menjadiciri khasnya juga adalah topi “safari” atau topi “wedana”. Pakaian jenis ini sudah digunakan sejak sebelum masa tahun 1920-an. Selain itu pakaian yang sering digunaka oleh pria Barat / Belanda adalah jas, kemeja dengan dasi dan pantalon.
8.6. Asia lain (Cina, Arab termasuk Afrika)
Pada iklan juga tidak banyak ditemukan penggambaran sosok Asia lain atau Afrika. Asia lain adalah pengelompokan masyarakat Asia selain Indonesia (pribumi) atas asal-usul atau etnisnya seperti misalnya Cina. Hanya ditemukan tiga iklan yang cukup jelas menggambarkan sosok Cina dan satu iklan menggambarkan sosok Arab. Sementara sosok Afrika ditemukan dalam iklan dimana gaya iklan tersebut bisa dilihat sebagai kelanjutan tradisi iklan Eropa / Barat yang secara stereotype sering menggambarkan bangsa afrika sebagai budak dalam iklan-iklan mereka.
9. Kesimpulan
9.1. Stereotype karakter
Iklan-iklan tidak akan dapat secara utuh mewujudkan realita sosial ke dalam rancangan-rancangannya karena iklan dibuat dengan satu kepentingan yaitu perdagangan. Bagaimana agar suatu produk dapat lebih diterima masyarakat menjadi tujuan utama. Faktor itu menyebabkan bahwa dalam pembuatan iklan-iklan tersebut akan terjadi penyederhanaan masalah (sosial) dan manipulasi kenyataan yang ada agar sesuai dengan strategi komunikasi dari iklan tersebut.
Di balik penggambaran sosok manusia yang ditujukan untuk kepentingan strategi iklan tersebut, dapat dilihat bahwa pandangan umum masyarakat saat itu disadari atau tidak, diwakili oleh para pembuat iklan dengan cara mereka menggambarkan tokoh-tokoh juga cara memposisikan tokoh-tokoh tersebut satu sama lain. Di sini terjadi proses konstruksi sosial karena iklan memiliki kekuatan untuk menanamkan gagasan ke benak pemirsa.
Dari kajian ini bisa ditemukan jejak dari ideologi kolonial yang masih bisa ditemukan di tahun 1920-1940-an dalam bentuk nilai-nilai dan pemahaman tentang kelas sosial yang sudah direkayasa oleh pemerintah Hinda Belanda lewat peraturan-peraturan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Perancang iklan, “membaca” fakta strata sosial masyarakat pada zaman itu dan menyederhanakan realitas strata sosial masyarakat ke dalam penggambaran sosok-sosok manusia sebagai berikut:
a. Belanda laki-laki
b. Belanda perempuan yang terdiri dari
- Ibu Rumah Tangga
- Beberapa jenis pekerja profesional lain
c. Pribumi perempuan yang terdiri dari
- Ibu Rumah Tangga
- Emban / Koki / Pelayan
- Beberapa jenis pekerja profesional lain
d. Pribumi laki-laki yang terdiri dari
- Priyayi
- Pekerja Kasar
- Jongos
- Tokoh muslim
e. Arab
f. Afrika
g. Cina
Stereotype sosok-sosok manusia tersebut dimanfaatkan menjadi gambar-gambar adegan yang bertujuan untuk memberikan makna kepada produk-produk yang diiklankan. Sosok-sosok manusia yang ditampilkan dalam iklan menjadi penanda terhadap produk sebagai petandanya. Sosok-sosok manusia dan adegan dari iklan menjadi penghubung antara kualitas abstrak dengan produknya itu sendiri. Media yang didistribusikan secara luas dan frekeuensi penayangan merupakan sebagian faktor yang mempengaruhi daya tembus gagasan dari iklan terhadap pemirsanya.
9.2. Perbedaan Ideologi dari majalah
Ketika saya melihat secara keseluruhan, maka terlihat bahwa Iklan-iklan yang menjadi bagian dari majalah memiliki potensi dan kecenderungan untuk menanamkan ideologi kepada pembaca. Baik De Zweep / D’Orient maupun Pandji Poestaka, walaupun keduanya ditujukan untuk target pembaca yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam ideologi kolonial yang dijunjungnya. Keduanya saling melengkapi gambaran tentang struktur sosial masyarakat yang sudah ditanamkan oleh pemerintah di Hindia Belanda. Secara tidak langsung, De Zweep/ D’Orient menguatkan strata sosial Belanda (Eropa) sementara Pandji Poestaka menguatkan posisi strata sosial pribumi. Ideologi kolonialisme yang terlihat dalam penggambaran strata sosial yang pada prakteknya menjadi suatu proses konstruksi kelas sosial.
Pada sisi tertentu, ditemukan kesejajaran antara penggambaran sosok manusia dalam iklan dengan realitas. Misalnya dalam penggambaran fisik dan cara berpakaian dari sosok-sosok manusia tersebut. Dari temuan foto-foto sejaman yang diperbandingkan dengan gambar pada iklan ditemukan kesamaan.
Belanda secara tidak langsung “memaksakan” pakaian Barat kepada pria pribumi yang ingin dianggap intelektual walaupun peralihan dari pakaian tradisi ke pakaian Barat dilakukan tanpa ada pemaksaan lewat aturan. Kaum pria pribumi dengan memakai pantalon, jas, dan menambahkan peci di kepalanya, memposisikan diri mereka setara dengan pria Barat. Proses tersebut ini terjadi karena adanya ideologi yang disampaikan lewat penanaman nilai-nilai di sekolah-sekolah, publikasi, dan akhirnya juga melalui iklan-iklan. Ketika suatu iklan yang menggambarkan adegan dimana fihak yang superior adalah yang menggunakan atribut Barat maka ada konotasi bahwa bila ingin menjadi yang lebih baik maka harus memiliki ciri-ciri fisik seperti yang menempel pada sosok Barat tersebut. Ideologi ini sudah semakin meresap sehingga pribumi sendiri sudah mempraktekkannya misalnya ketika seorang pelayan pribumi memperlakukan tamu secara berbeda-beda akibat dari pakaian tamu tersebut.
Di samping itu saya juga melihat kedua iklan tersebut secara terpisah antara iklan De Zweep / D’Orient di satu sisi dan Pandji Poestaka di sisi lain. Saya mempertimbangkan perbedaan target pembaca antara De Zweep / D’Orient dengan Pandji Poestaka karena dari pembedaan itu akan bisa didapatkan pemaknaan yang berbeda. Dalam De Zweep / D’Orient karena target pembacanya adalah masyarakat Belanda maka kode yang dominan berlaku adalah sistem kode lapisan masyarakat tersebut. Sosok yang dominan adalah perempuan Belanda dan Pria Belanda. Sosok pribumi muncul di majalah tersebut hanya sebagai penguat posisi Belanda sebagai strata sosial yang dominan yaitu jongos dan pelayan.
Demikian juga dengan Pandji Poestaka, dimana masyarakat pembacanya adalah pribumi yang cukup terpelajar, yaitu kelompok priyayi, maka sistem kode yang dipakai adalah sistem kode yang diyakini kaum priyayi sehingga di dalam iklan-iklannya, tidak terlihat dominasi Belanda. Di Pandji Poestaka sosok yang sering muncul adalah priyayi yang berpakaian daerah maupun berpakaian “nasional” yaitu sebanyak 54 orang, lebih dari separuh dibandingkan jumlah keseluruhan. Mereka menjadi sosok dominan dalam wilayah pribumi (Pandji Poestaka). Jarang sekali ditampilkan sosok pria Belanda. Dalam sistem kode Pandji Poestaka ini, jongos tetap menempati posisi yang sama. Bisa dikatakan bahwa “kepemilikan” atas jongos sudah berpindah dari Belanda kepada priyayi.
Jadi kelas dominan akan sangat mempengaruhi bagaimana sistem nilai yang dipergunakan sebagai acuan dalam merancang iklan.
Perempuan baik Barat maupun pribumi masih dikonstruksikan untuk berada di wilayah domestik, sandang dan pangan. Perempuan Barat lebih banyak dimanfaatkan sebagai elemen yang membawa konotasi keindahan, keduniawian dan gaya hidup. Sementara perempuan pribumi dominan sebagai pembawa makna kenyamanan, kelembutan kasih sayang.
Latar belakang politik dan sosial demi kepentingan ekonomis diserap oleh iklan menjadi bagian suatu pencitraan. Iklan memanfaatkan dinamika pergeseran nilai masyarakat yang tercermin dari cara berpakaian dan perilaku masyarakat menjadi gambar-gambar sosok manusia dan adegan yang seolah-olah “mencerminkan” kehidupan. Iklan berusaha untuk mensosialisasikan pencitraan “cerminan” kehidupan masyarakat tersebut agar diadopsi masyarakat dan menjadi gaya hidup baru. Dengan begitu produk yang dipromosikan kemudian menjadi bagian dari gaya hidup baru tersebut. Kolonialisme ataupun nasionalisme dalam hal pembuatan iklan hanya merupakan strategi untuk mencapai tujuan utama yaitu perdagangan.
Selain memberikan informasi-informasi tehnis, dan manfaat tentang produkperancang iklan selalu berupaya memberi makna baru terhadap produk sebagai nilai tukar. Disadari atau tidak, proses para perancang iklan “menangkap” kondisi dari strata sosial tersebut untuk kemudian menerapkannya ke dalam iklan juga bisa dilihat sebagai pelanggengan ideologi karena iklan memiliki kekuatan yang besar dalam menyebar-luaskan gagasan.
Daftar Pustaka
Teori Sosial – Ekonomi – Budaya – Sejarah Indonesia
Aaker, David A. Building Strong brands. New York: The Free Press. 1996
Adam, Ahmat. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan. Jakarta: Hasta Mitra / Pustaka Utan Kayu. 1995.
Adams, Cindy, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Cetakan ke-6. Jakarta: Ketut Masagung Corporation. 2000.
Althusser. Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies. Jakarta: Jalasutra. 1984.
Al Katiri. Zeffry Iklan “Lampau Indonesia dalam Wujud Komik, Analisis Bahasa dan Grafis,” Wacana, vol.7 no.1, April 2005 (65-80).
Ardhiati, Yuke. Bung Karno Sang Arsitek. Jakarta: Komunitas Bambu. 2005.
Barthes, Roland. Elements of Semiology. New York: Hill and Wang. 1967.
____________ Mythologies. New York: Hill and Wang. 1956.
Blackburn, Susan. Kongres Perempuan Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor / KITLV. 2007.
Barnard, Malcolm. Fashion Sebagai Komunikasi, Jakarta. Jalasutra: 1996.
Boomgard, Peter. Janneke van Dijk. Het Indie Boek. Zwolle: Waanders. 2001.
Boulding, Kenneth. The Image. Michigan: University of Michigan Press. 1956.
Burger, D.H. Sociologisch-Economische Geschiedenis van Indonesia. The Hague: The Hague Nijhoff. 1975.
Chaney, David. Lifestyles, Sebuah Pengantar Komprehensif. Yogyakarta: Jalasutra. 1996.
Cribb, Robert, ed. The late Colonial State in indonesia, political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880 - 1942. Leiden: KITLV Press. 1994.
Eco, Umberto. A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press. 1979.
Ewen, Stuart. All the Consuming Images. New york: Basic Books. 1994.
Foxworth, Marylin Kern-. Aunt Jemima, Uncle Ben, and Rastus. Blacks in Advertising, Yesterday, Today and Tomorrow. London. Pareger. 1994
Fries, JJ de. Jakarta Tempo Doeloe. Jakarta: Media Antarkota Jaya. 1972
Hall, Stuart, ed. Representation, Cultural Representations and Signifying Practices, London: Sage Publications. 1997.
Hoed, Benny H. “Dampak Komunikasi Periklanan sebuah ancangan dari segi semiotika”. Jurnal Seni 4:4 (1994): 111 - 133.
___________ Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya. Depok: FIB-UI. 2007.
Kartodirdjo, Sartono. Sejak Indische Sampai Indonesia. Jakarta: Kompas. 2005.
Lindblad, J. Thomas, ed. Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM – Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
Lloyd Christopher. The Structures of History, London: Blackwell. 1990.
Lombard, Denys, Nusa Jawa Silang Budaya, Batas-batas Pembaratan, Jakarta: Gramedia. 1990.
____________ Nusa Jawa Silang Budaya, Jaringan Asia. Jakarta: Gramedia. 1990.
Mc Lelland, David. Ideologi Tanpa Akhir. Jakarta: Kreasi Wacana. 2005.
Lull, James T. Media Komunikasi Kebudayaan, Suatu Pendekatan Global. Jakarta, Buku Obor. 1998.
Manring, M.M. Slave in the Box. Virginia: The University Press of Virginia. 1998.
Miert, Hans van. Dengan Semangat Berkobar, Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930. Jakarta. Hasta Mitra / Pustaka Utan Kayu: 2003.
Mulyana, Prof. Dr. Slamet. Kesadaran Nasional, dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan. jilid 1. Jakarta, LKiS. 2008.
Niel, Robert van. Munculnya Elite Modern Indonesia. Jakarta. Pustaka Jaya. 2009.
Nieuwenhuys, Rob, Mirror of the Indies, A History of Dutch Colonial Literature. Singapore: Periplus. 1999.
Nordholt, Henk Schulte. Outward Appearances, Leiden: KITLV Press. 1997.
Nuradi, et. al. Kamus Istilah Periklanan Indonesia. Jakarta: Matari Advertising / Gramedia Pustaka Utama. 1996.
Pieterse, Jan Nederveen. 1992. White on Black, Images of Africa and Blacks in Western Popular Culture. London. Yale Univ. Press.
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosutanto. ed. Sejarah Nasional Indonesia V, Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosutanto. ed. Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Reka Reklame, Sejarah Periklanan Indonesia 1744 -1984. Jakarta: Galang Press. 2004.
Reksodipuro SH, Subagio dan Haji Subagijo I.N. 45 tahun Sumpah Pemuda. Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta. 1974.
Ries, Al, and Jack Trout. Positioning, The Battle for Your Mind. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200 - 2004. Jakarta: Serambi. 2005.
Riyanto, Bedjo. Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870 – 1915), Yogyakarta: Tarawang. 2000
Stuers, Cora Vreede-De. Sejarah Perempuan Indonesia, Depok: Komunitas Bambu. 2008.
Soekiman, Prof Dr. Djoko. Kebudayaan Indis, dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa. Yogyakarta: Bentang. 2000.
Sumardjan, Selo. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Depok: Komunitas Bambu. 2009.
Surjomihardjo, Abdurrachman. Kota Yogyakarta Tempo Doeloe, Sejarah Sosial 1880-1930. Depok: Komunitas Bambu. 2009.
Suseno, Franz Magniz. Pemikiran Karl Marx. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.
Taylor, Jean Gelman. The Social World of Batavia. London: The University of Winconsin. 1983.
Thompson, John B. Analisis Ideologi. Jogjakarta: IRCiSoD. 2007.
Wertheim, W.F, Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial. Yogyakarta.Tiara Wacana. 1999.
Westerbeek, Loes, ed. Recalling the Indies, Kebudayaan kolonial dan identitas poskolonial. Yogyakarta: Syarikat Indonesia 2004.
Williams, Raymond. Keywords. London: Fontana Press. 1988.
Periklanan, komunikasi visual, dan desain
Barnard, Malcolm. Art, Design. And Visual Culture. London: MacMilan Press. 1988.
Barnicoat, John. Posters a Concise History. New York: Thames and Hudson. 1988.
Boulding, Kenneth. The Image. Michigan: University of Michigan Press. 1956.
Dalley, Terrence. The Complete Guide to Illustration and Design. London. Chartwells books. 1983.
Fowles, Jib, Advertising and Popular Culture, California: Sage publications. 1996.
Goes, Bernadette van der, and Pim Reinders. The Spirit of Modern Advertising, Jan Lavies, Poster Designer (1902). Amsterdam: Rainy Day publishing. 1997.
Klein, Naomi. No Logo. London: Flamingo. 2001.
Leeuwen, Theo van. Carey Jewitt ed. Handbook of Visual Analysis, London. Sage publications. 2001.
Marchand, Roland. Advertising the American Dream, Making Way for Modernity 1920 – 1940, California: University of California Press. 1985.
Silverblatt, Art. Media Literacy. Keys to Interpretating Media Messages. London. Praeger. 1995.
Walker, John A. & Sarah Chaplin. Visual Culture. Manchester: Manchester University Press. 1997.
Williamson, Judith, Decoding Advertisements, Ideology and Meaning in Advertising. New York. Marion Boyas. 1998.
[1] Sejak tahun 1942, Pandji Poestaka, diberi label di halaman depannya “DENGAN IZIN KANTOR HODOKA”, HODOKA adalah suatu kantor Jepang yang mengawasi penerbitan media.
[2] Hegemoni adalah kekuasaan atau dominasi yang dipegang oleh suatu kelompok sosial terhadap kelompok sosial yang lain. (Lull, 1997, 33)
[3] Lebih luas lagi, termasuk di dalamnya kode-kode untuk encoding dan decoding teks - (dominan atau hegemonis’), negosiasional atau oposisional (Hall 1980; Morley 1980). Lebih spesifik lagi, segala isme-isme bisa dimasukkan di dalamnya. Juga perlu dicatat bahwa semua kode-kode tersebut dapat dianggap sebagai bersifat ideologis (Chandler, 2001: 150)
![]()
Iwan Gunawan
Doctor in History, University of Indonesia, Jakarta
•••
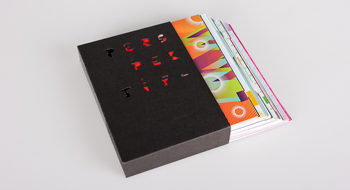



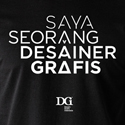



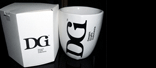

 1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto
1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto 2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong
2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong 3. Hurufontipografi | Surianto Rustan
3. Hurufontipografi | Surianto Rustan www.underconsideration.com
www.underconsideration.com

tapi ga ada gambarnya…
Iya Mas Iwan & Pak Hanny bisa bantu lengkapi dengan beberapa visual supaya lebih jelas? thx ya
“Angkat Komputer” untuk (Prof.?) Dr. Iwan Gunawan, S.Sn., M.Si. CONGRATULATION..!! semoga ilmunya bermanfaat tuk insan Seni Rupa (DKV) Nasional maupun Internasional..