Oleh: Koskow
“Aku kira inilah jalan sunyi pendidikan dkv, bahwa saat ini ia gagal dalam melahirkan pendidik yang visioner”
Tulisan ini mau mengelaborasi tulisan Hastjarjo yang berjudul “Mengkritik Pendidikan DKV di Indonesia”. Tulisan ini berusaha memberi tilikan yang sifatnya taktis. Tujuan tulisan ini pun sebatas menawarkan gagasan yang sifatnya “dapat dikerjakan”, sembari menghindar untuk berkutat di tingkat wacana. Meski demikian, mau tak mau, apa-apa yang dilontarkan Hastjarjo dalam tulisannya patut dijadikan pintu masuk dalam mendudukkan kembali arah pendidikan dkv di Indonesia. Satu hal yang patut diapresiasi ialah tanggapan berbagai pihak atas tulisan Hastjarjo tersebut. Boleh jadi hal tersebut menggambarkan betapa media (blog, facebook, dll.) memberikan ruang partisipasi bagi insan dkv dalam memandang beragam persoalan dalam tubuh dkv itu sendiri, termasuk pendidikan dkv. Dengan kata lain, tulisan ini merupakan salah satu dari sekian partisipasi publik yang semoga bermanfaat bagi pendidikan dkv melalui jalan kritik. Sebagai sebuah kritik tulisan ini maunya menelisik lebih dalam tulisan Hastjarjo tersebut sembari menemukan lebih jauh gagasan apa saja yang bisa dihadirkan.
Drink Me: Manifesto Utopia
Dalam tulisannya Hastjarjo mengulang pernyataan mendasar dalam pendidikan, yaitu “Bukankah katanya pendidikan untuk semua orang?” Pernyataan tersebut (bukan pertanyaan) barangkali mau mempertanyakan ulang esensi arah pendidikan dkv saat ini. Dalam tulisannya Hastjarjo masif menghadirkan penilaian baik di tataran konseptual maupun praksis. Sebagai contoh, gagasan “Ayo para dosen dkv bersatu dalam asosiasi!” terkesan sebagai sesuatu yang bernuansa reformis, mendesak, dan penting. Dalam pandangaku, gagasan tersebut bisa dilihat sebagai korban populisme sejarah, apalagi diawali dengan pernyataan “Jika para buruh saja mampu berasosiasi, mengapa para dosen dkv tidak?” Gagasan ini pun terkesan romantik.
Nah, tulisan ini mau menghindari gagasan yang demikian karena gagasan yang demikian, menurutku, mudah jatuh dalam tingkat wacana (karena menghadirkan populisme sejarah, Marxisme?) yang boleh jadi menjadikan gagasan tersebut akhirnya berhenti di tingkat wacana juga. Teks yang demikian dalam hal tertentu mudah jatuh ke dalam teks yang simulatif, meski terkesan intertekstualitasnya. Dengan kata lain perlu perhatian penuh dalam menilai gagasan-gagasan dalam teks yang demikian agar teks tersebut (tulisan Hastjarjo) mampu dinilai sebagai teks yang inspiratif, bukan teks yang membuka debat berkepanjangan. Meski demikian, tulisan Hastjarjo tersebut di sisi lain menjadi sebuah penegasan idealisme dalam tubuh pendidik(an) dkv hari ini. Artinya, yang telah dituliskan di masa lampau belum tentu tak bertaring untuk saat ini. Taring yang mau disodorkan Hastjarjo yaitu para dosen dkv dilihat sebagai sebuah kelas, seperti halnya kelas buruh, di mana sebagai sebuah kelas ia memiliki hal-hal yang diperjuangkan seperti kesejahteraan, kemakmuran, tunjangan transport, dll.
Dengan perbedaan cara memandang (menulis) pendidikan dkv yang demikian, tulisan ini mau keluar dari bingkai debat wacana. Berikut kutuliskan apa-apa yang kiranya bermanfaat dalam menjalankan pendidikan dkv.
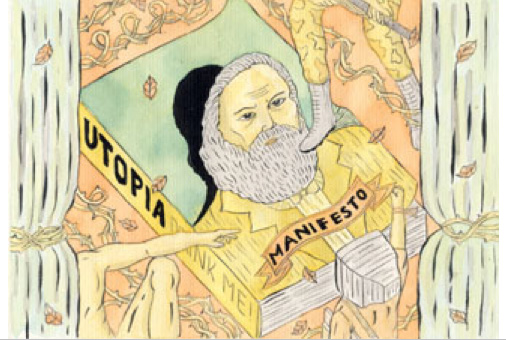
Keterangan gambar: Biennale Jogja X-2009 kategori Ruang Khusus, drawing oleh Koskow (2009)
Minimnya Apresiasi & Jebakan (Meng)Kritik
Sebuah kritik tak harus berupa penilaian negatif atas apa yang dikritik. Dalam pengertian tertentu, dan ini kerap dilupakan, kritik merupakan usaha yang mau memberi pengetahuan/penilaian atas sesuatu yang selama ini belum/tak diketahui publik. Meski demikian, hal yang demikian kerap dikenal dengan julukan apresiasi. Maka dari itu jika ditemui istilah kritik dkv, ataupun kritik pendidikan dkv, justru yang diharapkan ialah kajian-kajian yang sifatnya apresiatif, inspiratif. Pada persoalan yang demikian dkv di Indonesia minim apresiasi. Apresiasi di sini menunjuk pada keragaman kajian dalam dkv. Dapat diidentifikasi misalnya kepustakaan apa saja yang belakangan ini muncul. Paling banter akan ditemui nama-nama seperti Surianto Rustan, Budiman Hakim, Sumbo Tinarbuko, Jito Kasilo, atau Danton Sihombing sebagai teks babon pengetahuan dkv (di) Indonesia.
Di wilayah media massa berkala (hanya) dapat dijumpai majalah Concept, Versus, Babybos. Di jagat internet dapat dijumpai Bajigur. Jurnal dkv pun dapat dihitung jumlahnya. Dalam kancah perbukuan kerap/senantiasa direproduksi buku-buku tutorial software desain. Apresiasi atas karya dkv pun kerap berkutat di wilayah kreativitas, teknis, ataupun semiotika. Pendek kata, apresiasi yang selama ini hadir belum dapat dinilai sebagai sebuah kritik dalam artian menginformasikan sesuatu yang belum terbaca oleh publik. Hal ini menandakan bahwa terdapat kekosongan penilaian dalam dunia dkv. Aku kira, kritik yang selama ini dijalankan baru berada pada tingkat kritik dalam artian mencari kekurangan, kelemahan, atau ditulis dari sudut pandang ke-aku-an, alias kritik-kritik tersebut belum menjadi teks yang visioner dalam perspektif ke-kita-an.
Aku mau bilang bahwa apresiasi yang konstruktif dapat dimulai dari pemahaman kritik yang berusaha mau mengisi kekosongan pengetahuan. Atas cara yang demikian tulisan “Mengkritik Pendidikan DKV di Indonesia” yang maunya reformis/visioner di lain sisi rentan jatuh pada tataran konservatif (ingat gagasan populisme di atas).
Di lain sisi kritik atas praksis dkv paling kerap berupa pelaporan kerja kreatif dalam bungkus agensi, produsen, ataupun artis. Agency, artis, dan produsen di sini merupakan infrastruktur industri dkv. Tak ayal jika masyarakat/publik kerap terabaikan dalam kritik maupun apresiasi dkv. Dalam arti tertentu masyarakat/publik belum diberikan tempat sebagai juru bicara atas nama mereka sendiri. Pendeknya, mereka senantiasa dijurubicarai oleh pihak lain. Publik kerap disunyikan dalam apresiasi dkv. Atas persoalan ini kita dapat mulai menuliskan gagasan berikut yaitu advokasi dalam dkv.
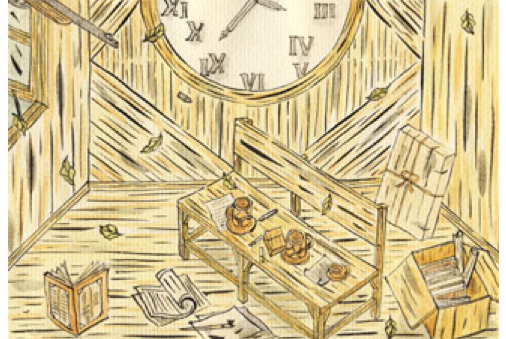
Keterangan gambar: Biennale Jogja X-2009 kategori Ruang Khusus, drawing oleh Koskow (2009)
Minimnya Advokasi
Jika mengamati tanggapan atas tulisan Hastjarjo akan mudah ditemui topik yang cukup menjadi bulan-bulanan perdebatan. Topik tersebut ialah industri. Industri di sini diartikan sebagai suatu arena yang di dalamnya melibatkan harga jasa desain, kemampuan mendisain, klien, pitching, hingga sertifikasi desainer. Saat ini industri merupakan kenyataan yang sulit disangkal. Namun, cara melihat industrilah yang perlu diperbaharui. Misalnya, jika membicarakan industri apa-apa saja yang terlupakan, atau yang luput dari perhatian? Jika membicarakan industri yang terlupakan antara lain hal-hal yang selama ini belum/tidak dianggap sebagai bagian dari industri. Di sini akan muncul konsep tentang advokasi. Advokasi bukan dimengerti mengadvokasi industri dan praksis jasa dkv yang selama ini kita mengerti. Advokasi di sini maunya melihat dkv sebagai mediator, sebagai fasilitator untuk yang bukan industri, misalkan kampung, ukm, desa, tradisionalisme, hingga kaum miskin atau si korban. Di sini perlu dibedakan dkv dalam pengertian simbolik dan dkv dalam pengertian budaya (praksis). Bolehlah jasa dkv yaitu mencipta tanda-tanda simbolik. Namun sebenarnya yang simbolik tadi sangat perlu dipertanyakan praksisnya. Ini bukan perkara sepele. Ini menyangkut kedirian insan dkv.
Dalam pendidikan dkv advokasi bisa menunjuk pada biaya pendidikan dkv. Hastjarjo dalam tulisannya memberi stabilo merah atas praktik biaya pendidikan dkv yang kian terjerumus dalam komersialisasi (naluri kapitalisme). Parahnya hal tersebut dimulai sejak pengambilan (pembelian) formulir pendaftaran yang sebenarnya di jaman internet seharusnya kian dimudahkan. Lebih parah lagi jika seleksi yang dilakukan adalah tanpa seleksi. Pengertian dkv laris manis justru menunjukkan tak adanya advokasi bagi kualitas dkv itu sendiri. Di sini yang jadi korban ialah masyarakat pengguna dkv dan dkv itu sendiri. Jadi, salah kaprah juga pemahaman penyelenggara jasa pendidikan dengan adagium pendidikan untuk semua orang. Yang dimaksud pendidikan untuk semua orang terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia menunjuk pada modal ekonomi dan kesempatan mengenyam pendidikan yang kini harganya kian melangit. Sedangkan pendidikan untuk semua orang tidak bisa diberlangsungkan pada tataran kualifikasi calon peserta didik. Jika prinsip-prinsip ini diabaikan pendidikan dkv jatuh pada pragmatisme pendidikan. Lebih parah lagi jika kondisi ini dijadikan alasan tersembunyi di balik BHP pendidikan tinggi dkv, meski pemerintah telah menggelontorkan gagasan ekonomi kreatif yang sebenarnya bukan hal baru.
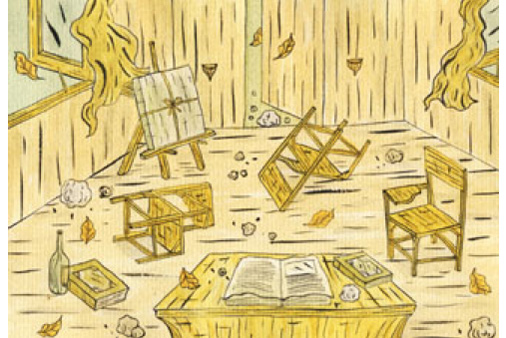
Keterangan gambar: Biennale Jogja X-2009 kategori Ruang Khusus, drawing oleh Koskow (2009)
Cara Lain Membaca Karya-karya DKV
Agenda lain yang patut digagas dalam mengisi kekosongan paradigma dalam pendidikan dkv yaitu soal apresiasi karya. Masih teringat ketika sebuah model analisis/pembacaan menjadi trend dari satu dekade ke dekade lain. Misalkan, saat ini semiotika menjadi trend analisis (termasuk aku yang dulu sempat jadi korban! bodohnya aku, termakan trend dan gagal menjadi diri sendiri!). Bukan salah semiotika jika ia menjadi model analisis yang sedang laris. Di sini yang diperlukan ialah cara baru memandang karya dkv (teks). Misalkan, sebuah iklan, poster, atau apapun itu, semata tidak dipandang sebagai teks namun sebagai media di mana pengertian media di sini menunjuk pada hubungan sosial. Dalam ilmu komunikasi hal ini bukan hal baru (literasi media). Dalam dkv gagasan pembacaan yang demikian jarang (aku) temui. Apa implikasi bagi dkv dengan cara pembacaan yang demikian? Karya-karya dkv tak lagi cukup didudukkan sebagai sebuah tanda, sebuah simbol, namun ia akan diuji sejauh mana ia mampu mengatasi hubungan sosial di baliknya. Dengan demikian sebuah bilboard tidak dipandang dari sisi teks namun hubungan sosial di balik kehadiran bilboard itu sendiri. Meski demikian, pembacaan yang demikian jarang dilakukan apalagi oleh praktisi dkv yang maunya nyaman di lanskap industri mengingat tugasnya sebatas menciptakan tanda-tanda dalam berkomunikasi, bukannya mengurusi hubungan sosial media bilboard di mana ia hadir, berinteraksi, dan menduduki lokasi tertentu.
Dalam dunia periklanan, terutama yang menyangkut identitas perempuan, nasibnya mungkin lebih baik. Perempuan saat ini mampu menjadi juru bicara atas dirinya sendiri. Meski demikian masih kerap ditemui iklan yang menghadirkan sosok perempuan sebagai objek eksploitasi dalam komunikasi bermedia. Di sini iklan yang demikian tidak dilihat sebagai sebuah teks namun dilihat pada sejauh mana kita berelasi dengan perempuan dalam praktik keseharian. Apakah iklan yang demikian menjadikan hubunganku dengan perempuan kian membaik, atau tetap berlangsung prinsip dominasi (relasi tuan – budak). Jika yang terakhir yang berlangsung maka iklan jatuh pada tataran tanda-tanda semu, tak peduli sejauh mana daya kreativitas pada iklan tersebut.
Dalam dunia pendidikan persoalan di atas semestinya diapesiasi dengan cara memasukkan kurikulum dari kepentingan yang selama ini dijadikan budak, dari sisi mereka yang selama ini jadikan korban/objek penderita. Cara membaca karya dkv yang demikian sebenarnya masih berkaitan erat dengan gagasan di atas yaitu advokasi dalam dkv (namun dalam wilayah praksis). Meski demikian, diam-diam dalam pendidikan dkv atau barangkali telah dikerjakan pula dalam industri dkv pendekatan antropologi yang mau mengerti secara detail target sasaran, terutama dalam periklanan. Meski demikian, hal tersebut masih patut ditanyakan untuk tujuan apa semua itu dikerjakan. Apakah untuk tujuan pragmatis (jualan) atau mau memperbaiki relasi sosial antara masyarakat/publik dengan produk dan iklan bersangkutan? Sekali lagi di sini dibutuhkan cara baru memandang karya-karya dkv yang bukan sebatas teks namun melihatnya sebagai hubungan sosial. Kata seorang teman, kita patut membangun perspektif ke-kita-an, bukan aku centris.

Keterangan gambar: Biennale Jogja X-2009 kategori Ruang Khusus, drawing oleh Koskow (2009)
Menjaraki Trend & Melakukan Perluasan
Maksud dari menjaraki trend & melakukan perluasan di sini dimengerti sebagai usaha untuk tak larut dalam populisme jaman. Memang, dalam dkv berlaku zeitgeist (semangat jaman). Namun, dkv pula yang kerap menjatuhkan zeitgeist tersebut ke dalam fenomena latah/paritas. Latah/paritas di sini berlaku untuk dunia praksis dkv, pendidikan dkv, maupun pembacaan dkv. Gejala ini tidak mungkin dilepaskan dari keterlibatan industri dalam artian industri tidak berani melakukan spekulasi mengingat melinbatkan modal yang tidak sedikit. Maunya pasar ya dituruti. Maunya tidak rugi alias turut ambil keuntungan sepintas dari fenomena/trend yang menggejala. Maka, banjirlah distro, banjirlah skripsi semiotika, sampul buku njogja, sampul buku chicklit maupun teenlit, komik manga, dsb.
“Keren” di satu sisi menjadi kata yang kerap dirujuk dalam memberi pembuktian aktualisasi diri dalam dunia dkv. Kata tersebut di satu sisi menyimpan makna aktual, up to date, kekinian, populer, dan gak ketinggalan jaman. Di sini dapat disandingkan dengan pembacaan karya-karya dkv di mana selama ini karya-karya yang kerap diapresiasi mungkin karya-karya yang demikian. Jika karya tersebut dilihat sebagai hubungan sosial maka barangkali tidak aneh kemunculannya karena memang direncanakan sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tugas visioner seorang pendidik ataupun desainer yaitu mencari perluasan dan melakukan penjarakan terhadap fenomena popularitas dan memperkaya keberagaman terutama untuk menyiasati stereotype (gaya) desain.
Maka dari itu di sini dapat dilakukan penjarakan terhadap misalkan fenomena media yang akhir-akhir ini memenuhi obrolan dalam periklanan seperti unconventional media. Atau barangkali kita menerima begitu saja obrolan tentang local genus di mana sebenarnya dalam keseharian local genus tadi belum menjadi bagian dari diri kita (kita asik ngobrolin local genus namun kedirian kita sebenarnya kedirian yang global, alias diri kita belum dibetot hingga yang terdekat dengan kita sendiri).
Persoalan-persoalan di atas tak saja berlangsung dalam industri dkv namun juga industri musik tanah air. Kita mudah jatuh dalam stereotype karena popularisme di mana stereotype itu sendiri jelas tak mampu menggambarkan keragaman realitas. Persoalan yang demikian kerap hadir ketika seseorang dididik mengapresiasi karya melulu melalui pendekatan tertentu, bukannya mempertanyakan mengapa praktik tersebut (karya tersebut) hadir sedemikian rupa. Pendidikan dkv yang hanya sibuk berkutat menelisik teks, akan lebih bermanfaat jika perluasan pembacaan dilakukan misalkan untuk mempertanyakan mengapa karya tersebut menjadi sedemikian rupa, struktur sosial dan struktur kognitif apa yang menyangganya, dll. Tugas mengapresiasi lantas diberlangsungkan sampai pada kemampuan mencari tahu kehadiran sebuah karya/fenomena. Di sini tidak berlaku usaha untuk menilai, namun usaha untuk mendengarkan, mencari tahu, dan menelisik persoalan yang jauh lebih mendasar. Dengan cara demikian, perluasan pembacaan pada akhirnya menyangkut perluasan kedirian kita sebagai desainer maupun pendidik dkv.
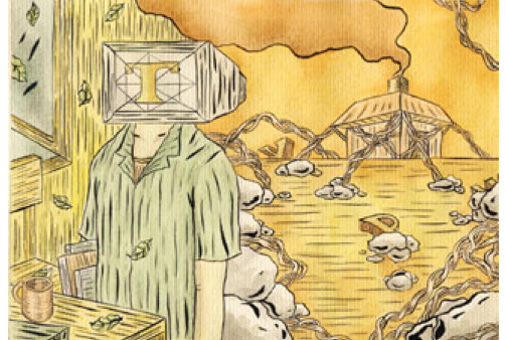
Keterangan gambar: Biennale Jogja X-2009 kategori Ruang Khusus, drawing oleh Koskow (2009)
Penutup
Tulisan “Mengkritik Pendidikan DKV di Indonesia” aku kira ditulis bukan tanpa sebab. Tulisan tersebut mengindikasikan sesuatu. Barangkali, Hastjarjo mau mengingatkan kembali spirit pendidikan Ki Hadjar Dewantoro. Di kesempatan lain Hastjarjo menyebut AD Pirous dalam memperkaya dan menegaskan kembali pendidikan dkv dan kedirian desainer.
Sayangnya, dalam tulisannya, Hastjarjo tak menyebut nama-nama yang sekiranya saat ini menjadi generasi terkini pendidikan dkv. Apakah ini mengindikasikan bahwa kita kekurangan, bahkan tidak memiliki pendidik yang layak dijadikan anutan, baik dalam hal kepribadian maupun gagasan-gagasan visionernya. Mengenai yang terakhir, AD Pirous dalam satu kesempatan, mengatakan bahwa menjadi desainer itu menjadi seseorang yang visioner.
Aku kira inilah jalan sunyi pendidikan dkv, bahwa saat ini ia gagal dalam melahirkan pendidik yang visioner. Dalam situasi jaman yang tunggang langgang dan menawarkan beragam jenis kepribadian yang kerap dibongkar ulang (posmodernitas), tulisan Hastjarjo ibarat pena yang berteriak di padang gurun yang sunyi. Sedangkan, di tengah kota, desainer dan sang dosen asik mendengarkan lagu-lagu rock melayu. Sedangkan aku, anda pembaca, di sini berusaha mau mencari celah sunyi dalam tulisan Hastjarjo tersebut. Bahwa dalam hal tertentu kensuyianku dalam memandang dkv adalah kesunyian dalam perspektif ketidaksendirian. “Yang tertusuk padamu berdarah padaku”, ujar Sutardji Calzoum Bahri. Semoga tahun esok kian mencerahkan. Salam dari tepian waktu pinggiran Jogja.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bagi yang belum membaca tulisan Hastjarjo B Wibowo yang direspon oleh Koskow ini, berikut adalah link-nya > Mengkritik Pendidikan DKV di Indonesia
•••
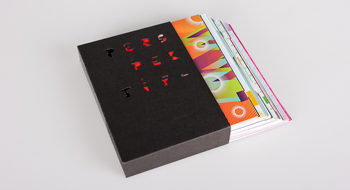



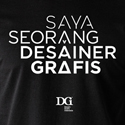



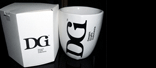

 1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto
1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto 2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong
2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong 3. Hurufontipografi | Surianto Rustan
3. Hurufontipografi | Surianto Rustan www.underconsideration.com
www.underconsideration.com

hmmm…pembahasan yang baik…
apa yang saya tangkap, begitu pula apa yang saya ucapkan “bergerak, kumpul nyata, bareng2 lebih dekat!!”
itu saja yang saya lontarkan.
semuanya perlu kestuan yang lebih dekat, nyata, terlaksana.
yu…semua kumpul…yu….kita rubah.
semuanya kendala waktu dan jarak bisa diatur untuk mendorong arah pendidikan dkv, ke awam-an org2, instansi2 trkait tentang pendidikan ini.
jujur saya masih jauh dalam ilmu ini..ilmu dkv khususnya.
isu pendidikan atau pembelajaran seperti ini sudah pernah saya tuangkan di artikel ini:
http://desaingrafisindonesia.wordpress.com/2008/09/16/design-against-style-melawan-penindasan-gaya-dalam-desain-grafis/
kesunyian boleh aja, tp jangan sampai kegersangan ilmu. =P
Trims atas perspektifnya yang elegan bung Koskow.
Salam
Hastjarjo B. wibowo
saya setuju dengan tanggapan Pak Koskow disini, menarik sekaligus mengemukakan artikel pak Has dari sisi positif.
artikel sebelumnya tidak salah, hanya apabila tidak dilihat dari sisi positif hanya akan menjadi gunjingan dan adu ‘bacot’ antar pihak.
ya memang tidak bisa kita menyalahkan satu pihak saja tapi semua pihak yang harus bersatu mengubah perspektif yang salah tersebut. dimulai dari hal menghargai dan mau belajar dari satu sama lain.
Karna “kesunyian boleh aja, tp jangan sampai kegersangan ilmu.”
Ada beragam ilmu, beragam pengetahuan dalam dkv, namun sedikit orang yang mau konsisten dan mencapai sampai pada tahap yang paling mendasar. Setia pada hal-hal kecil (detail).
Aku kira, jalan sunyi di sini tak lain jalan untuk menekuni sesuatu dan tak berarti ia menjadi gersang. Barangkali, persoalan besar dkv saat ini ialah mengatasi waktu yang serasa kian cepat. Kecepatan berbanding terbalik dengan kedalam, kata seorang teman. Memang, terasa jadul & gak populer.
Tapi ya itu tadi, aku masih sempat minum teh hangat di angkringan dengan teman-teman ngobrolin apa saja.
Ini soal way of learning, cara belajar, cara menjadi.
Desain grafis itu belum punya ‘rumah’. Bisa anda terangkan dimana lokus dan fokus keilmuan desain grafis itu?
Dan kalau memang desain grafis itu adalah desain komunikasi visual, lalu mengapa Malcolm Barnard mendiskusikan kembali “Graphic Design as Communication”? Apakah mungkin dia sedang melawak?
=P
Kalau dkv belum punya rumah, mari kita bangun bersama. sip tenan dab. oke
Karena itu, mengkritik pendidikan dkv adalah mengkritik keilmuannya yg belum berumah itu. Bukan direduksi menjadi ngedumel soal penyelenggaran kursus dan pembukaan jurusan dkv.
Letakkan dahulu paradigmanya sebelum kebablasan membahas ‘rumah’ orang lain, klarifikasi dan analisa dahulu yang mana sebenarnya masalah pendidikan dan keilmuan desain, dan yang mana masalah kebijakan publik (termasuk menjamurnya kursus desain & jurusan dkv), yang mana masalah bisnis: manajemen & pemasaran produk dan jasa desain. dstnya.
Dan masalah dalam dunia pendidikan desain grafis ini adalah ‘para pelaku’-nya sendiri tidak sadar kalau keilmuan desain grafis itu sendiri belum be-rumah, dan selama ini menumpang dimana-mana.
Jadi, sekedar saran, bincangkan hal-hal yang primer dulu baru kemudian yg sekunder.
http://designobserver.com/
http://sitem.herts.ac.uk/artdes_research/papers/wpades/index.html
http://www.artandresearch.org.uk/
Satu lagi tulisan yang memperkaya ruang lingkup DKV, memang pendidikan DKV merupakan strategi budaya bangsa yang dikaitkan dengan kepentingan sektor2 lain yang dalam hal ini tentu berhubungan dengan kepentingan ekonomi. Pada beberapa negara maju pendirian satu jurusan pendidikan yang kelak tamatannya akan tampil sebagai profesi tertentu , diijinkan sesuai dengan kebutuhannya di masyarakat tersebut. Jadi kelak akan terlihat keseimbangan supply - demand dari satu profesi. Hal ini tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah atau para universitas yang menyediakan jurusan DKV.. Kenyataan bagi para mahasiswa pencari kerja praktik setiap tahunnya tidak pernah mendapat kesempatan bekerja dibidang DKV ataupun mengisi lowongan di perusahaan2 tersebut kalau bekerja kelak. Bagaimana penelitian terhadap prosentase alumninya , berapa banyak yang bekerja dibidang DKV dan berapa orang dibidang lainnya?
Para pendidik / dosen memang seorang visioner yang justru sangat langka sekarang .Banyak orang baru tamat langsung bisa mengajar tanpa melalui proses sebagai asisten dan masih cenderung dengan mentalitas “keakuan” nya dan menanamkan se- akan2 dirinya sebagai sosok yang mengajar mata kuliahnya sebagai yang paling penting dibandingkan yang lainnya. Sarjana DKV tetap merupakan hasil sinergy dosen pembimbing dan mahasiswanya , untuk hal ini dapat ditanyakan pada para alumni bagaimana proses itu berlangsung dan kesimpulan mereka masing2 pada dosen yang membimbingnya ( layak/kurang).
Tanpa adanya kerjasama antara asosiasi perusahaan dibidang DKV, para praktisi/desainer, asosiasi DKV, Dep.PDK, Perguruan tinggi dll. yang harus bisa membuat strategi nasional pendidikan akan sulit sekali kita melakukan sertifikasi profesi yang seharusnya itu sudah merupakan bagian standard kurikulumnya, yang kelak dapat diterima masyarakat. Jangan ini merupakan surat ijin cari uang yang harus mempunyai rekomendasi ini dan itu dari pihak2 yang terkait, atau bahasa halusnya surat ijin sarjana siap pakai.
Apa yang diajukan oleh kawan Koskow dan ditanggapi oleh kawan Karnamustaqim dan kawan Merdi sangat menarik dan banyak yang saya setuju. Jadi Kalo boleh saya petakan dan tambahkan disana-sini dengan imajinasi saya sendiri, mungkin kira kira begini - mohon koreksi dan masukannya:
1) rumah desain grafis (pinjam istilah kawan Karna)
Bagaimanapun desain grafis itu tidak bisa lepas dari seni rupa, Pohon “ilmu” nya adalah olah visual dan seni visual. Untuk memahami ini dalam ranah sekolah DKV swasta yang cuma berpikir duit, sulitnya minta ampun. Bahkan banyak juga dosen dkv yang ga melihat pentingnya seni rupa utk DKV (ampun…!).Ketika dipakaikan istilah desain komunikasi visual, kita seakan terjebak jadi bagian kecil saja dari ilmu komunikasi.
2) Aplikasi desain grafis
pd titik ini barulah kita berpikir ttg ilmu ilmu tambahan dan teknis apakah yang akan memperkaya kerja desain grafis - termasuk ilmu komunikasi tadi. Disinilah interseksi dan warna tiap perguruan tinggi bisa diperkaya. Ada yang mau creativepreneur, ada yang mau jadi jagoan computer, jagoan iklan, jagoan wacana dan konsep, monggo. perkayalah dg ilmu ilmu yang bisa menjual. Dalam konteks praktek nya pasti kemudian akan terjadi interseksi, lintas disiplin, hal itu tidak bisa dihindari, karena desain grafis itu ilmu yang praktis, techne. Tidak boleh tutup mata dari ilmu lain.
Masalahnya yang terjadi kini banyak sekolah yang lebih mengutamakan ilmu ilmu pendampingnya dengan alasan entrepreneurship. Ini memang jadi trend neokapitalisme, ketika setiap aspek kehidupan dinilai dengan satuan materi, rupiah. Setiap sektor dan tahapan kerja (belajar) mahasiswa dinilai dari seberapa cepat akan menghasilkan nilai finansial yang sudah dikeluarkan dalam proses pendidikan si mahasiswa. Kesadaran materialisme yang hidup di konsumen pendidikan ini yang diadopsi dan jadi panduan para pengelola pendidikan.
Kalau balik pada pohon ilmu seni rupa, kita tidak bisa lepas dari kesadaran bahwa seni adalah ekspresi budaya dan pemikiran masyarakat, manusia. tidak semua bisa di nilai dengan uang.
Dua hal diatas: ilmu utama dan ilmu pendamping jangan dibolak balik repotlah ilmu desain grafis jadinya.
3) Kesadaran Nilai/Etik
Hal ini walau terkesan klise, tapi tidak bisa dipungkiri dan ditutup tutupi dibawah karpet tebal. Mulai dari isu global warming hingga isu kesadaran berbuat desain utk orang yang membutuhkan (tapi ga mampu bayar jasa desain). Ingat Manifesto First thing First nya Ken garland dkk. Sekolah sekolah desain grafis, sesingkat apapun belajarnya, harusnya ga boleh ngelupain ini.
4) Praktek pendidikan Desain grafis
Nah ini yang bersifat praksis,.tampaknya meresahkan kawan Hast. Banyak sekolah Desain grafis yang semena-mena dan tidak menghargai profesionalitas dosen desain grafis. sehingga dibayar rendah. Sudah gitu dosennya malu utk minta lebih, karena nanti dikira tidak bisa cari rejeki lain selain ngajar. Jadi dibayar murah tidak apa, seakan tidak terlalu butuh uang.
Pada titik inilah mungkin sebuah aksi yang solid dibutuhkan..
Monggo, mangga, ayo,
kita terus berpikir dan bergerak.
Salam, Selamat Natal dan Tahun Baru..
bung arief adityawan, bagi kita yang telah memahami bahwa akar dkv (perkembangan dari desain grafis) adalah seni rupa. sejarah membuktikan itu. aku setuju, karena di sinilah kekhasan ilmu kita (rumah). meski demikian, perluasan pendidikan dkv menjadi hak tiap institusi lembaga pendidikan dkv. sepakat dengan karna juga, rumah kita tsb mesi diopeni (jagn sampai dilupakan). salah satu rumah nyaman membicarakan itu ya di situs ini, yang bentar lagi menjadi portal.
mengenai pengajar dkv, aku kira ke depan ada peluang bahwa dibutuhkan spesialisasi-spesialisasi pada pengajaran. aku percaya, bahwa minat menjadi alasan kuat seseorang mendesain (hingga menjadi pakar dik bidangnya), dan tidak salah jika pendidikan tinggi diisi orang-orang demikian. meski demikian, pengajaran dkv saat ini masih disibukkan dengan urusan administrasi dll. yang kadang menyikat perhatian.
aku mau bilang, apapun kondisinya, jalur spesialisasi bisa menjadi jalan memerbaiki rumah kita. aku juga yakin kalau melalui spesialisasi sangat terbuka peluang untuk hadir di tingkat yang lebih luas, banyak pakar membuktikan itu. terimakasih kepada bung karna, bung arief adityawan, kawan merdy yang dengan cara mereka sendiri menjaga alur perbincangan dalam rangka membangun rumah dkv ke depan, baik dalam wilayah praksis maupun akademisi. salam
“Minimnya Apresiasi & Jebakan (Meng)Kritik”
Padahal Indonesia bukan negara komunisme… harusnya apresiasi tuh bisa berkembang kan?!
@ Makati: emangnya di negara komunis apresiasi ga bisa berkembang ya? malahan desain grafisnya lebih okeh daripada di negara Pancasila (hehe…becanda, ga perlu dibahas)
pandangan saya sebagai guru, memang betapa sunyi dalam pendidikan dkv, lebih tertuang pada aplikasi komputer grafisnya saja dan tak ada bahan atau materi yang diterapkan dalam masyarakat untuk dkv.
saya sendiri menyusun modul pembelajaran untuk dkv taraf smk kejuruan sangatlah bingung panduan saya banyak refensi dari luar dari dlm negeri hanya sedikit.
tapi saya berharap dimasa depan pendidikan dkv khususnya dapat lebih terarah dalam pendidikan di sekolah ataupun perguruan tinggi.
mas eddy, benar sekali, bahwa salah satu kelemahan pendidikan dkv ada di tingkat smu/kejuruan. maka dari itu, arah pendidikan dan dkv ke depan justru potensial dibenahi melalui tingkat smu/kejuruan. salam
ternyata di dunia kedokteran juga ada dokter dengan harga murah (lko di dunia desain grafis ada DESAIN GROSIR)…cuma bedanya..klo di dunia kedokteran SI DOKTER MURAH bakal mendapat penghargaan….tetapi klo di dunia desain grafis..SI DESAINER MURAH malah mendapat cemoohan dan dimusuhi…dinilai melecehkan profesi lah… menjatuhkan harga diri desainer lah…dll….
nich link dokter murah : http://www.detiknews.com/read/2009/12/17/125510/1261884/608/sudanto-dokter-rp-2000
sueegerr banget! dan benar sekali, kelemahan dari pendidikan DKV ada di tingkat SMU & Kejuruan.tapi untuk memperbaiki, alangkah baiknya jika kita lihat kualitas para pengajar yang sebagian besar kurang paham……apa itu DKV!
PDGD, salut atas perjuangannya memurahkan desain grafis agar lebih dapat dijangkau masyarakat,…
hanya saja, kayaknya kok ndak pas kalo Desain Grosir menyebandingkan diri dengan Dokter Murah,.. hehehe…
cari bandingan yang lain mas,…
Jadi bias soalnya, ini bisnis atau kegiatan sosial/pengabdian masyarakat…
kalau semacam pengabdian masyarakat, saya lebih setuju dengan format yang ditawarkan temen2 Jogja Mural Forum, antara lain membantu warga untuk mengelola Sign System kampungnya secara ndesain grafis….
Nah kalau desain murahnya untuk mengedukasi misalnya para perajin kecil atau pengusaha jajan tradisional yang memang membutuhkan uluran tangan desainer yang mau mendesain dengan sepenuh hati dengan bayaran sukarela ya ndak papa….
sipp..
(ngelantur)
Tulisan saudara Koskow… “Aku kira inilah jalan sunyi pendidikan dkv, bahwa saat ini ia gagal dalam melahirkan pendidik yang visioner”.
Maksudnya apa ya? Bisa gak dijelaskan lebih detail.
Terimakasih:)
salam,
Dody
Pelajaran seni di sekolah2, bahkan pelajaran menggambar pun nyaris dipunahkan. Dan hanya segelintir sekolah2 SMU yg berinisiatif utk membuka kelas ekstrakurikuler berupa kegiatan Desain grafis dan Fotografi.
Ada apa dgn pendidikan di Indonesia? Seni dianggap tidak penting, tetapi sibuk ikut gosip ‘creative industry (economy)’?
“Aku kira inilah jalan sunyi pendidikan dkv, bahwa saat ini ia gagal dalam melahirkan pendidik yang visioner”. Maksudnya, pendidikan dkv tak lepas dari pengajar. Aku kira, salah satu kemajuan dkv adalah dari materi ajar, visi-visi pengajar, atau kegiatan-kegiatan pengajar itu sendiri. memang banyak pengajar yang aktif dengan minat dan perhatian masing-masing. hanya saja, hingga saat ini belum muncul pengajar yang benar-benar serius dengan sebuah gagasan yang matang untuk memandang dkv ke depan. ibaratnya, kita jalan di pinggiran, namun arus besar dkv belum ditemukan. ini bukan sesuatu yang negatif. kegagalan berarti kesuksesan yang tertunda. siapa saja dapat mengisinya. salam
Bukan ndak ada mas. Justru yg punya visi intelektual ter-marjinal-kan (bahasa kerennya: terpinggirkan) dari kancah dunia dkv yg mayoritas berpikir dengan logika perut (minjem istilah dari seorang temen).
Wacana keilmuan dkv barangkali terkait juga dgn ini:
http://desaingrafisindonesia.wordpress.com/2010/01/26/inspirasi-visual-yongky-safanayong-sebuah-bedah-buku/