Oleh Obed Bima Wicandra
ABSTRAK
Estetika visual dalam seni rupa semakin dipertanyakan dalam konteks budaya global yang terbuka. Karya yang menjurus kekerasan, pornografi, kebohongan dan hal lain yang jauh dari moral dan etika diperhadapkan dengan identitas masyarakat yang mengikuti hasrat dalam memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Karya-karya visual yang semakin berkembang beserta dengan medianya merangsang kreator visual dalam menuangkan gagasan dan imajinasi. Bagi peradaban kehidupan manusia, karya-karya visual yang dibuat harus mendukung arah peradaban yang lebih baik. Di sini peran iman dalam hubungannya dengan Tuhan mendapat ruang berinteraksi, sehingga karya visual yang dihasilkan mencerminkan kode-kode maupun simbol dalam perputaran ideologi atau nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi hakikat keimanan.
Kata kunci: estetika visual, imperatif moralitas, iman.
ABSTRACT
Visual aesthetics in visual arts are more and more questioned in the context of open global culture. Works that lead to violence, pornography, lies, and other things far from morality and ethics, are faced with public’s identity to follow their desire to fulfill their consumtive needs. The blossoming of visual works and their media stimulates the visual creators in expressing ideas and imagination. Created visual works must support a better cultural direction for human life. Faith in its relation to God plays a role in achieveing space for interaction, so that visual works can reflect codes or symbols in the cycle of ideology or cultural values that respect the essence of faith.
Keywords: visual aesthetics, moral imperative, faith.
PENDAHULUAN
Seniman atau seorang desainer berangkat dari pemahaman tentang konsep yang terbaca dari pengalaman kedekatannya dengan lingkungan untuk menuangkan imajinasinya. Imajinasi yang menurut Sartre (1972) merupakan alam kesadaran untuk membayangkan sebuah tempat yang dihuni oleh kesamaan-kesamaan yang merupakan kumpulan imaji, telah mengalirkan sejumlah gagasan untuk berkarya. Gagasan dari seorang pencipta karya visual itulah yang kini dituntut untuk memiliki muatan tidak hanya yang berasal daricitra diri, ekspresi diri maupun sekedar tuntutan komersial, namun mampu membuka ruang demi terciptanya kultur kehidupan yang lebih baik. Dalam hal muatan sendiri, Kant memberikan penilaian atas karya tidak lepas dari cara pandang di mana realitas tidaklah terletak pada dunia yang diartikan sebagai kumpulan objek-objek, namun realitas terbentuk dalam benak manusia yang merekonstruksi semua gejala dalam relasi-relasi logis.1) Muatan-muatan yang ada dalam realitas manusia inilah yang diharapkan tergambar dalam karya-karya visual.
Secara umum pemikiran dalam seni adalah untuk menghasilkan suatu karya yang mengandung muatan adalah simbolik, metaforik, pengekspresian diri, memanipulasi suatu objek serta mempunyai kesan dan pesan tertentu. Hal tersebut merupakan gambaran-gambaran tentang realitas dan penerjemahan apa yang dilihat di dunia dalam bentuk karya visual. Hubungan antara manusia dengan kehidupan dan lingkungannya serta keberadaan manusia itu sendirilah yang diasosiasikan seni sebagai karya manusia yang bermuatan dunia.
Pola hubungan yang dekat, permainan rasa, intuisi dan eksekusi visual menempatkan karya seni mempunyai keragaman daya-daya dan kapasitas serta kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki manusia untuk mengungkapkannya secara simbolik. Seni dikatakan sebagai ungkapan yang bersifat simbolik, karena gejala dan unsur kehadirannya mempunyai petunjuk pada konsep-konsep yang dihidupi oleh komunitas maupun masyarakat tertentu. Hal demikianlah yang membuat sebuah karya seni berpijak pada kekuatan konsep dari simbolisasi secara fenomenologis dan mengakibatkan sebuah karya seni harus mampu mengantarkan orang atau penikmat ke suatu kumpulan makna.
Karya seni lukis, seni patung, seni grafis hingga yang bersifat reproduktif massal seperti film dan iklan adalah karya visual yang terbentuk dari muatan-muatan. Muatan yang biasanya bernilai pada kebenaran, kejujuran, adi luhung, dan seterusnya dianggap memberikan nilai batas pada karya visual. Nilai kesadaran yang seolah-olah ada kekuatan yang mengatasi (transendental) menggerakkan muatan-muatan memiliki benang merah dari semua aktivitas berkaryanya, yaitu hasrat atau keinginan manusia. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai pijakan pada hasrat dengan syarat. Dengan demikian, maka setiap karya visual menjadi alat untuk mengatasnamakan seni demi mengejar hasrat manusia. Karya-karya yang condong pada kekerasan, pornografi dan segala hal manipulasi pada akhirnya harus berhadap-hadapan dengan muatan yang menuntut kebenaran, keadilan, pencerahan dan sebagainya.
Segala macam ‘keharusan’ atau ketetapan yang sering muncul pada tuntutan karya visual menimbulkan representasi pada karakteristik visual. Hal inilah yang disebut Derrida sebagai keterbatasan dalam berkarya seni.2) Derrida melihat ‘batas’ akhirnya direduksi menjadi pertanyaan yang bersifat dikotomis sehingga melahirkan pertanyaan baik atau burukkah? Aku atau kamu? Hari ini atau kemarin? Padahal ‘batas’ dapat direpresentasikan sebagai ‘akhir yang memulai sesuatu’ atau sebaliknya sebagai totalitas. Dengan pengenalan batas pula, maka sebenarnya kita senantiasa berada pada fenomena yang tak terputuskan dan tak menentu dimana terjadi banyak ruang yang bisa diapresiasikan dalam karya visual. Bentuk dan isi yang dipersoalkan tidak menjadi yang lebih penting, karena semua mempunyai kesempatan penafsiran yang sama sesuai dengan sifat menginterpretasi yang sarat dengan ribuan makna.
Tulisan ini bertujuan untuk menggali secara ilmiah, bahwa karya seni adalah sebuah kemungkinan-kemungkinan tentang representasi makna. Seni yang dilahirkan dari situasi estetik tidak serta merta menjadi sebuah tuduhan negatif ketika karya tersebut menyinggung atau masuk kepada norma-norma tertentu dalam masyarakat tanpa ada penggalian makna dari kaidah-kaidah seni juga.
FILSAFAT ESTETIKA
Dalam melakukan analisis mengenai estetika visual serta aspek-aspek yang mendasari penciptaan karya yang dibuat secara eforia sehingga tidak mengindahkan nilai-nilai dalam moralitas yang bermuatan kebenaran, keadilan dan kesucian, maka pendekatan lebih diarahkan kepada nilai dan sifat keindahan itu sendiri sesuai pola dalam filsafat estetika. Filsafat berhubungan dengan spekulasi dan analisis, filsafat juga bersifat selalu bertanya, analitis, kritis dan evaluatif. Cara pandang ini menunjukkan bahwa filsafat adalah kegiatan yang bersifat integratif atau kegiatan yang mengarah pada sintesis berbagai macam unsur ke dalam keseluruhan yang bersifat koheren dan terpadu.3)
Dengan pendekatan filosofis dapat diusahakan untuk mengerti pendirian suatu pendapat dan norma-norma yang dipakai seorang pengamat dalam menilai karya seni. Pendekatan filosofis juga tidak selalu memberikan jawaban tunggal tetapi bisa bersifat multiinterpretatif. Kemudian pengintegrasian dilakukan dengan mendekatkan keimanan kepada Tuhan sebagai dasar pemikiran, bahwa semua imajinasi dan ide yang bertujuan baik dan mulia adalah ciptaanNya, maka perlu diupayakan dalam setiap proses berkarya nilai kebenaran, keadilan dan kesucian patut dijunjung tinggi dalam membangun peradaban manusia yang lebih baik.
MORALITAS DALAM BERKARYA
Keprihatinan moral dan persoalan-persoalan moral menjadi mengemuka dalam perkembangan budaya global yang menampikkan nilai kemanusiaan. Di sini digunakan kata ‘moral’ dalam pengertian filsafat kewajiban. ‘Moral’ digunakan untuk merujuk hal yang benar atau salah serta bagaimana kita bertindak dan berpikir sesuai dengan prinsip betul dan salah. Immanuel Kant,4) yang terkenal dengan teori kewajiban (imperative) menyatakan karya seni yang memenuhi unsur ‘kehendak baik’ adalah karya seni yang baik menurut dirinya tanpa pamrih dan tanpa syarat. Dalam dunia manusia melawan nafsu-nafsu dirinya, maka kehendak bisa dilakukan dengan maksud-maksud tertentu yang tidak baik pada dirinya. Kant kemudian membedakan antara ‘tindakan yang sesuai dengan kewajiban’ dan ‘tindakan yang dilakukan demi kewajiban’. Yang pertama, menurutnya tidak berharga secara moral dan disebut hanya memenuhi “legalitas”, sedang yang kedua bernilai moral dan disebut moralitas. Pandangan inilah yang kemudian disebut sebagai imperatif moralitas.
Pandangannya tersebut mulai dikritik karena memunculkan “rigorisme moral” (rigor = keras, kaku, ketat), karena Kant menolak dorongan hati (belas kasih, setia kawan, dsb) sebagai tindakan moral. Kemudian untuk menjelaskan hal itu, Kant sebenarnya ingin mengatakan bahwa dalam moralitas yang penting adalah pelaksanaan kewajiban meski kadang tidak mengenakkan hati. Dorongan hati macam itu bisa saja baik, tapi moralitas tidak terletak padanya.5)
Karya visual tercipta dari beberapa proses yang tidak terlalu mengikat dan sesuai dengan bakat kepribadian masing-masing seniman atau desainer. Proses penciptaan karya yang lazim dipakai tersebut adalah teori milik Graham Wallas dalam buku The Art of Thought.6) Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
 Gambar 1. Alur penciptaan karya model Graham Wallas
Gambar 1. Alur penciptaan karya model Graham Wallas
Dalam proses demikian, keadaan dalam menciptakan karya seni tidak selalu tergantung pada urutan di atas. Proses berjalan dan kerap yang terjadi adalah kreator visual telah melangsungkan tahap elaborasi (perluasan) saat tiba-tiba pada tahap inspiration (ilham) muncul ilham baru. Maka bisa ditebak eksekusi karya pun berubah tanpa benar-benar melalui pemikiran yang mendalam.
Kondisi demikian menyebabkan terjadinya banyak ‘lubang’ sehingga karya visual belum benar-benar terseleksi dengan baik. Komunikasi yang diharapkan antara pembuat dengan pengamat pun tidak berjalan dengan baik melalui karyanya. Selain itu tidak adanya kontrol terhadap karya yang memungkinkan memunculkan pola kekerasan, percabulan dan nilai-nilai yang keluar dari moral tidak bisa diminimalisasikan dalam proses berkarya tersebut. Pada proses inkubasi seharusnya bisa saja diminimalisasi dengan melakukan proses seleksi ide, namun hal tersebut jarang dilakukan karena pada tahap memperoleh ide (inspiration), hal tersebut bisa tergeser oleh ide lain yang seharusnya diikutkan serentak pada tahap inkubasi.
Untuk meminimalisasikan karya yang cenderung tidak sesuai dengan konsep moralitas yang tidak memunculkan nilai kebenaran, keadilan dan kesucian ada proses penciptaan karya yang penulis tawarkan, yaitu:
 Gambar 2. Alur penciptaan karya terseleksi
Gambar 2. Alur penciptaan karya terseleksi
Bagan di atas menjelaskan alur penciptaan karya berdasarkan kematangan ide serta kematangan dalam mengeksekusi secara visual. Penggambaran visual yang tidak cerdas (kekerasan digambarkan secara vulgar, percabulan yang secara vulgar ditawarkan) bisa ditangkal sedini mungkin dalam tahap seleksi ide. Sehingga ketika ide yang seharusnya suci, mulia dan membangun bisa benar-benar dieksekusi secara visual. ‘Nyeni’ tidak harus keluar dari nilai moral atau asal beda, namun karya seni yang bagus dan mempunyai nilai estetika yang tinggi adalah karya yang mampu menimbulkan impact di masyarakat, yaitu tetap menawarkan kepada masyarakat ekspresi diri, kepekaan lingkungan dan tetap dapat menghibur dalam bahasa moralitas hubungan manusia dengan Tuhan. Ingat massa adalah bagian yang juga terpenting dalam proses penciptaan karya seni.
FENOMENOLOGI RELIGI DALAM KARYA VISUAL
Persenyawaan antara realitas dunia dengan imaji menghasilkan gagasan yang memulai adanya sikap teologia dalam beberapa karya visual. Konsep teologi Kristen dalam beberapa karya visual terbentuk dalam penggambaran Yesus yang mampu menembus batas wilayah dan ras. Hal tersebut misalnya penggambaran Yesus sebagai orang Jawa, Yesus orang Afrika, Yesus dari Cina dan sebagainya beserta assesoris yang menunjukkan dimana Dia berasal. Sifat penggambaran demikian membuktikan kepemilikan figur Yesus yang bahkan juga terdapat dalam poster propaganda Kuba yang berjudul Guerilla Christ. Poster ini menggambarkan Yesus memanggul senjata api laras panjang dan ikut menjadi seorang gerilyawan. Poster propaganda tersebut ingin memperlihatkan, bahwa Yesus adalah seorang penolong bagi mereka yang tertindas.7)
 Gambar 3. “Guerilla Christ” (1969). 8 )
Gambar 3. “Guerilla Christ” (1969). 8 )
Fenomena penggambaran karakteristik religius dalam Kristiani jelas tergambarkan seperti di atas karena memang audience yang menikmati adalah kalangan Kristiani sendiri. Namun bagaimana menyiratkan kebenaran, keadilan, kejujuran dan bukannya pornografi, kekerasan dan sebagainya dalam karya visual yang akan dinikmati banyak orang dan bersifat universal? Edmund Husserl pada tahun 1900 melalui Logische Untersuchungen menerapkan fenomenologi sebagai bagian penting cara melihat serta bersikap. Dalam fenomenologis ini seorang pencipta karya visual haruslah menarik diri atau surut dan bukannya melepaskan diri dari dunia. 9) Kreator visual yang sudah terlanjur mempunyai gaya surrealis tidak harus serta merta menggantinya dan beralih kepada karya yang bersifat religius. Begitu pula kreator visual tidak harus selalu mengikutsertakan figur maupun simbol Yesus atau merpati yang dekat dengan simbol Kristiani dalam setiap karyanya ‘hanya’ untuk menimbulkan muatan kebenaran.
Kekerasan, pornografi maupun ketidakadilan adalah realitas. Namun dalam fenomenologi ini, hal-hal tersebut dilihat sebagai “yang ada”. Penanda-penanda visual lah yang akan menerjemahkan hal-hal yang bermakna kebenaran sebagai kesamaan fenomenologis bahwa setiap “yang ada” dapat diingat dan mengambil tempat di dunia sebagai konsep-konsep. “Yang ada” identik tidak dalam artian harfiah sebagaimana kesamaan wujud dan rupa, sama disini terkait dengan suatu simpul yang lahir karena proses rekoleksi. Semua objek terkumpul sebagai suatu ‘dunia’ yang memiliki daya makna berlapis-lapis dalam arti mikro dan makrokosmik yang berkesinambungan.
Jadi, ketika kita menuntut bahwa karya visual jangan menggambarkan kekerasan, pornografi atau hal-hal yang melenceng dari moralitas, maka hal tersebut menjadi ketidakniscayaan. Bukan terpatok pada kekerasan atau pornografinya, namun semua masih bersikap terbuka dalam penginterpretasian. Mengapa demikian? Karena sejak lahir manusia sudah berdunia dan dunia memiliki “yang ada”. Hal inilah yang mencoba direkam oleh seniman untuk menuangkannya ke dalam karya seni sesuai dengan realita yang ada. Yang dibutuhkan agar karya visual tampil dalam kebenaran adalah penanda visualnya harus mampu menerjemahkan “yang ada” tersebut ke dalam kode-kode maupun simbol-simbol.
SENI: IDENTITAS, MORAL DAN BUDAYA
Seni sebagai integral dari kebudayaan selalu bersifat hybrid. Identitas budaya tidak ada yang tetap dan tegas serta tidak ada yang murni dan monolitik. Oleh karena itu, seni dianggap sebagai perwujudan media berekspresi yang sangat rentan dan dalam dirinya tidak ditemukan kemapanan karena adanya potensi yang senantiasa dan terus berubah. Perubahan budaya pada umumnya berada dalam daya tarik budaya maju yang selalu siap menggeser atau bahkan menghegemoni budaya lainnya.
Saat Desember Kelabu yang melahirkan Gerakan Seni Rupa Baru (1975-1979) dan diantaranya dimotori oleh Hardi dan FX Harsono, muncullah definisi seni rupa yang terkungkung oleh seni patung, seni lukis dan seni grafis serta anti elitisme. Hal ini tampak pada karya-karya mereka yang mengusung wacana seni instalasi yang merupakan akar dari perkembangan seni post-modernisme. “Pemberontakan” perupa muda inilah yang menjadi tonggak sejarah dalam menggeser identifikasi seni rupa konvensional.
Perkembangan lain dalam budaya adalah pergeseran media baru yang memperkenalkan konsep gaya hidup. Media baru seperti MTV merangsang para perupa, desainer, animator dan musisi gerakan bawah tanah (underground) untuk membuat karya visual yang bersifat kontemporer dan hal ini didukung oleh MTV yang visualnya tidak akan ditemui di stasiun televisi lain. Hal ini berkaitan dengan ditampungnya gaya desain dari wacana post-modernisme yang dianggap kalangan modern sebagai sampah.
Dari hal-hal tersebut di atas, budaya sebagai identitas tidak bisa ditebak ke mana arahnya. Industrialisasi kebudayaan dalam skala global telah menciptakan berbagai perubahan pandangan mengenai budaya itu sendiri yang kini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas-aktivitas ekonomi: produksi, distribusi dan konsumsi. Industrialisasi kebudayaan ini pulalah yang menciptakan paradigma budaya baru yang radikal, orientasi nilai budaya yang tak terbayangkan sebelumnya. Makna-makna budaya ini tentunya sangat kontradiktif dengan tradisi kultur, adat dan agama. Inilah peralihan budaya ke arah yang disebut sebagai “budaya konsumer”. Budaya konsumer menggiring masyarakat global ke pola-pola budaya yang telah terdiferensiasi ke dalam sub-sub budaya. Hal ini ditandai dengan cepatnya intensitas pergantian tanda, kode dan makna budaya dan semakin mencairnya identitas akibat arus pergantian identitas yang semakin cepat.
Disebabkan permainan tanda, makna, citra dan identitas tersebut dikendalikan oleh hasrat untuk meraih keuntungan, maka konsumerisme dengan mudah menjadi alat permainan dan tempat bagi dekonstruksi nilai-nilai adat, moral dan agama. Kapitalisme tubuh dipertontonkan oleh seni foto dengan model telanjangnya, darah sebagai inspirasi dalam video clip, ketidak jujuran yang diterapkan dalam periklanan serta yang lainnya.
Kehidupan keimanan yang ditandai dengan moralitas keagamaan bersama ajaran, identitas dan nilai-nilai yang dibawanya sebenarnya mulai menghadapi tantangan besar sejak adanya gerakan anti kemapanan pada era ’70-an, seperti gerakan feminisme, gerakan anak muda dangerakan sub kultur.10) Gerakan subkultur (gerakan hippies, punk, skin-head, dan sebagainya) menjadi tantangan kehidupan keagamaan karena bersifat lebih sebagai gerakan budaya daripada sebuah gerakan sosial politik. Seni yang lahir pada era setelah ’70-an tentunya mewarisi sifat-sifat demikian tadi. Di sinilah iman ‘ditantang’ dalam lingkupnya yang terhimpit oleh gerakanbudaya kontemporer.
Dalam kajian estetik visual, fakta artistik dari alam dan tubuh manusia adalah satu hal, sedangkan hal lainnya adalah ekspresi artistik dari manusia itu sendiri. Seperti ungkapan Sartre (1972) yang menyatakan, bahwa seni juga adalah sebuah kesadaran, maka ekspresi manusia mempunyai muatan kesadaran, bahkan manusia terlahir dari keseluruhan kesadarannya. Sehingga dengan demikian ekspresi artistik tidak hanya memenuhi kebutuhan hasrat (lust) artistik saja, namun juga harus memiliki tujuan atau berorientasi eksistensial sebagai manusia yang penuh kesadaran sebagai makhluk Tuhan.
Sejalan dengan hal tersebut, maka keindahan adalah sesuatu yang mesti dan bukan sebagai pilihan. Mengapa demikian? Karena bukankah Tuhan sendiri sudah berkesenian dengan segala keindahannya? Mencintai keindahan itu terwujud dari ciptaanNya, yaitu manusia dan alam semestanya. Dalam seni, keindahan adalah harmoni (cosmos) dan bukan kebalikannya chaos (disharmony).
SIMPULAN
Hasrat religi dalam berkesenian merupakan dua hal yang bersumber pada dimensi pengalaman terdalam manusia yang menceritakan ideologi manusia dengan segala sesuatu termasuk Tuhan. Kejadian-kejadian yang bersifat realis itulah yang akan tergambarkan dalam karya visual yang dibuat. Agama sebagai pangkal moralitas memang tidak harus mengkooptasi seni sedemikian rupa seperti jaman di abad di mana agama melalui gereja menjadikan seni sebagai alat dari agama untuk menyampaikan ajaran-ajaran dan dogma-dogmanya, sehingga seniman diharuskan membuat karya-karya yang berkaitan dengan ajaran dan dogma Kristen belaka. Pemahaman yang lebih radikal lagi adalah di luar karya gereja, maka karya tersebut adalah sesat. Moralitas dalam berkesenian tidak seperti ini. Jangan sampai hanya karena ketidaksetujuan atas simbol-simbol maupun tanda-tanda yang ada dalam karya visual kemudian menganggapnya sebagai karya seni yang menyesatkan.
Yang harus dipahami adalah kesadaran bahwa karya visual yang dibuat merupakan agen dalam perubahan apapun, termasuk agen budaya. Karya visual yang berangkat dari pemahaman ini tentunya mempunyai konsepsi-konsepsi dalam melakukan ‘perburuan ide’ yang di dalamnya mempunyai muatan-muatan tidak hanya berorientasi pada konsumtif semata tetapi juga melakukan penyadaran pada masyarakat, misalnya seni yang membawa perdamaian dan sebagainya. Dalam konteks seni modern seperti sekarang ini, nilai-nilai keimanan menjadi sesuatu yang penting dalam menghadapi kultur yang sangat berkembang beserta dengan pola pikir masyarakat yang semakin beragam. Seni yang multi-interpretasi sedapat mungkin tetap meluhurkan nilai-nilai kemanusiaan, ke-Tuhanan serta penafsiran personal tentang nilai dan hubungan antara manusia dengan Tuhan.
“Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.” (Flp.4:8).
_________________________
1) Wiryomartono, Bagoes P. Pijar-Pijar Penyingkap Rasa: Sebuah Wacana Seni dan Keindahan dari Plato sampai Derrida. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. h. 33.
2) Wiryomartono, Ibid. h. 97.
3) Sumaryono, E. Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat. Cetakan ke-5 (edisi revisi). Yogyakarta: Kanisius, 1999, h. 139.
4) Wiryomartono, op. cit, h. 32.
5) Hardiman, F. Budi. Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 146.
6) Djelantik, A.A.M. Estetika Sebuah Pengantar. Cetakan Kedua. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 2001, h. 64.
7) Wicandra, Obed Bima. 2004. Relasi paradigmatik ikon kristiani dalam poster propaganda Kuba. Jurnal Nirmana. Volume 6 Nomor 1. Januari, h.13.
8) Poster ini dibuat oleh Rostgaard (desainer grafis asal Kuba) diangkat dari ucapan seorang gerilyawan Kolombia yang tewas tertembak tahun 1966. Sebelum wafat ia berujar, “If Jesus were alive today, He would be a guerillero”.
9) Wiryomartono, Bagoes P. Pijar-Pijar Penyingkap Rasa: Sebuah Wacana Seni dan Keindahan dari Plato sampai Derrida. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. h.108.
10) Piliang, Yasraf Amir. Prolog: Seni, Nation-state, Identitas dan Tantangan Budaya Global dalam Aspek-Aspek Seni Visual Indonesia: Identitas dan Budaya Massa. Edisi I. Yogyakarta: Yayasan Seni Cemeti, 2002, h.19.
KEPUSTAKAAN
Djelantik, A.A.M. Estetika Sebuah Pengantar. Cetakan Kedua. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 2001.
Hardiman, F. Budi. Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Sartre, Jean Paul. Psikologi Imajinasi. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002.
Sumaryono, E. Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat. Cetakan ke-5 (edisi revisi). Yogyakarta: Kanisius, 1999.
Piliang, Yasraf Amir. Prolog: Seni, Nation-state, Identitas dan Tantangan Budaya Global dalam Aspek-Aspek Seni Visual Indonesia: Identitas dan Budaya Massa. Edisi I. Yogyakarta: Yayasan Seni Cemeti, 2002.
Tester, Keith. Media, Budaya dan Moralitas. Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2003.
Verhaak, C. dan Haryono Imam. Filsafat Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
Wicandra, Obed Bima. Relasi paradigmatik ikon kristiani dalam poster propaganda Kuba. Jurnal Nirmana. Volume 6 Nomor 1. Januari, 2004.
Wiryomartono, Bagoes P. Pijar-Pijar Penyingkap Rasa: Sebuah Wacana Seni dan Keindahan dari Plato sampai Derrida. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
![]()
Sumber: Desa Informasi > Pusat Penelitian (Research Centre) Petra Christian University
“Desa Informasi” or “Information Village” is the name adopted for the Local eContent (digital information resources with local flavor) development project being carried out in Petra Christian University Library.
“Desa Informasi” can also play an important role in preserving (at least) digitally local historical and cultural heritage, thus preserving the collective memory of a local society.
All Local eContent collections are available for everyone through the Internet for free. Some Local eContent collections are currently available in “Desa Informasi,” such as Surabaya Memory, Digital Theses, eDIMENSI, Petra@rt Gallery, Petra iPoster, and Petra Chronicle.
![]()
Obed Bima Wicandra
Dosen Jurusan Desain Komunikasi Visual
Fakultas Seni dan Desain-Universitas Kristen Petra
•••
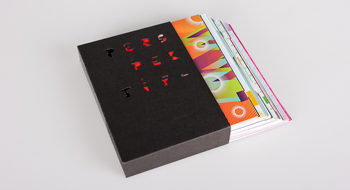



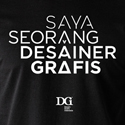



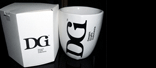

 1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto
1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto 2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong
2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong 3. Hurufontipografi | Surianto Rustan
3. Hurufontipografi | Surianto Rustan www.underconsideration.com
www.underconsideration.com

Dear Obed, ulasan Anda amat menarik. Masyarakat produksi visual sering tidak memperhatikan lagi soal ‘moralitas’ dalam berkarya karena sudah tidak dianggap relevan. Saya hanya ada sedikit saran untuk memperkaya tulisan ini, silakan dipertimbangkan atau tidak… Mungkin perlu disinggung bagaimana filsafat Plato (walau ia tidak membahas visual) serta Neoplatonisme di estetika monoteisme (Plotinus yang membahas emanasi dan remanasi dalam karya seni) serta Arsitoteles dan Scholasticism (di Abad Pertengahan dengan hylomorphism-object = matter + form-dan ‘goodness’) mempengaruhi filsafat estetika modern yang dipicu mulai dari Descartes dan tumbuh hingga ke Kant dan pemikir kontemporer lainnya.
estetika = etika (Muelder).
Luar biasa Karna!
Waduh, haha…yang hebat itu Wittgenstein, di tractatus dia menyatakan: “Ethics and aesthetics are one and the same.”
Saya cuma kebetulan dipertemukan dengan Maurice M. Eaton yg dengan sengaja mengangkat definisi ‘estetika’-nya sebagai etika.
Moral barangkali salah satu alasan mengapa desainer perlu merefleksikan kenapa ia mendesain seperti yang ia desain itu.
[…] ______“Melahirkan Imperatif Moralitas dalam Karya Visual” dalam Jurnal Nirmana. Januari 2005/Vol. 7/No. 1. […]