Pada hari Sabtu, 8 November 2008, di DKV ISI Yogyakarta telah dilangsungkan kuliah terbuka dengan narasi sejarah, yaitu Iklan Enamel (oleh Karina Rima Melati, alumni DKV ISI, mahasiswi S2 Ilmu Religi dan Budaya Sanata Dharma Yogyakarta), Etiket Teh oleh Johanes Budi Gunawan (alumni DKV ISI Yogyakarta), dan Kemasan Wingko Babat Semarang oleh Natalia Afnita (mahasiswa DKV ISI semester 7). Berikut adalah makalah yang disampaikan oleh Natalia Afnita. (Redaksi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budaya Kemasan Wingko Babat
Natalia Afnita
“The product is the package”, sebuah produk adalah sebuah kemasan itu sendiri.. Berangkat dari sinilah keingintahuan mengenai produk makanan lokal wingko babat dimulai, dan dari wingko babat Cap Kereta Api-lah pembahasan lebih lanjut mengenai sebuah kemasan meluas.
Pada umumnya orang mengenal wingko babat sebagai makanan khas dari Semarang. Ini dikarenakan sebuah merek terkenal lahir di ibukota Jawa Tengah ini, sehingga dari satu merek tersebut, lahirlah banyak pesaing yang memperkaya jumlah produsen wingko di Semarang. Meskipun demikian, dari namanya akan dapat diketahui bahwa sebenarnya wingko babat berasal dari Kota Babat, yang merupakan daerah kecil di Lamongan, Jawa Timur.
Bagaimana satu merek bisa berpengaruh terhadap perkembangan produksi wingko babat di sebuah daerah yang notabene bukan merupakan daerah asal produk tersebut, dengan kemasan yang identik, serupa tapi tak sama, sehingga memunculkan banyak alternatif kemungkinan dari sudut pandang yang berbeda?
Mengutip Seno Gumira Ajidarma dalam tulisannya mengenai Riwajat Persaingan Wingko Babat dari majalah Blank! Edisi 6 tahun 2003, memperkuat keingintahuan akan pembahasan mengenai wingko babat itu sendiri :
“..merk-merk wingko babat ini hanya bisa berbicara lebih baik dengan memperhatikan kembali hubungan-hubungan di bawah permukaan melalui sudut pandang baru, yang tidak lagi peduli kepada ‘indah tak indah’, bukan bagaimana kebudayaan terpajang sebagai benda-benda, melainkan kepada bagaimana kebudayaan itu berlangsung.”
Sekilas Sejarah Wingko Babat di Semarang
Masyarakat Semarang hampir dipastikan akan menunjuk wingko babat Cap Kereta Api sebagai rujukan wingko terenak di kota ini. Tak heran kalau kita tahu bahwa ternyata produsen dari merk inilah memang, yang pertama mempopulerkan makanan khas Babat di Semarang. Dalam kemasannya tercantum bahwa wingko tersebut dibuat oleh D.Mulyono.
Awalnya seorang wanita Tionghoa kelahiran Tuban bernama Loe Lan Hwa bersama suaminya The Ek Tjong alias D.Mulyono beserta kedua anaknya mengungsi dari Kota Babat ke Semarang sekitar tahun 1944 karena suasana panas Perang Dunia II membuat kota Babat terimbas huruhara. Sang suami lalu mendapat pekerjaan di K.A. jurusan Tawang-Surabaya Pasar Turi, sedang sang istri lalu mencari usaha tambahan membuat dan menjual kue wingko, dan ternyata memang merupakan keahlian yang diturunkan dari ayahnya, Loe Soe Siang. Kue itu kemudian dijajakan di sekitar stasiun K.A Tawang Semarang, tempat suaminya bekerja.
Kue wingko buatan Loe Lan Hwa itu ternyata banyak disenangi warga Semarang. Banyak yang menanyakan nama kue tersebut. Di Babat sendiri kue tersebut hanya disebut kue wingko. Maka, untuk memenuhi keingintahuan pembelinya dan sekaligus sebagai kenang-kenangan terhadap Kota Babat tempat dia dibesarkan, Loe Lan Hwa menyebut kue buatannya itu sebagai wingko babat.
Dengan dijual di stasiun, tersebarlah kue itu ke mana-mana sebagai oleh-oleh. Sampai saat ini pun kue wingko babat masih tetap dicari oleh orang-orang yang berkunjung ke Semarang, untuk dibawa pulang sebagai salah satu makanan oleh-oleh.
Ilustrasi kereta api yang dibuat dalam kemasan wingkonya merupakan pilihan dari D.Mulyono, karena ketertarikannya dengan gambar kereta api pada sampul muka buku formulir isian saran di gerbong restorasi. Pada awalnya dia menggunakan gambar kereta api dengan sebutan Cap Spoor. Tapi kemudian, sesuai perkembangan bahasa Indonesia, kata-kata Cap Spoor diganti dengan Cap Kereta Api.
Kue wingko babad cap Kereta Api buatan Loe Lan Hwa itu semakin terkenal dan dicari banyak orang untuk oleh-oleh dari Semarang. Hal ini pun lalu menarik orang lain untuk mencoba membuat kue yang sama dengan menggunakan gambar kereta api juga sebagai mereknya, walau gambarnya tidak sama seratus persen. Keadaan ini cukup membingungkan konsumen.
Maka, untuk membedakan kue wingko babad buatannya dari buatan orang lain, Loe Lan Hwa kemudian mencantumkan nama suaminya “D. Mulyono”, dengan di belakangnya ditambah kata-kata “d/h Loe Soe Siang” (nama ayahnya) pada pembungkus wingko babad buatannya. Tambahan “d/h Loe Soe Siang” tersebut dimaksudkan sebagai penegasan bahwa wingko babad merek D Mulyono itu merupakan kelanjutan dari wingko babad yang dibuat Loe Soe Siang di Babad. (sumber:Kompas, 26 Mei 2003 & brosur wingko babat Cap Kereta Api)
Analisis Kemasan Etiket Wingko Babat
Kemunculan dan kesuksesan merk Cap Kereta Api sebagai perintis wingko babat di Semarang, seperti magnet yang menarik pengusaha lain untuk turut memproduksi wingko babat dengan kemasan yang identik, serupa tapi tak sama, sehingga menimbulkan kebingungan konsumen ketika memilih. Dalam analisis semiotik Seno Gumira pada tulisannya mengenai ‘Riwajat Persaingan Wingko Babat’, disebutkan bahwa bagaimana pemilihan gambar kereta api dengan lokomotif batu bara sebagai ilustrasi kemasan makanan empuk nan gurih ini bisa diterima dan terhubungkan dengan citarasa enak?
Kemungkinan pertama ialah konsep modernitas, yang pada saat kemunculan pertamanya, kereta api dengan lokomotif itu merupakan representasi kemajuan , perubahan kearah yang lebih baik, penghubung dari kota ke kota, kecepatan dalam menempuh jarak, ruang dan waktu. Singkatnya, kecepatan itulah ciri modernisasi, dan modernisasi itulah kesempurnaan mengenai gagasan rasionalitas. Sehingga apabila suatu merk berwujud gambar kereta api yang terpampang dalam kemasan wingko tersebut, bisalah diandaikan bahwa maksudnya adalah menunjukkan betapa cita rasa wingko didalamnya adalah juga yang sempurna, yaitu yang paling enak.
Kemungkinan kedua jauh lebih sederhana: wingko ini dijual di stasiun Tawang, dan kereta api-lah gambar yang paling tepat untuk mengingatkan dimana wingko ini dijual. Dan menurutnya, logika para ‘bakul’ yang cenderung konkret karena alasan tersebut mungkin masih bisa diterima, namun konsep modernitas lebih dianggap memungkinkan perbincangan lanjutan.
Konsep modernitas mengantar kita kepada produsen lain yang tak kalah seru-nya memilih gambar kereta api sebagai ilustrasi kemasannya. Bermunculanlah merk-merk wingko babat seperti Cap Kereta Api Expres, Cap Kereta Api Senja Utama, Cap Kereta Api Argo, dll. Merk-merk inilah yang memperkuat konsep modernitas, karena seiring berjalannya waktu, kereta api-pun juga mengalami perkembangan, bahkan juga alat transportasi selain itu. Dan rupa-rupanya gagasan lebih cepat berarti lebih modern sangat disadari oleh D.Mulyono terhadap para pesaingnya yang setidaknya secara simbolik telah melebihinya, sehingga dalam satu masa perkembangan perusahaannya, ia sempat mengganti merknya menjadi ‘Cap Kereta Api Diesel & Jet’ (Dengan gambar kereta api berlokomotif diesel dan jet di atasnya).
Lain lagi dengan kompetitornya bernama N.N.Meniko yang tampil dengan merk Cap Setoom Mini, menampilkan alat transportasi yang sangat lambat, jauh dari representasi modern. Namun jika diteliti lebih lanjut, imbuhan kata ‘asli’ di dalam kemasannya akan menjelaskan konsep N.N.Meniko dilihat dari makna ‘yang tertua’, yang pertama, yang asli… Seolah imbuhan ini menjadi keunggulan kemasan karena sekaligus mempromosikan dirinya sebagai yang ‘asli’, meskipun kenyataannya tidak demikian.
Selain berkompetisi dalam keunggulan kecepatan kereta api karena konsep modernitas tersebut, kompetitor lain bermunculan dengan varian transportasi yang berbeda. Contohnya Wingko Babat Cap Bus Bisnis, Cap Mobil Antik, Cap Kapal Laut, Cap Kapal terbang, Cap Kapal Laut, Cap KM. Mutiara, dll. Merk-merk ini dianggap masih saja terbayang kesuksesan Cap Kereta Api, karena dilihat dari macamnya, merk yang digunakan masih menginduk pada alat transportasi. Representasi yang timbul dari konsep pemilihan alat transportasi seperti kereta api, bus, kapal laut / kapal terbang ialah sebuah sarana yang menunjukkan prasarana dimana logikanya menjelaskan keberadaan tempat transit dari segala penjuru, dari berbagai macam orang datang dan pergi, sehingga merupakan tempat yang strategis dalam menjajakan berbagai varian oleh-oleh, termasuk juga wingko. Selain itu, konsep mengenai kenyataan yang ada, realitasnya, symbol kereta api sebagai modernitas tak lagi cukup menjelaskan bahwa kereta api mewakili citra modernitas saat ini. Banyak alat transportasi lain yang berkembang dan menjadi alternatif selain kereta api yang sama halnya menjadi alat yang menghubungkan ruang, jarak dan waktu yang singkat. Dan meski masih terkesan mengekor sebagai pengikut Cap Kereta Api, pemilihan alat transportasi lain sebagai merk mungkin mengindikasikan beragamnya tempat penjualan wingko saat ini, tak hanya di sekitar stasiun seperti awal mula kesuksesan Cap Kereta Api, namun juga di terminal bus, pelabuhan, bandara, dll. Hal ini mungkin yang menjadi pertimbangan para produsen baru dalam membaca peluang selain masih berpatok pada alasan D.Mulyono memilih kereta api.
Ada pula kompetitor merk Cap Stasiun Lokomotif yang lebih kreatif dengan memunculkan gambar stasiun, dimungkinkan karena pesaing lain masih berkutat seputar alat transportasi sebagai gambaran yang hampir serupa dengan merk Kereta Api agar konsumen seolah terkecoh dan kebingungan saat memilih. Namun wingko dengan merk ini seperti berjalan di jalurnya sendiri, karena realitas stasiun sebagai ‘rumahnya’ kereta api, bisa membuka 2 kemungkinan. Pertama, secara halus mengungkapkan bahwa merk ini juga berlomba memberi kesan ‘asli’ atau paling tidak tak jauh dari aslinya , karena merk Kereta Api yang menggunakan gambar kereta api pastilah membutuhkan stasiun sebagai tempat berhentinya penumpang. Jadi kaitan antara stasiun dan Kereta api ialah suatu hubungan yang tak terpisahkan. Kemungkinan kedua, stasiun sebagai pemberhentian kereta merupakan tempat dijualnya oleh-oleh berupa wingko babat seperti halnya wingko merk Kereta Api yang pada mulanya dijual di stasiun oleh D.Mulyono (meskipun dalam kemasan tidak tercantum tempat penjualan di stasiun).
Terakhir, kompetitor wingko babad Cap Cakra dengan konsep merk dan gambar etiket yang tak ingin mengekor pada fenomena kesuksesan gambar kereta api menjadikan produknya lain dari yang lain . Gambar yang digunakan adalah cakra dan produsennya adalah Sri Kresna. Dari keduanya dapat diketahui bahwa cakra adalah senjata dari Kresna. Ia menggunakan symbol yang tak ada hubungannya dengan kereta api maupun alat transportasi lainnya. Tapi dari ukuran kemasan, penataan merk dan gambar, masih bisa dikategorikan terbius dengan pakem kemasan wingko babat a la Cap Kereta Api.
Kesimpulan
Dari sebuah kemasan, memunculkan kemasan lain yang identik, baik merk, warna, tipografi, layout, ukuran dan bentuk kemasan. Faktor kesuksesan dan perintisan pertama dimungkinkan yang membuat hal ini banyak terjadi di sekitar kita. Dalam hal ini wingko babat Cap Kereta Api merupakan perintis sebuah ‘pergerakan’ persaingan wingko babat di Semarang.
Konsep Modernitas yang membawa pesaing dengan nama kereta api yang lebih modern belum mampu menggeser kepercayaan akan simbol kereta api yang masih berlokomotif batu bara. Konsep realitas mengenai varian alat transportasi sebagai tempat dijualnya oleh-oleh termasuk wingko, juga belum cukup bersaing meski banyak imbuhan ‘asli’ menyertainya. Bahkan konsep kreativitas dan keunikan merk yang muncul-pun seolah menghiasi jajaran pesaing di level amatir, meski keberanian untuk tampil beda merupakan hal yang patut dihargai. Terkadang merk-merk yang mengikutinya terdengar semakin aneh bahkan nyleneh ditelinga, karena cabang dari merk pertama, kedua dan seterusnya menghasilkan berpuluh-puluh merk untuk sekedar mengecoh konsumen dari produk aslinya. Fenomena ini menarik untuk diamati, karena sejauh apapun para kompetitor berusaha menampilkan produknya berbeda, tetap saja masih ada sisa-sisa ‘penghormatan’ pada produk aslinya.
“The product is the package”, adalah awal mula dan berakhirnya ulasan ini. Wingko babat dan kereta api-nya adalah contoh hubungan simbiosis mutualisme, meskipun pada mulanya kereta api dipilih karena faktor kesukaan dan bukan dari hasil pemikiran konsep yang panjang. Mungkin D.Mulyono sendiri tak mengira persaingan wingko babat ini justru bermula dari kereta api yang dipilihnya. Namun cabang yang ditumbuhkan dari benih itulah yang membuat kebudayaan berlangsung sehingga memunculkan banyak alternative pertanyaan baru yang direspon otak jika kita mengamatinya.
•••
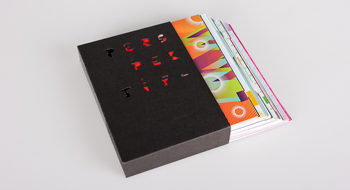


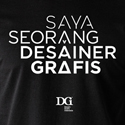




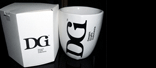

 1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto
1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto 2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong
2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong 3. Hurufontipografi | Surianto Rustan
3. Hurufontipografi | Surianto Rustan www.underconsideration.com
www.underconsideration.com

[…] oleh: Natalia Afnita | via: DGI Blog […]