Seni kontemporer Indonesia memang memuat gejala yang beragam dan unik. Tak mudah untuk menandai atau memberi sebuah identitas, apalagi memastikan genre estetika tertentu yang disematkan dalam membaca sebuah pemaparan karya seorang perupa.
Pameran solo, perupa Magdalena Pardede, dengan tematik: Unforgotten Paradise, tentulah bisa dibaca dengan keunikannya tersendiri, sebagai sebuah arus kecenderungan beragamnya seni kontemporer di Indonesia. Salah satunya adalah pengamatan terhadap kegemaran Magda dengan membuat proses berkaryanya via medium karya berbasis seni cetak grafis dan sekaligus seni cetak digital.
Kita akan segera teringat bahwa, medium seni berbasis cetak grafis mengalami metamorphosis yang tidak linear kehadirannya di tanah air, sebagaimana “lurusnya” pembabakan keberadaanya didalam sejarah seni di barat.
Apa yang dikatakan oleh Claire Holt, di Art in Indonesia: Continuities and Change (1967, New York), sangat menarik sebagai sebuah rujukan/ patokan awal. Peneliti dari Cornell University dengan buku yang dianggap “babon” seni modern (dan menjejaki kemunculan “seni kontemporer”) di Indonesia ini, menyimpulkan, bahwa sejatinya seni modern Indonesia adalah merefleksikan kreatifitas yang mencari-cari dari para seniman secara terbuka dengan pengaruh endapan estetik seni masa lampau dan semangat seni masa kini. Seni rupa Indonesia adalah “mozaik” apa yang telah menjadi “kekayaan lokal seni visual” kita selama ratusan tahun, sekaligus menjelajahi nilai-nilai seni rupa dunia (terutama barat) yang menghampirinya “dalam masa pendek” di abad 19-20 dalam proses kesadaran nasionalisme versus kolonialisasi (yang kemudian dihasratkan sebagai
paradigma paska kolonialis). India, Cina dan Timur tengah adalah sebuah hal ikwal yang melatari pembentukan seni rupa kita sebelumnya.
Ciri Baru Evolusi Seni Grafis
Sementara itu, seni grafis yang dikatakan modern, di peradaban barat, mengalami “gegar estetik”, dengan adanya pengaruh luar biasa dari Gerakan Dada, awal abad 20 (Zurich, Cabaret Voltaire, Hugo Ball Diary, 16 Juni 1916), yang sohor dengan pembongkaran apapun tetang nilai-nilai yang dianggap mapan di seni rupa modern dunia.
Dengan demikian, seni grafis pun, mengalami “koreksi”, dengan sebuah ciri seni grafis baru, – jika paradigma modern dan paska modern dihitung dari munculnya gerakan Dada ini dengan sebutan “seni kontemporer”, termasuk seluruh kesadaran tentang realitas yang bertumpu pada pemahaman nilai-nilai dan standar modern barat diralat – mengemuka dengan metode, presentasi ke publik, pemaparan gagasan estetik dan medium yang jauh sekali sangat berbeda dengan kurun waktu sebelumnya.
Gerakan para avan gardaist Dada yang berawal di Eropa (Zurich, Hugo Ball cs) kemudian berlanjut di Negara Eropa lain, eksistensi seni grafisnya dianggap telah menemukan cara ungkap visual dan gaya ekspresi baru, Bahkan, yang lebih radikal, melabrak kaidah-kaidah lama yang dianggap telah “lapuk”. Sebagai contoh: nongolnya seni grafis di “sembarang tempat” dengan nama-nama yang “mendekati” grafis adalah gelatin silver print, lithograph painting and photo montage bercampur chromolithograph (di Paris dengan Francis Picabia), dan sebaliknya, memperkaya dunia “applied art”. Untuk urusan presentasi ke publik, karya-karya tersebut di pamerkan di galeri yang dianggap mainstream di Jerman,( seperti karya-karya Max Ernst), atau di ulas karyanya-karyanya di jurnal Dada di Amerika misalnya (karya Marchel Duchamp) dll. Semua ekspresi medium dieksplorasi, mereka menemukan pula found object art selain assemblage art dikemudian hari.
Seperti kita mahfum, seni grafis, dulunya, sering dianggap hanya sebagai seni terapan, dengan kelemahannya karena bisa direproduksi ulang, dengan sistem cetak, maka tak lagi “orisinal”, hingga tak layak disebut sebagai seni yang “fine”. Kehilangan aura otentisitasnya. Seni grafis, dalam beberapa praktik, oleh para seniman bisa diperpanjang hidupnya, dengan berbagai cara, seperti: alat untuk propaganda, baik sifatnya yang politis-ideologis maupun kebutuhan-kebutuhan industri komersial (cover buku, poster iklan dll) .
Para Dadaist tak peduli, mereka jalan terus, menggunakan seni grafis “untuk kebutuhan apa saja”, kita bisa menemukan karya-karya “etsa-campuran”, para eksponennya, seperti: Max Ernst atau Francis Picabia menggunakan berbagai kombinasi etsa tersebut dengan drawing, art obyek, atau kolase photo montage, serta cat minyak/cat air didalam sebuah kanvas atau bahkan papan.
Di sebuah pameran gerakan Dada ini, kita sulit menemukan mana yang disebut secara orisinal, memakai karakter berlabel seni grafis dengan ciri “kemurnian” seperti: etsa, lithograph atau linograph yang kita kenal? Sebuah zaman baru telah lahir, sebuah revolusi seni sedang berjalan. Dalam waktu yang sama, teknologi cetak offset, segera saja membuat fotografi memungkinkan tak hanya dicetak di film seluloid dan kemudian dikertas, namun bisa dicetak diatas plastik, atau media apa saja. Maka cetak saring (silk screen) sebagai media cetak baru menjadi media grafis anyar “jagoan” dari generasi sesudah Dada, layaknya kita menemukan di Neo Dada, Fluxus atau Pop Art di tahun 1940-1960an. Selanjutnya, bisa ditebak: tentulah kemunculan seni cetak digital, yang tak lepas dari pengaruh ditemukannya fotografi digital, mesin cetak/ offset digital dan digital imagery dengan komputer pada akhirnya lebih memperkaya lagi di wacana seni grafis kontemporer barat.
Untuk urusan piranti teknologi, kita masih ingat, semua ini juga berawal dari bagaimana Gerard Ritcher (1960-1970 photo-painting, Buchloch Essay), seniman Jerman menguarkan kredonya yang “aneh” tentang photo-painting di genre seni lukis dan keberadaan teknologi sebagai sebuah alternatif dari tesa sekedar alat bantu atau tujuan artistic kaitannya dengan sebuah lukisan? Demikian pula, seni cetak digital yang mengambil imej dari photography digital, selanjutnya, memperkaya seniman-seniman digital art-painting dari seniman seni grafis sesudah era Gerard Ritcher.
Kelahiran seni cetak digital di tanah air, tak bisa tidak, dikaitkan dengan ihwal perkembangan seni grafis yang lebih lama eksis. Kedua jenis seni ini—baik seni cetak digital (digital art) dan seni grafis- yang kadang diibaratkan bagai saudara kembar—karena keduanya bertumpu pada sistem cetak-, yang berjuang untuk tetap dan akan selalu ”diakui”, dibanding seni lukis dan patung yang lebih popular dahulu.
Seni grafis yang dianggap “telah kuno” bagi kita, diwakili di sejarah, sebagai contoh, tahun 1946, Baharudin Marasutan dan Mohtar Apin, pada masa pergerakan menuju “mempertahankan” kemerdekaan Indonesia, melalui “diplomasi seni”, membuat karya cukilan kayu yang kemudian diperbanyak oleh Menteri Urusan Pemuda disebarkan ke sejumlah negara asing yang mendukung kemerdekaan Indonesia.
Namun, dikemudian hari, Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB), tahun 1970an, yang “setengah meminjam” apa yang dimanifestokan para Dadais di Eropa hendak pula “merombak” seni grafis yang telah dianggap menjadi “dekaden” di Indonesia. Tahun 1987, GSRB dengan tema Pasaraya Dunia Fantasi, media cetak saring menjadi ungkapan ekspresi visual baru dengan simbol-simbol dan tanda-tanda yang meledek dan memelesetkan perilaku konsumerisme dan materialism di kota besar Indonesia dengan gaya pop art nya. Dimasa ini, seni grafis telah dicampur dengan teknik drawing, fotografi, bahkan art object sekaligus seni instalasi, layaknya eksplorasi apapun dilakukan dengan ”manauladani” para pelopor Dada di Eropa.
Di ajang Penghargaan Nasional seni Lukis, tahun 1990 an, Kompetisi Philip Morris, kita juga menemukan berbagai karya yang dijagokan para juri bertendensi “nyeleneh”, dengan pengayaan-pengayaan baru, penjelajahan imajinatif, serta penemuan media cetak baru sebagai cara ungkap, jika dibandingkan karya grafis yang dianggap “kuno”. Berbarengan dengan itu, munculah para seniman grafis kontemporer sejak tahun 1980-1990an an, seperti Tisna sanjaya, FX Harsono, Agus Suwage, Marida Nasution sampai Firman Lie. Disanalah, pada akhirnya perupa Magdalena Pardede, tahun 1990an, muncul di permukaan dunia seni rupa kontemporer Indonesia. Magdalena Pardede, tepatnya, pada tahun 1995, meraih the best Indonesian painter dari kompetisi nasional Phillip Morris.
Magda, memiliki kehidupan yang unik, sering kali bereksperimen, karena bekerja sebagai pekerja desain grafis, selain menjadi fotografer lepas di berbagai agensi grafis komersil. Tak dinyana, inilah pengalaman yang membuat Magda tahun 1990an, mengenal Macintosh, mesin ajaib desain computer, bereksperimen dan mengenal dekat sekaligus dua saudara kembar seni berbasis cetak ini: Seni Cetak Digital dan Seni Grafis. Secara manual, tangannya terlatih dan piawai di akademi seni (IKJ), mengolah berbagai teknik kerja seni grafis murni. Namun, dilain pihak, ia dengan ringan pula menggunakan imej-imej desain komputer serta sekaligus photography untuk berkarya diluar bangku kuliah.
Magda terus, berkarya dan bekerja dengan keyakinannya sendiri. Ia mendapat berbagai undangan workshop dari mulai negara Jepang, Australia maupun Italia di tahun-tahun berikutnya. Magda juga tak lupa ikut berpartisipasi di event seperti Trienalle Grafis di tanah air. Sampai kemudian, pameran tunggalnya yang ke empat, tahun 2005, Magda membuat kolaborasi dengan Indra Leonardi, seorang photographer senior di Indonesia. Mereka bersama, nampaknya hendak mengumandangkan lajunya seni kontemporer sejalan dengan seni cetak digital, yang merayakan pertemuan seni grafis, seni photography digital dan desain komputer (digital imagery) secara bersamaan.
Anomali Rupa Mozaik dan Letupan Ekspresif
Seperti yang pernah ditandai oleh Claire Holt, seni rupa kita memiliki kecenderungan sebagai yang dianggap memiliki “mozaik”. Karena latar budaya pluralistik yang mencipta artefak kesenian yang kita kenal hari ini. Dalam penafsiran dan upaya pembacaan karya Magda, teknologi yang dipakai, terutama teknik digital adalah hanya sebagai alat bantu. Magda, memakai teknologi ini sebagai sebuah anomali atau bisa disebut pengecualian/ keanehan dalam cara berekspresi. Magda, seutuhnya, masih memakai “cara-cara lama” dalam mengungkapkan bahasa visualnya.
Seni cetak digital, dipakai oleh seniman-seniman barat, bahkan sejak tahun 1980-1990an, sepertinya lebih mengutamakan kapabilitas dan kecanggihan eksplorasi teknik dalam bertutur secara rupa. Mereka hendak melampaui apa yang dicapai oleh fotografi, dengan digital imagery bank, teknik montage mutakhir, sistem ilustrasi untuk mencapai presisi detailitas, bahkan penggambaran sebuah dunia fantasi yang “beyond of imagination”. Apalagi, dengan presentasi tekhnik vector art yang berbeda dengan pixel art, sebuah loncatan kecanggihan “rasa riil” di wilayah seni grafis digital ini. Realitas rupa hendak diciptakan melebihi kenyataan akan kesadaran akal. Mimpi hendak diwujudkan, hasrat inderawi, terutama mata hendak dimanja semaksimum mungkin .
Namun, apa yang dilakukan oleh Magda, benar-benar jauh dari perkiraan akan segala kecanggihan yang didapat dengan ditemukannya teknologi digital. Magda, malahan hendak “mengolok” teknologi ini, Bukannya, presisi super detailitas melampaui yang didapat oleh fotografi, justru detailitas dihilangkan, presisi diabaikan, struktur dicemooh, bahkan volume yang menerbangkan imajinasi seakan akan sebuah obyek atau benda bisa kita sentuh ditinggalkan begitu saja, perspektif ruang akan sebuah tempat fantasi yang menjadi riil seolah minta dijamah, malahan dihindari. Paparan rupa di kanvas lukisan digitalnya, tertumpah secara ekspresif, meletup-letup, berdimensi flat, tumpang-tindih kadang bercorak naïf. Obyek-obyek, bisa mencerminkan sebuah kenyataan seperti aslinya,(hasil montage fotografi) seringkali menjadi terpiuh, menghablur, terstilisasi, atau malahan menjadi kian ekspresif menyerupai bentuk-bentuk sederhana seperti lukisan kanak-kanak atau “yang paling eksterm” bagai lukisan – lukisan mereka yang belum pernah mengenal struktur anatomi sebuah bentuk obyek. Ini benar-benar penampakan visual yang anomalistik. Teknologi digital tidak digunakan dengan “semestinya”. Melainkan, mirip torehan-torehan atau gambar-gambar primitive dan berbau arkaik yang mengemuka.
Kita bisa mendeteksi, cara kerja sejak awal Magda, kadang-kadang ia mengoreskan penampakan garis-garis seperti mendekor, dengan tangan manual di kertas, seperti sketsa, dikombinasikan dengan sebuah imej hasil grafis etsa, kemudian sebuah gambar-fotografi montage dicampurnya dalam satu bidang dengan cara difoto sekaligus, atau diterapkan terpisah (tersendiri) dengan teknik scanning, selanjutnya dimasukkan di sistem program desain komputer, diacaknya, ditata atau disusun semaunya, seperti sebuah layar-layar yang saling menindih atau mungkin “berdialog” satu dan lainnya. Fase berikutnya, segera dicetak dengan ploter digital. Namun, kembali setelah tersedia di depan Magda, lagi-lagi “dirusaknya” dengan “menindihnya” lagi dengan cat akrilik atau cat minyak memakai kuas. Tentulah, hal ini mencipta sebuah gambaran mozaik yang ekspresif dan berkarakter unik.
Bisa dibayangkan, kanvas lukisannya acapkali menjadi rupa “chaos”. Apa kata Magda? Dengan entengnya dia berujar “Aku cuman menggunakan bentuk-bentuk,, mencampurnya semua, seperti berlapis-lapis menyerupai dinding-dinding penyekat separuh transparan, layaknya bermain mozaik saja”. Satu kali waktu, Magda menambahkan “ Ada seperti rasa berdebar-debar, rasa penasaran, atau semacam sensasi ketika melihat bentuk-bentuk itu bercampur semua, dan sepertinya tak terduga menjadi “sesuatu lagi” yang lain diluar perkiraan.
Hal ini, bisa dipahami, Magda, yang lama menggeluti dunia seni grafis manual, yang dulunya ”rasa berdebar-debar” ini dirasakan, misalnya seperti ketika membuat proses teknik aquatint, ia membentuk lapis-lapis atau layar bertindih, mencelup guratan di kepingan plat yang tiba-tiba saja setelah terendam di larutan asam nitrat, hasilnya menjadi demikian tak terduga. Sebuah surprise. Garis, gambar bentuk obyek atau warna menjadi eksotik menurutnya. Inilah, yang hendak dilakukan di teknologi komputer digital! Program Photoshop, hanya dipinjam untuk “mengaduk sup sayuran” dari” bumbu-bumbu“ teknik grafis manual biasa. Sensasi dirasakan bukan karena “kematangan sup” dalam derajat tertentu dan “tampilan sup” yang menggoda, namun rasalah menjadi segala. Meski dengan bumbu kuno dan tampilan “chaos”, rasa tetaplah lezat. Identifikasi oleh Claire Holt menjadi benar, bahkan sejak tahun 1960an, bahwa seni rupa kita adalah mozaik dari beberapa hal, bukan dari teknologi atau isme yang didapat dari barat, namun “cara berpikir dan cara berekpresi memahami dunia secara lokal” lah, dan ini berkaitan dengan budaya yang mengakar, perilaku orang timur yang “ekspresif” meski kadang memakai simbol-simbol, bersayap, bagai larik-larik sebuah pantun, dan meminta selalu untuk ditafsir, yang membuatnya menjadi sangat khas.
Apakah Magda, jika kita amati lagi, memiliki semacam “gumaman mantra” di tradisi timur, jika kita kaitkan dengan banyaknya imej-imej anak kecil, atau benda-benda lain yang selalu hadir repetitif dikanvas-kanvasnya? Atau mari kita selami lebih jauh, dengan gayanya yang “nyeleneh” dengan garis-garis bertenaga dan kesukaanya tak henti membuat semacam ornamen adalah “mewarisi” seni dekoratif peninggalan nenek moyang kita? Misalkan, batik yang di Jawa kita mengenal istilah “isen-isen”, yang mengilhami Magda, dengan bentuk-bentuk floral, repetitif dan ajeg?
Bisa saja ini terjadi, diambang bawah sadarnya terekam pola-pola yang ia kenal sejak lama, bahkan mungkin saja sejak kecil. Budaya Batak dan Jawa bersatu di dalam kehidupan Magda. Opungnya suka bercerita soal tradisi, keluarga besarnya selalu saling berbagi pengalaman, koleksi benda-benda tradisi dan Magda sendiri, mungkin saja yang hidup di Jakarta “tercerabut” dari akar azalinya, merindukan “yang lain”, mengimajinasi yang dulu nun jauh menghantui kesadaran pada masa kecil dan selalu dirindui ketika kelak dewasa.
Satu kali Magda bersemangat bertutur “Kenapa, jika aku mengerjakan dalam proses karyaku, seakan tak mau berhenti, mengulang-ulang, atau selalu menambahkan aksentuasi, obyek, imej, atau garis, bahkan ketika orang lain bilang karyaku semestinya sudah final?, karena aku ingin sekali bebas, menelusuri ruang-ruang hatiku yang tak kan pernah puas, bergolak, membagi apapun yang ada di rasa, yang kadang tak mengacuhkan kerja nalarku”. Magda, dengan pengakuannya, seperti ingin berjalan sendiri, menggumam, berteriak bahkan terus berlari, sebagai perwujudan kebebasan yang ingin ia raih dan memberinya pemaknaan dengan cara melukis dan hanya melukis dengan caranya yang amat khas tersebut.
Di terminologi barat, mungkin saja sejarah Art Burt, yang dikenalkan oleh seniman paling terkenalnya: Jean Dubuffet bisa di terangkan dengan jelas untuk alasan proses berkarya semacam Magda. Jenis seni ini, yang menanggalkan kerja nalar, dekat dengan istilah automatisasi fisik dan pembiaran laku syaraf-syaraf otak bergerak bebas (spontan). Gerakan surealisme, dengan tautan kajian psikoanalisa juga sangat mempengaruhi, dengan membiarkan ambang bawah sadar untuk bereaksi aktif, dirangsang untuk bergerak sebagai semacam outlet bagi ekspresi-ekspresi yang paling absurd, liar dan sangat primitif keluar dari kekangan alam ego ( ambang kesadaraan sosial dan etika serta nalar) muncul di permukaan.
Sigmund Freud lah yang mengidentifikasi bagaimana alam Id (bawah sadar sebagai hasrat azali) manusia, wajib menampakkan paras aslinya mengalahkan ego. Ambang tilik kesadaran yang seimbang di super ego (kesadaran untuk keseimbangan) sekali waktu tak di indahkan, berubah menjadi “yang lain” diluar struktur alam sadar, terutama ekspresi yang ditampilkan di dunia kesenian adalah keniscayaan.
Tapi, tentunya, Magda tidak demikian sepenuhnya, membebaskan diri dari kerja nalar sama sekali. Ini bisa dibuktikan dengan kekuatannya membuat konsep-konsep filosofis dan simbol yang relatif sistematik, runtut dan juga memiliki korelasi sekaligus koherensi pada tiap-tiap kanvas lukisannnya, antara satu dan lainnya, yang dalam pameran ini digelar 41 lukisan digital. Justru, pola kerja penerapan teknik dan ekspresi seperti Magda menjadi demikian mengejutkan, aneh lagi ganjil, acapkali paradoks dan kadang mendebarkan sekali. Ia bisa liar tak terarah, sulit dimengerti, namun seperti terbingkai dengan sebuah kesatuan pesan yang jelas dan terukur. Sebuah anomali atau pengecualian olah rupa mozaik tercipta! Seni sebagai sebuah tujuan estetik, memang memiliki relatifitas nilai. Ia selalu berubah sejalan perkembangan jaman dan keunikan individu sang seniman.
Dongeng Surga dan Kesadaran Kosmos Diri
Pameran solo Rotua Magdalena Pardede Agung di Four Season Hotel, Jakarta dengan tajuk Unforgotten Paradise menarik dan patut disimak secara tematik, selain keunikan dia dengan teknik digital art, serta olah rupa yang ekspresif tersebut. Magda, mengawali proses kreatifnya dengan pertanyaan-pertanyaan arti dan makna paradise yang datang dari melihat kosmos diri sebagai pusat semesta. Kejamakan makna surga yang digambarkan secara visual dalam pamerannya ini, telah merangkum definisi surga secara epistimologis, spiritual sekaligus keberpihakan dia, tentang konstruk kultural timur yang dirasa. Tematik ini, diambil dari upaya mematut diri, memahami begitu banyak hal terjadi yang “menderitakan” manusia diluar diri Magda. Ruang-ruang ketakutan, rasa sedih dan empati melihat begitu banyak kesakitan, rasa skeptis menjadi pengalaman batin yang mengkristal, kemudian, oleh Magda digambarkan segera setelah proses kontemplatif satu persatu dibangunnya obyek, warna, dll berupa kode-kode visual. Magda sedang mentransfer rasa internalnya.
Simbol Kertas Tabularasa, yakni konsep tentang ruang kosong dan bersih diambil Magda sebagai sebuah pencarian kembali ke ruang intim internal. Mengasah diri, meminjam bahasa anak-anak yang tulus dan naif, mengarungi pengalaman masa kecil, bahwa sebenarnya jiwa dan hati ditulis oleh “pengalaman-jiwa” di “kertas hati”. Kekecewaan, kesedihan, rasa bersalah yang mendera, selayaknya mampu untuk ditulis ulang. Menghapus pengalaman “buruk”, menjadi kertas kosong yang baru. Lambang ini, di kanvasnya bisa saja imej anak kecil yang bermain, paras wajah tanpa dosa, tatapan mata tulus, ruang-ruang sepi yang “menyejukkan”. Filosofi Tabularasa perwujudan surga, bagi Magda, yakni kertas yang selalu siap ditulis setiap hari dan bisa dihapus untuk dievaluasi.
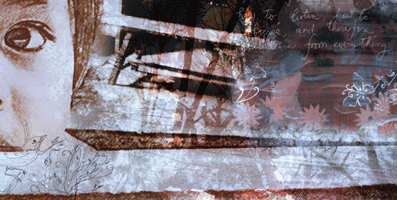
Melihat dengan Murni
Ada juga, ikon rumah yang dekat dengan pengertian tentang keluarga. Sejak awal peradaban timur, konon keluarga adalah komos kecil yang menjadi tolok ukur adanya chaos atau ketertiban mampu terjaga. Budaya timur, menjelaskan jika inti semesta adalah diri, atau jagad kecil. Dengan demikian, keluarga, atau batih terkecil, kelompok terinti sebagai penentu, adalah surga, pusat kebahagiaan. Banua tengah, di budaya Batak, memberi persepsi secara kultural, kita berekspresi secara sosial dengan anggota-anggota keluarga terkecil sebagai fundamen utama. Keluarga ini, dalam karya Magda, bisa berwujud simbol bangunan rumah tradisional.
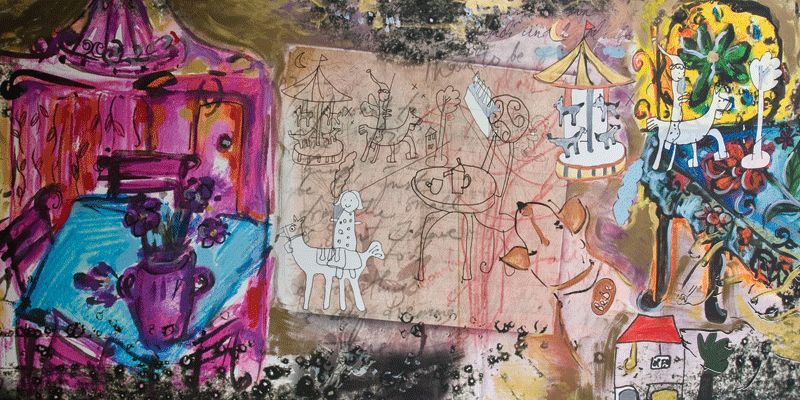
Rumahku Impianku
Yang lainnya, simbol piring, adalah sebuah reproduksi nilai-nilai kultural yang mengakar. Keyakinan lama di tradisi, mengatakan bahwa makanan adalah berkah yang disyukuri, sebuah kenikmatan atas rezeki bahkan sesajen untuk para pendahulu kita (ancestor), pada upacara-upacara mistis tertentu. Makanan, dan tangan telanjang ketika proses makan bersama adalah sebuah simbol tentang bagaimana rasa syukur diekspresikan secara langsung dengan berbagi. Lambang-lambang ini, sering muncul bersama, baik melalui gambaran piring, tangan, bentuk dan jenis makanan serta proses ritual bersama.

Penuhilah Maka Engkau Akan Dipenuhi
Di kanvas lainnya, goresan-goresan dari hasil kerja teknik etsa, sketsa tangan, atau imej-imej photo yang di kombinasikan kepiawaian desain graphic di komputer lantas dicetak digital, membentuk simbol kalender kuno. Mewakili konsep ruang dan waktu, sebagai representasi penghormatan ke budaya timur. Kenyataannya, bahkan sampai saat ini, hitungan ruang dan waktu kuno, masih menjadi hal yang “mengikat” pada generasi modern. Kalender, sebagai sebuah pertanda mistis, mampu mengidentifikasi waktu dan tempat mana yang akan menjadi “hari-baik” atau “hari buruk” melakukan hajatan-hajatan komunal atau aktifitas internal sebagai standar identitas keunikan dan perasaan bahagia karena memiliki lokalitas kosmos tersendiri.
Konsep figur ibu, yang muncul di kanvasnya, dengan sosok orang tua bermata bijak, atau seringkali, sosok perempuan, yang diambil siluetnya, adalah harapan Magda untuk sebuah kekuatan, justru di dalam kelemahan, kejujuran meski telah renta dan lemah. Simbol ibu, semestinya sudah kita mahfum, adalah kosmos tentang lambang kesuburan, memberi tak pernah meminta, seperti bumi dan air yang menyediakan kasih dari sumber yang tanpa habis, seperti cinta yang selalu terberi di tangan sang ibu. Surga ditelapak kaki ibu, di budaya kita, adalah ungkapan yang bahkan tak usah difikir, cukup dirasakan. Surga menjadi demikian lekat di kosmos diri.

Perempuan Seorang Ibu
Mungkin, ini sebuah harapan yang dituturkan oleh Magda, dengan pameran Unforgotten Paradise ini rasa syukur, untuk ditularkan pada kita semua. Sepahit apapun hidup ini, masih terasa indah untuk tetap dilanjutkan.
Bambang Asrini Widjanarko
Kurator
•••










 1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto
1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto 2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong
2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong 3. Hurufontipografi | Surianto Rustan
3. Hurufontipografi | Surianto Rustan www.underconsideration.com
www.underconsideration.com
